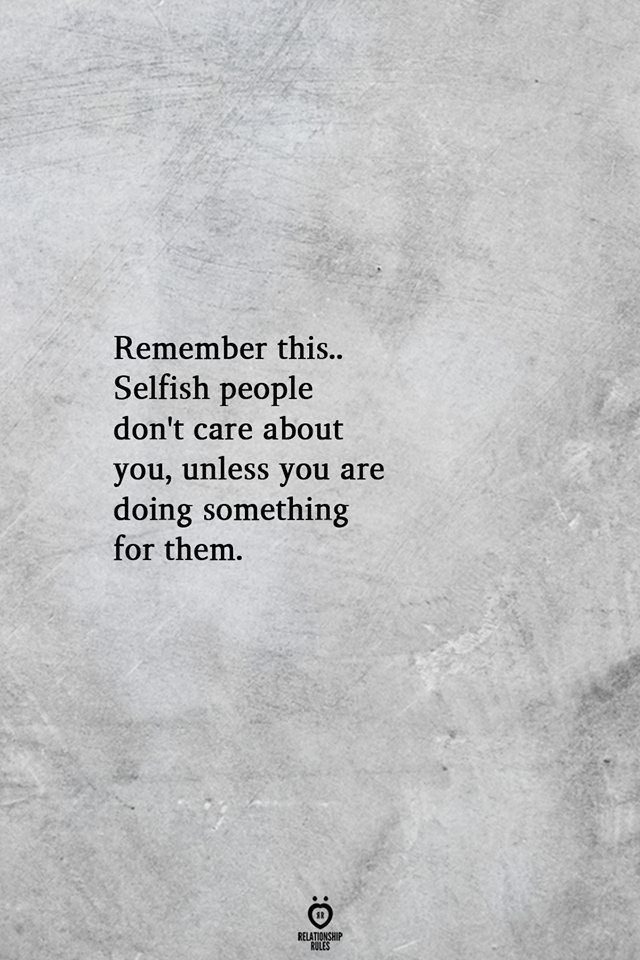Pinkie Promise: 10. Tawaran
11 Februari 2025 in Vitamins Blog
****
Perlahan, kedua kelopak mata milik Tiara terbuka sempurna setelah ia mengerjapkannya beberapa kali hingga kilat dari bola mata hazel miliknya nampak membulat indah lantas menatap dengan sorot pandang nanar pada langit-langit kamar yang ditempatinya melewati malam panjang untuk kesekian kalinya.
Biasa saja, kosong dan hampa.
Pagi itu terasa sangat hening dan lelah yang menyeruak dalam diri Tiara bermuara pada hela nafasnya yang panjang berulang dan perlahan. Tiara kembali memejamkan matanya, tubuhnya seakan hanya mampu berpasrah diri pada keadaan yang sedang dialaminya. Semalam ketika Wilona menawarkan kepadanya untuk beristirahat karena hari sudah larut malam, Tiara menuju kamar singgahnya dengan langkah yang melemah karena sungguh tak ingin dan berat hati namun pada akhirnya ia tetap memilih patuh karena tak ingin mengecewakan Wilona yang selalu berbaik hati dan begitu peduli kepadanya.
Selama ia melangkah dengan lunglai menuju kamar, di balik punggungnya, sebenarnya Tiara bisa merasakan sorot pandang sepasang mata yang menatapnya dengan tajam dan menusuk dari Wildan yang tanpa jeda tengah mengulitinya bahkan Tiara seakan bisa mendengar suara hati Wildan yang seakan meneriakinya, “Dasar, perempuan merepotkan!”.
Sepanjang hari sejak kejadian munculnya Norman di halaman belakang rumah, Wildan memang terlihat dipenuhi amarah yang tak kunjung mereda, ia uring-uringan seperti perempuan yang mengalami kram perut menyambut siklus menstruasi bulanan. Jelas sekali nampak dari caranya bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk dan Wilona berusaha sepanjang waktu meredakan Wildan seperti seorang Peri Bijaksana yang menangani Manusia Serigala. Tiara sendiri memilih bersikap acuh tak acuh, namun di dalam hatinya, Tiara ingin hari yang panjang dan menyebalkan itu segera berakhir. Ia ingin segera bertemu malam atau akan lebih baik jika tiba-tiba saja saat dirinya berbaring, maka ia terbangun dan kembali ke dunia yang lebih ia kenal.
“Kalau kau tidak mau makan, sebaiknya kau katakan saja, tidak ada yang diuntungkan di sini jika kau menjaga diri dari kelaparan. Katakan saja kau tidak mau makan daripada kau mengaduk-aduk makanan tanpa alasan seperti itu! Menyebalkan!” hardik Wildan tanpa menatap Tiara yang tertegun dan bergidik ngeri dengan sikap dinginnya.
“Tiara, apa makanannya tidak sesuai dengan seleramu?” tanya Wilona dengan lebih lembut dan menatap mata Tiara dengan penuh harap menunggu jawaban.
Tiara menggeleng cepat lantas segera bergegas memakan hidangan makan malamnya dengan lahap, “Maafkan aku, aku hanya sedikit melamun.”
Wilona terlihat lega, sedangkan Wildan nampak tak senang hati dengan sikap Tiara.
Tiara berdecak kesal mengingat kejadian semalam ketika mereha bertiga tengah menikmati makan malam bersama.
“Haaah, sepertinya aku masih harus terima kenyataan bahwa pagi ini pun aku masih terjebak di dunia asing ini.” ucap Tiara lirih sembari menghela nafas berkali-kali.
Tiara yang terlalu tenggelam dalam ruang pikirannya yang kalut dan terlalu mengingat-mengingat kejadian hari kemarin, membuatnya tak sadar akan sekitarnya. Sosok seorang manusia sejak beberapa waktu berlalu tengah duduk diam di kursi kayu kecil yang tersedia di sudut kamar yang agak remang karena tirai jendela di dalam kamar tersebut masih tertutup rapat dan cahaya pagi di luar sana belum sepenuhnya merangsek masuk di celah-celah tirai. Manusia yang duduk manis dengan senyum tersungging di wajahnya, memilih diam tanpa ada niatan sedikitpun mengganggu kependiaman Tiara yang berlangsung beberapa saat. Ia memilih mengamati saja setiap gerak-gerik Tiara.
Setelah merasa bosan menghela nafas berulang kali dan menyadari langit-langit kamar takkan berubah meski dirinya terus menatap ke atas dengan penuh selidik, Tiara memilih bangkit dari pembaringan, duduk di tempat tidur lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya beberapa kali lantas mulai menepuk-nepuk ringan pada kedua pipinya.
“Kalau kau terus menepuk pipimu seperti itu, aku jadi khawatir itu akan menimbulkan bekas merah yang tak wajar. Seingatku, sudah kuingatkan kemarin, tapi sepertinya tak kau hiraukan.”
Mendengar suara yang tak asing namun tak percaya berasal dari dalam kamar yang ditempatinya, tubuh Tiara segera terbujur kaku dan sepasang matanya terbelalak karena terkejut. Perlahan ia menoleh ke arah sumber suara dan sesuai dugaan di dalam kepalanya maka ia tak salah tebak bahwa yang bicara tadi adalah Norman.
Tapi, bagaimana bisa Norman sekarang berada di kamar?
Apakah saat ini Tiara harus marah karena seorang pria asing dengan lancang memasuki kamarnya?
Atau, haruskah Tiara menyambut dan mengucapkan selamat pagi?
Norman kembali tersenyum ramah ketika mendapati Tiara telah menyadari keberadaannya dan sekarang sedang menatap kepadanya dengan penuh tanda tanya yang sangat jelas terpancar dari sorot matanya. Kemudian sebagai seseorang yang terlahir sebagai pribadi yang sangat peka, Norman segera meminta maaf karena telah lancang masuk di dalam kamar tanpa izin.
“Oh, maafkan aku karena tiba-tiba berada di sini. Aku hanya khawatir padamu setelah kejadian kemarin.” ucap Norman penuh senyum bersahabat lalu membuka tirai dengan sekali jentik dengan jari tangannya.
Pada saat itulah Tiara yang tadinya hanya melihat sosok Norman dalam suasana remang hingga seperti siluet, kini bisa melihat sosok Norman dengan jelas dan sinar matahari pagi yang merangsek masuk setelah tirai terbuka begitu mendukung pancaran indah dari sosok Norman yang harus Tiara akui bagai pangeran tampan dari negeri dongeng.
Tanpa sadar, wajah Tiara merona karena tersipu malu lantaran mengagumi keindahan di depan matanya, sosok pria tampan yang memanjakan kedua matanya.
“Kurasa karena kau tak mengindahkan peringatan dariku mengenai menepuk pipi, sekarang wajahmu jadi memerah.” ucap Norman sembari cekikikan kecil.
Tiara terkesiap, ia tak siap dengan celetukan Norman yang terkesan polos hingga dirinya menjadi malu karena Tiara sangat tahu wajahnya memerah sebab terpesona bukan akibat ia menepuk-nepuk halus pada kedua pipi di wajahnya. Tiara bahkan lupa untuk waspada dengan kehadiran Norman yang secara tak masuk akal tiba-tiba berada di dalam kamarnya tanpa izin.
“Ini karena aku terkejut! Juga karena sinar matahari!” Tiara berdalih dengan cepat dan memalingkan wajahnya agar Norman tak bisa memperhatikan wajahnya yang masih merona malu dengan teliti.
Tanpa aba-aba, Norman menjentikkan kembali jemarinya dan kali ini membawa tubuhnya dalam sekejap menghilang dari kursi dan berpindah tempat duduk di tepi tempat tidur milik Tiara, tepat disampingnya.
Tak hanya itu, Norman bahkan mendekatkan wajahnya di depan wajah Tiara seakan memastikan sesuatu.
“Benarkah wajahmu memerah karena terkejut dan paparan sinar matahari?”
Tiara tak siap dengan wajah Norman yang begitu dekat padanya, ia kembali memalingkan wajahnya ke arah lain namun Norman kembali mengejar wajahnya.
“Hentikan!” pekik Tiara lantas sedikit mendorong ringan tubuh Norman untuk menciptakan jarak di antara wajahnya dan wajah Norman.
“Maafkan aku, apa aku membuatmu tak nyaman?” tanya Norman lirih dengan memasang raut wajah yang lugu.
Pada saat itulah Tiara memperhatikan lebih saksama sosok Norman yang terlihat berbeda dari hari kemarin. Norman mengikat rambut cokelat bergelombang miliknya seperti ekor kuda dan itu terlihat lebih menegaskan garis-garis wajahnya yang maskulin dan meskipun Norman seorang pria yang tubuhnya tak lebih kekar dari Wildan disertai rambut panjang bergelombang sebahu yang terkesan feminim didukung oleh bibirnya yang tipis berwarna cerah, tapi ia tetap menguarkan aura pria yang mendebarkan untuk dipandang.
Tiara menelan ludahnya dan mengosongkan pikirannya secepat kilat yang terlalu banyak membuat penilaian terhadap Norman secara fisik. Ia merasa telah menjadi perempuan rendahan ketika dirinya malah sibuk mengagumi sosok pria di depan matanya yang sejak tadi bahkan menatap wajahnya dengan lugu tanpa kilat berbahaya sedikitpun.
Pria yang tampan dan baik hati.
“Apa kau baik-baik saja? Apa kau keberatan aku berada di sini?” tanya Norman menyadarkan Tiara dari renungannya.
Tak ada jawaban, Tiara bahkan tak tahu apa ia harus berkata iya atau tidak atas pertanyaan yang dilontarkan Norman. Saat ini Tiara hanya merasa senang Norman mendatanginya yang sebelumnya merasa kosong dan hampa. Namun, Tiara juga merasa tak pantas untuk menyatakan bahwa dirinya tak keberatan atas kehadiran Norman.
Bagaimanapun juga Norman masih terhitung pria asing, kan?
“Sebenarnya kehadiranku kemari karena aku ingin membawamu melihat-lihat Kota Thames, itupun kalau kau tidak keberatan.” ucap Norman dengan nada lembut.
“Membawaku?” Tiara melayangkan pertanyaan retorika sembari tanpa sadar menggenggam bandul Ratnaraj yang dikalunginya.
Norman yang teliti menangkap setiap gerak-gerik Tiara tersadar bahwa Tiara sedikit menunjukkan kewaspadaan terhadap dirinya.
“Maafkan aku, tapi aku sungguh tidak punya niat jahat sama sekali seperti menculik ataupun mengelabuimu dan aku minta maaf jika caraku terkejut saat menyadari bandul Ratnaraj ada pada kalungmu kemarin membuatmu khawatir akan diriku.” terang Norman perlahan dan masih dengan nada yang lembut sehingga terasa nyaman menelusup di telinga Tiara.
Tiara segera melepaskan genggamannya pada bandul kalungnya dan meskipun ia ingin mengucapkan sepatah kata apapun, lidahnya terasa kelu dan bibirnya terasa kaku serta ia merasa tak tahu harus berkata apa.
“Kuakui aku memang terkejut, namun aku tak bermaksud buruk padamu. Kau boleh tidak percaya padaku, kau punya hak untuk itu.” terang Norman lagi, namun kali ini ia mengambil jeda yang sedikit panjang sebelum melanjutkan kata-katanya seperti memberi waktu untuk Tiara berpikir ulang mengenai dirinya.
“Tapi aku akan tetap keras kepala menawarkan diri untuk mengajakmu berkeliling Kota Thames. Apa kau tidak bosan hanya berada di rumah tua ini dan hanya bersama dengan si kembar Wildan dan Wilona?”
Norman melemparkan pertanyaan kepada Tiara dengan nada yang sedikit menggoda disertai raut wajah jenaka yang membuat Tiara menurunkan kewaspadaan. Norman yang merupakan pria asing seakan tahu dengan baik cara mengambil hati Tiara. Kali ini Norman memilih bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di tepi ranjang dengan tegap serta mengulurkan salah satu telapak tangannya dihadapan Tiara.
“Bagaimana nona cantik, maukah kau berjalan-jalan denganku? Akan kutunjukkan indahnya Kota Thames dan kau akan suka berbagai menu makanan yang tersedia di perjalanan, tentu saja aku yang membayar semuanya untukmu.”
“Aku bahkan baru bangun tidur dan belum sedikitpun bangkit dari tempat tidurku, aku belum membersihkan diri, merapikan diri, aku tidak dalam keadaan siap sedikitpun untuk kemana-mana dan kau begitu percaya diri menawarkan padaku untuk ikut berkeliling kota?” celetuk Tiara yang terdengar bersungut-sungut manja.
Norman tersenyum tipis, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas tempat tidur untuk menumpu tubuhnya yang sedikit membungkuk condong ke depan agar wajahnya dapat berada di posisi yang sejajar dengan wajah Tiara.
“Nona cantik, apa kau meragukan kemampuanku? Jangan khawatir, ada aku di sini, kau akan siap dalam sekejap.”
Setelah mengucapkan kata-katanya yang sangat mendominasi, Norman menegakkan tubuhnya dan kembali menjentikkan jemarinya hingga Tiara yang masih terkesima dengan sikap Norman yang memangkas jarak di antara mereka, tak sadar bahwa penampilannya telah berubah dari menggunakan pakaian kemarin yang lusuh, kini menggunakan pakaian yang lebih indah dipandang serta tubuhnya terasa segar seolah-olah Tiara baru saja selesai menikmati kolam air hangat yang menyegarkan.
Tiara bangkit dari tempat tidurnya dengan cepat dan berjalan terburu-buru menuju cermin di sudut kamar seukuran tubuh manusia sehingga ia bisa melihat keseluruhan penampilannya yang telah berubah.
Tiara tak bisa menyembunyikan perasaan takjub ketika mendapati dirinya telah berpenampilan lebih cantik dari biasanya. Ia menggunakan gaun rumbai selutut berwarna putih dengan garis tepi berwarna emas dan rambutnya yang tergerai kini telah diikat seperti ekor kuda dengan pita berwarna kuning emas senada dengan garis tepi pada gaunnya. Kalung berbandul Ratnaraj miliknya pun tetap menghiasi lehernya yang jenjang dan ia begitu menyukai sepatu bot berwarna cokelat kulit yang menghiasi tungkai kakinya. Tiara lagi-lagi menepuk ringan pada kedua pipinya sebagai wujud rasa tak percaya atas apa yang terjadi padanya.
“Sudah kubilang jangan lalukan itu pada pipimu, nanti akan memerah dan terlihat buruk di wajahmu yang cantik.” tegur Norman lirih yang telah berdiri dekat di belakang punggungnya, seakan tengah berbisik di telinganya.
Tiara terkesiap karena merasakan sensasi yang tak biasa pada tengkuknya sehingga ia segera beranjak menjauh dari tubuh Norman dan mencoba mengalihkan pembicaraan.
“Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi buktikan janjimu bahwa akan banyak hal menarik yang kutemukan di sana.” celetuk Tiara.
“Percayalah padaku, nona manis.” ucap Norman lirih dan kembali memangkas jarak yang telah diciptakan Tiara, kali ini Norman menghela tubuh Tiara agar mendekat padanya. Satu tangannya melingkar di pinggang Tiara, mengetatkannya hingga Tiara semakin dekat berada dalam dekapannya tanpa mempedulikan wajah Tiara yang semakin merona hingga Tiara dapat merasakan kedua telinganya terasa panas seakan terbakar oleh percikan api tak kasat mata. Kemudian satu tangannya lagi mulai terangkat di udara dan dengan sekali jentik pada jemarinya, Norman membawa Tiara pergi, sosok mereka berdua telah menghilang dari ruang kamar menyisakan keheningan di dalam kamar yang kosong tak berpenghuni.
****
Dari pintu kamar yang beberapa saat lalu sedikit terbuka tanpa disadari oleh Tiara, tampak sepasang bola mata yang tak sedikitpun melepaskan pandangannya untuk mengawasi setiap hal yang terjadi diantara Tiara dan Norman meski tak sedikitpun ingin merangsek masuk ke ruangan kamar untuk merusak suasana, hanya cukup mengamati.
“Sedang apa kau?” tanya Wildan dengan nada dingin dan tiba-tiba yang mengejutkan Wilona hingga kedua pundaknya sedikit berjingkat. Wilona telah menjadi pengintip handal di celah pintu kamar saat Tiara sedang bersama Norman dari awal Tiara terbangun dari tidurnya sampai Tiara san Norman menghilang dari pandangan.
“Kau mengejutkanku, aku hanya memastikan keadaan Tiara.” ucap Wilona dengan keraguan yang terlihat jelas dari bahasa tubuhnya.
Wildan yang merasa ada yang aneh, dengan gusar mendorong tubuh Wilona agar menepi dan langsung membuka lebar pintu kamar yang ditempati Tiara lantas menyadari bahwa Tiara tidak ada di dalam kamar.
“Di mana perempuan itu?!” tanya Wildan tegas kepada Wilona yang hanya bersandar dengan santai di daun pintu. Wilona memutar kedua bola matanya dengan malas, terkadang ia lelah untuk menanggapi kelakuan saudara kembarnya yang selalu tergesa, gusar dan dipenuhi amarah.
“Wilona?!” tuntutnya lagi menghampiri Wilona dan merapatkan tubuhnya untuk menghimpit Wilona hingga Wilona merasa terdesak oleh sikap Wildan.
“Bisa tidak kau sebentar saja tidak arogan? Aku hanya membiarkannya pergi bersama Norman.” terang Wilona yang membuat Wildan tersentak.
“Apa katamu?!” Wildan meremas kedua bahu Wilona dengan kesal.
“Wildan, mengertilah, aku membiarkannya bersama Norman karena aku melihat Tiara merasa nyaman dengannya. Apa kau tidak kasihan pada Tiara? Ia bahkan sedang dalam situasi sulit, tentu saja Tiara harus berpikir jernih dengan takdir yang harus dijalaninya. Ia harus membunuh, dan tentu itu tidak mudah. Andai saja kau memliki sedikit empati, maka kau akan mengerti.” terang Wilona dengan lemah lembut dan tak gentar sedikitpun meski Wildan menghadapinya dengan gusar.
Kata-kata Wilona membuat Wildan merasa terintimidasi. Sudah sejak lama ia selalu mendengar kata-kata semacam itu, seolah dirinya adalah makhluk tak berperasaan, tak punya empati, simpati, dan sejenisnya.
Wildan bahkan meragukan dirinya, apakah dirinya bukan manusia sampai harus mendapati julukan sebagai pribadi yang arogan terus menerus?
“Cih! Aku lupa kau lebih peduli dengan Norman.” ucap Wildan dengan sinis dan dingin lalu berlalu dari hadapan Wilona yang hanya bergeming tak ingin membantah.
****
Bersambung~

PROSA HATI: #7 Obrolan Wanita Dewasa
6 Agustus 2024 in Vitamins Blog
Pada dasarnya manusia itu bisa berubah,
Manusia bertumbuh dan berkembang.
Tidak hanya tentang lahir sebagai sosok bayi mungil tak berdaya yang bertahun-tahun kemudian menua dimakan waktu.
Pun ketika telah banyak lembaran-lembaran drama kehidupan yang dilewati, manusia yang tadinya naif pun tiba-tiba mampu mati rasa dan realistis hingga ironis.
Malam ini kau dan aku tertawa getir setelah obrolan panjang yang membuat kita larut dalam perasaan-perasaan tak tergambarkan.
Tentang kau yang berhenti berjuang dan aku yang menurutmu begitu kuat tapi dengan keras kepala kusebut diriku bodoh.
“Obrolan kita sepertinya berat yaa?” celetukku.
Tawamu renyah di telingaku dan sedikit berpikir keras kau mencari kata-kata yang tepat untuk menanggapiku, “Definisi sudah berumur, benar-benar berat, haha.”
“Ingat nggak dulu kita bercerita tentang buku komik yang kita baca, crush yang menginspirasi bikin komik serial cantik?” celetukku lagi.
Tawamu kembali terdengar renyah, perpaduan rasa segan membuat keributan di kedai kopi yang sedang hening dan wujud getirnya asa yang belum sepenuhnya melegakan hatimu.
“Dan sekarang kita bicara sok bijaksana, saling bergaya memberi penghiburan padahal sama aja bobroknya.” lanjutku.
Keheningan membentang beberapa saat lalu kau berucap lirih menanggapiku,
“Rasanya tidak ada apa-apanya aku daripada dirimu, tapi kamu selalu terlihat baik-baik aja bahkan orang lainpun bisa sampai iri dengan dirimu.”
Aku mengaduk-aduk cappuccino dihadapanku dan senyumku getir sebab aku bukannya tidak tahu bagaimana orang lain memandang hidupku.
Barangkali dunia pun bisa menghakimiku, jika aku berteriak dan mengangkat tanganku karena menyerah bertahta di menara istana antah berantah yang indah.
Tapi aku bukannya tak pernah ingin menyerah secara egois tanpa peduli seisi dunia menghujatku, aku hanya merasa tak ditakdirkan menyerah.
“Menurutmu kenapa aku merespon pilihanmu dengan kata-kata penuh dukungan, aku bahkan tidak bertanya kenapa kau menyerah?”
Kau terdiam karena aku bergaya penuh teka-teki, lantas aku melanjutkan kembali penjelasanku tanpa menunggu tanggapanmu.
“Jika aku bertanya alasanmu, berarti aku nggak percaya seutuhnya dengan pilihanmu sedangkan aku sangat yakin kau membuat pilihan yang tak mudah hingga di tahap ini.” jawabku tegas.
“Aku merasa sangat lemah, dibandingkan kamu sebenarnya aku nggak ada apa-apanya.”
Aku mengernyitkan dahi kesal mendengar pernyataan sumbangmu,
“Kamu tuuh hebat, kamu mengambil keputusan yang berat dan kamu bukan menyerah tapi kamu berani menutup sebuah cerita untuk membuka cerita yang baru lagi nantinya. Padahal Allah bisa saja menggagalkan pilihanmu tapi coba renungkan kenapa semua ini berhasil sampai akhir? Konsekuensi pasti ada di setiap pilihan, tapi selalu ada solusi kedepannya, paham tak?”
Kau hanya mencibirkan bibirmu dan aku sedikit lega melihatmu bisa bersikap konyol menyebalkan setelah sekian waktu kau tampak seperti perempuan anggun menyedihkan dalam kisah-kisah novel drama rumah tangga.
Pikiranmu sedang kesulitan mencerna apa yang kurasakan setelah semua perbincangan panjang penuh drama telenovela.
“Aku nggak tahu apa aku harus salut atau khawatir sama dirimu.” celetukmu tiba-tiba.
Tidak ada jawaban dariku untukmu, aku tidak perlu menegaskan apapun.
Yang aku tahu, sekarang aku tidak terlalu suka perbincangan penuh spekulasi terhadap apa- apa yang kujalani.
Rasanya meski pelukku akan selalu kuberikan bagi orang-orang yang tengah terserang pilu, aku tak suka orang-orang menatap iba dan menawarkan pelukkan yang sama.
Jadi, jangan berusaha membalas apapun, dan berterima kasih saja aku ada menemanimu saat kau perlu menguatkan dirimu atas pilihan hidupmu.
Tentangku, biar aku sendiri yang menanganinya.
XOXO,
ROSETTA

PROSA HATI: #6 RENJANA
6 Mei 2024 in Vitamins Blog
Kau bagai renjana di dalam bejana. Terjebak asa bagai candu yang membuatku pilu. Pada pertemuan tak terencana, sorot matamu yang redup memporak-porandakan buntalan rindu yang kupendam sendiri.
Kau bertahan terisak dengan belati yang menghujam riak tawamu, terhimpit sendu yang kucandu dalam khayalku, lebur dalam pelukan perayaan kau dan aku di dalam mimpiku.
Wahai pujangga yang merayu dengan cinta yang semu,
Sedang apa kau dengan bait-bait rindu yang kau bisikkan kepadaku?
Aku kalah padamu, bahkan meski aku bersumpah menghujatmu seumur hidupku, nyatanya aku berakhir dalam dekapmu kala jemari bertaut tak terhalang jarak dan waktu.
Purnama malam itu membulat sempurna, menerangi kau dan aku yang tengah berdiam diri saling membisu di antara ribuan bising yang hiruk pikuk.
Kau membatu bisu, tak pandai bicara layaknya diksi-diksi indah dalam kisah-kisah imajinasimu sendiri, sedang aku dalam kependiamanku tengah terlampau muak menanti penghiburan yang ingin kudengar hingga aku berdecak kesal.
Menyadari kekesalanku kau meraih tangan kananku dan mengecup punggung tanganku tanpa peringatan hingga aku terkejut dan secara impulsif menarik tanganku menjauh dari bibirmu yang terasa dingin.
Aku ingin pergi, berlari menjauh darimu secepatnya karena ego yang menguasai diriku.
Aku ingin kau memohon padaku, merangsek memelukku dan menahanku agar tak pergi darimu.
Seakan mampu membaca inginku, kini aku tenggelam dalam dekapanmu yang hangat. Kau melarangku pergi dengan terbata-bata, begitu lirih di telingaku.
Rupanya kau tak pandai bicara, tapi kau manusia paling peka dengan semua egoku.
Jemarimu yang kokoh menyapu bibirku yang sedikit basah dan dingin, sedang tanganmu yang lain menghela pinggangku agar merapat padamu.
Dalam sekejap aku bisa merasakan kehangatan yang asing pada indera pencecapku, berpadu aroma tembakau yang berasal dari dirimu.
Untuk sesaat waktu terasa terhenti, di bawah pohon rindang pada bangku taman yang menjadi saksi bisu pertemuan kau dan aku, hanya ada rindu yang berakhir temu.
Aku lupa siapa aku, kau abai siapa kau. Kita tak peduli apapun dan untuk sesaat kau berbisik ditelingaku,
Kau renjana-ku selamanya.
XOXO,
ROSETTA

PROSA HATI: #5 Pengakuan
22 Maret 2024 in Vitamins Blog
“DIA BUKAN ANAK SUAMIKU!”
Ucapnya cepat dan tegas lantaran tak ingin aku melanjutkan seluruh kalimat manis penuh pengharapan bait-bait doa nan suci dari bibirku.
Aku tengah mendoakan kebaikan atas rumah tangga yang dia bina, sebuah rasa suka cita atas kehadiran buah hati yang menahun dinanti-nantikan.
Dan ketika ia mengucapkan kalimatnya, aku hanya bisa termangu dan bergeming sepersekian detik. Sorot mataku menatap lekat ke dalam sepasang manik matanya yang meredup dan menyimpan gelap, didukung semburat amarah tersembunyi yang nyaris menguar tanpa tahu malu.
“Apa katamu?” gumamku lirih tak percaya atas apa yang kudengar.
“Aku pernah bilang padamu kan? kalau kau muak dengan lelakimu, kau coba saja pria lain di luar sana, begonya malah aku yang melakukan itu!”
Nadanya terasa getir ketika ia mengucapkan kalimatnya lagi, namun disertai kelegaan bahwa ia akhirnya bisa menemukan manusia lain untuk mengakui dosanya yang tersimpan rapat hingga menyiksa hati nuraninya selama ini.
Seharusnya aku tidak kaget, ia terbiasa bersikap liar karena itulah aku selalu maklum atas kata-katanya yang cenderung terlalu bebas dan tak punya adab sedikitpun.
Kupikir aku beruntung, sebanyak apapun ia menelusupkan pandangan-pandangan yang tak berbatas mengenai sentuhan pria, namun sebagai perempuan yang tak menganggap sentuhan fisik adalah hiburan, semua yang ia katakan hanyalah angin lewat bagiku.
Ah, mungkin jika boleh aku berkhayal jauh, aku hanya ingin bertemu pria yang mendengarkan cerita konyolku, menepuk punggung telapak tanganku dan berkata, “Kau perempuan yang hebat.”
Tak sedikitpun aku teracuni oleh kata-kata liar yang ia telusupkan dalam memoriku, tentang mendulang anggur dari pria asing di tengah pertemuan singkat saat hidup terasa penat.
Untuk beberapa saat aku hanya bisa terdiam dengan pikiranku yang seketika kosong lantas kependiamanku berakhir dengan reaksi mual yang menggelegak nyaris membuatku ingin muntah, sebab sekelibat bayang-bayang asing menjijikkan tak menyenangkan mulai memaksaku berimajinasi.
Kutatap bola mata jernih dari bayi mungil nan suci yang tersenyum ceria menatapku dari pangkuan ibunya.
Hatiku pilu membayangkan malaikat kecil nan lugu yang tak tahu apapun itu.
Hatiku tersayat membayangkan perasaan pria baik-baik yang sudah pasti mengira malaikat kecil di hadapanku ini adalah buah hati dari jatuh bangun drama cinta yang mereka bangun dan yang dinantikannya selama ini.
Hatiku terenyuh membayangkan perempuan dihadapanku ini menanggung dosanya dengan rongga dada yang terhimpit sesak seumur hidupnya.
Entah kenapa aku jadi mempertanyakan bagaimana ia bisa menatap mata prianya setiap hari dengan dosa yang menjelma dalam pangkuannya?
Aku frustasi, semua kompilasi rasa itu membuatku mual. Aneh, dia yang berbuat aku yang merasa mual tak berdaya.
Aku menarik nafasku, menghela dengan hati-hati sembari menenangkan batinku yang bergejolak. Aku berusaha menerima fakta yang tak sanggup diterima oleh hati nuraniku dengan sekuat tenaga lalu kutemukan kedua bola matanya meredup setelah beberapa waktu menatapku dengan nanar.
Ah, jangankan sumpah serapah, untuk menghakiminya aku sudah tak tega, memberi penghiburan pun aku tak mampu.
Hatiku luluh seketika, kuraih salah satu telapak tangannya yang bebas tak bertugas merangkul tubuh si bayi mungil , namun lidahku kelu tak mampu berkata-kata apapun.
Di dalam benakku, aku tengah bicara sendirian, tentang aku yang takkan sanggup menjadi dirinya dan secara egois aku diam-diam bersyukur dan memetik saripati kehidupan yang dia alami.
Sudah, aku tak punya apapun untuk menguatkanmu, lantas secara curang aku hanya memikirkan diriku sendiri dan terserah bagaimana kau menjalani sisa hidupmu.
XOXO,
ROSETTA

Pinkie Promise: 9. Norman
1 Desember 2023 in Vitamins Blog
****
Semilir angin sayup-sayup terasa membelai lembut wajah mulus Tiara yang terlihat redup sembari kedua mata hazelnya menatap lurus pada sebuah batu nisan yang berdiri kokoh di hadapannya. Bentangan langit pagi yang menaunginya tidak jauh berbeda bahkan begitu serupa dengan langit yang meneduhkan dunia tempat ia tinggal nun jauh di sana. Langit yang sama, biru cerah dengan semburat kuning keemasan dari sang surya yang berpendar malu-malu, juga beberapa gumpalan awan putih yang berarak di sana-sini . Tidak ada yang terasa berbeda, suasana pagi yang terasa sama seperti pagi yang biasa dilewati Tiara di dunia sebelumnya, seakan ia tak pernah pergi jauh ke dunia asing yang sekarang ditempatinya. Pun tidak ada yang menarik dari batu nisan yang nampak masih kokoh dan tampak bagus lantaran baru beberapa hari lalu ditancapkan untuk menandai tempat bersemayam seorang wanita tua berhati mulia yang namanya kini abadi dalam ukiran yang dipahat dengan indah oleh ahlinya di permukaan batu tersebut.
Tiara tersenyum kecut, tiba-tiba saja ia teringat momen semalam bersama Wildan dan Wilona yang menyatakan bahwa dirinya ditakdirkan untuk mengakhiri riwayat hidup Marvin, penyihir yang tamak hingga gelap mata mengotori tangannya dengan membunuh kedua orang tua Wilona dan Wildan demi kekuasaan yang didambakannya. Kendati hati nurani Tiara ikut merasa tersayat setelah mendengar kisah derita memilukan yang disampaikan oleh Wilona dan Wildan, namun ia merasa berat menerima kenyataan bahwa ia ditakdirkan untuk membunuh seseorang meskipun orang tersebut memang layak untuk dibunuh karena dosa-dosanya.
Tapi, memangnya siapa Tiara berhak menjadi hakim bagi kehidupan seseorang?
Tiara kembali menatap lekat-lekat pada batu nisan yang sedari tadi dipandanginya dengan rasa iba bercampur amarah. Itu adalah batu nisan milik Bibi Meredith yang dianggapnya bertanggungjawab atas takdir aneh yang menimpanya. Semalam setelah mendengarkan Wilona dan Wildan dengan saksama hingga sampai pada berita mengenai takdir Tiara untuk membunuh Marvin, maka Tiara segera bergeming untuk beberapa saat sembari amarah mulai membuncah dalam dirinya sebagai bentuk penolakan mentah-mentah terhadap apa yang disampaikan Wilona dan Wildan. Tiara teringat semalam ia benar-benar merasa kesal hingga tanpa pikir panjang Tiara bermaksud untuk melangkah pergi dari rumah bahkan ingin kembali ke Taman Rosetta di mana ia pertama kali muncul ke dunia yang aneh ini dan berharap bisa segera kembali ke dunianya sendiri entah bagaimana caranya, ia pikirkan nanti setelah berhasil merangsek pergi dari rumah tersebut. Semalam jika bukan Wilona yang menenangkan Tiara, mungkin Tiara akan lepas kendali menyerang Wildan yang sejak awal memang memancing Tiara untuk kesal lalu ia berpikir lari secepatnya meski Tiara tahu itu tidak ada gunanya. Wilona berusaha membujuk Tiara untuk istirahat dan berpikir dengan lebih tenang, malam juga sudah begitu larut, Wilona berjanji esok hari apapun yang menjadi keputusan Tiara, maka Wilona tidak akan menghentikannya lagi. Pada akhirnya Tiara menuruti bujukan Wilona untuk beristirahat di sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap ke pekarangan belakang rumah. Tiara menyerah, memilih untuk tidur sejenak. Bagaimanapun juga Wilona benar, Tiara sangat lelah dan perlu istirahat.
Jika semua ini hanyalah mimpi, Tiara hanya ingin segera terbangun dengan harapan esok pagi ia kembali ke kehidupannya yang normal.
Dan pagi itu, Ketika Tiara terbangun dan mencoba melihat suasana pagi di luar rumah melalui jendela, ia melihat batu nisan itu, batu nisan milik Bibi Meredith yang ada di pekarangan belakang rumah milik Wilona dan Wildan. Terbersit perasaan kecewa dalam dirinya setelah menyadari ia masih berada di kamar yang sama dan dunia yang semalam dikenalnya masih menjadi tempatnya berpijak. Akhirnya hal pertama yang dilakukan Tiara setelah bangun dari tidurnya adalah mendatangi batu nisan tersebut, terdiam sepanjang waktu hanya untuk merutuk atas takdir yang menimpa dirinya. Tiara sudah beberapa kali bertanya “kenapa” pada batu nisan yang hanya membisu dalam keheningan pagi, berharap batu nisan yang bungkam secara ajaib akan menjawab entah setelah sekian kali ia bertanya mulai dari mendesis, bergumam, hingga memekik karena begitu kesal tak ada jawaban yang muncul. Pada akhirnya Tiara hanya bisa menangis sesenggukkan karena tak berdaya, rongga dada nya begitu berat oleh beban yang bergelayut tanpa pamrih.
Tiara yang sudah lelah berdiri di atas kedua kakinya kini mulai berlutut. Kedua lututnya yang tak tertutup kain rok miliknya bertumpu pada hamparan rerumputan berwarna hijau subur yang membentang di pekarangan belakang rumah tersebut. Ia masih sesenggukkan, mecoba meredakan tangisnya perlahan sembari mengusap kedua matanya dari air mata yang membasahi seluruh wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam keheningan yang menyelimutinya, samar-samar ia mendengar suara dari belakang punggungnya.
“Apa yang kau tangisi?”
Tiara terkesiap, sepasang bahunya terjungkat sepersekian detik karena terkejut, matanya terbelalak untuk sesaat sembari tetap menatap lekat-lekat pada batu nisan dihadapannya lalu memberanikan diri menoleh kearah suara yang berasal dari belakang punggungnya. Perasaan takut merayapi sekujur tubuhnya lantaran Tiara sadar bahwa dirinya sedang berada di sebuah makam di mana hal-hal mistis mungkin saja terjadi tanpa peringatan untuk waspada. Tiara juga menyadari bahwa sedari tadi dirinya hanya sendirian dan sejak semalam manusia yang ditemuinya hanya Wilona dan Wildan. Setelah Tiara menoleh dengan derajat putaran yang sempurna, tampaklah sosok seorang lelaki asing berdiri di sana dengan tubuhnya sedikit bersandar pada pohon besar yang memang berdiri kokoh tanpa pesaing di halaman belakang rumah itu.
“K-k-kau, siapa?” gumam Tiara lirih.
Pria itu tersenyum tipis, wajahnya terlihat cerah dan tampak tak berbahaya. Tiara memindai lekat-lekat pada pria tersebut mulai dari ubun-ubun hingga ujung kakinya. Pria yang saat ini berdiri beberapa hasta darinya terlihat tak terganggu akan sikap menilai yang dilakukan Tiara bahkan ia sengaja berdiri dengan tegap dan diam sejenak untuk memberi waktu kepada Tiara menyelesaikan apapun yang sedang dilakukannya.
Wajah pria itu sedikit samar karena berdiri di bawah pohon besar yang rimbun namun Tiara menyadari pria itu tengah tersenyum dan menunjukkan mimik wajah yang ramah. Tiara memicingkan kedua manik hazelnya meski sebenarnya Tiara tak memiliki gangguan penglihatan. Ia merasa perlu melakukannya untuk membuat dirinya fokus memindai sosok manusia di depan matanya saat ini.
Pria itu memiliki garis wajah yang tegas namun sepasang matanya memancarkan aura yang ramah dengan manik matanya yang memiliki nuansa hijau zamrud pada pupilnya dengan sklera putih yang jernih dan segaris bulu mata yang lebat dan lentik. Bibirnya tipis dan berwarna merah ranum segar dan alisnya tidak terlalu tebal namun memiliki lekukan yang indah berwarna kecokelatan. Kulitnya putih kekuningan, Tiara dapat melihat dari wajah dan punggung tangannya dengan jari jemari yang panjang dan lentik. Pria itu memiliki rambut yang bergelombang berwarna kecokelatan serupa alisnya, belah tengah tanpa poni yang mengekspos seluruh wajahnya dan rambutnya terjuntai panjang menyentuh bahu. Rambut kecokelatannya terlihat kontras dengan mantel putih tulang yang digunakannya. Mantel dengan bahan kain yang lembut menutupi seluruh tubuhnya, beberapa kancing besar berwarna putih serupa tampak menghiasi bagian dadanya. Atasan berwarna putih tersebut dipadankan dengan celana berwarna cokelat terang dan sepatu booth yang berbentuk ramping sebatas tungkai kakinya. Pria itu menegakkan tubuhnya yang sedari tadi bersandar pada batang pohon dan maju beberapa langkah untuk memangkas jarak diantara dirinya dan Tiara. Pada saat itulah perhatian Tiara tertuju pada kedua kaki milik pria asing itu, memastikan keduanya melangkah dengan tapak yang jelas pada hamparan rumput yang membentang di antara mereka.
“K-k-kau, bukan hantu?” celetuk Tiara kemudian ketika menyadari pria tersebut berpijak pada bumi namun ia tetap bergerak mundur beberapa langkah untuk tetap menjaga jarak.
Pria itu menghentikan langkahnya sejenak, sedikit terkejut atas apa yang didengar dari mulut mungil Tiara yang memancarkan sorot mata ketakutan meski ia begitu yakin tidak perlu ada rasa takut tercipta terhadap dirinya, sebab ia sangat percaya diri menjamin bahwa dirinya berpenampilan sangat baik tanpa cela, tidak menyeramkan sedikitpun, bahkan ia sangat yakin dirinya lebih mirip pangeran tampan yang muncul tiba-tiba.
“Apa aku seperti hantu untukmu?” tanyanya dengan senyum tergelitik.
Tiara membisu, tak bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Tiara memang meragukan tanda tanya dalam dirinya atas pria yang berada di depan matanya sebab ia pun menyadari daripada seperti hantu, pria tersebut lebih seperti pangeran tampan yang keluar dari buku-buku cerita bergambar yang dibacanya sejak kecil. Tiara untuk sesaat memang terpesona akan ketampanan pria di hadapannya, namun ia belajar dari pengalaman singkat semalam yang membuatnya tetap perlu waspada terhadap siapapun.
“Perempuan cantik, siapa namamu?” tanyanya lagi membuat Tiara tersadar dari kependiamannya.
“A-a-aku, Tiara.” ucap Tiara singkat dan mulai menurunkan rasa takutnya.
“Halo, Tiara yang cantik. Boleh aku mendekat?” izinnya.
“Tunggu! Kau siapa?” sergah Tiara tak mengizinkan pria tersebut untuk melangkahkan kakinya lebih dekat kepadanya sebab ia Tiara tak tahu apakah yang di depan matanya adalah lawan atau kawan.
“Aku?” tanyanya lagi.
Pria itu tetap diam mematung di titik posisinya berdiri lalu membuang pandangannya dari Tiara dan menatap nanar pada batu nisan yang menjadi panggung utama di halaman belakang rumah tersebut, lantas menjawab pertanyaan Tiara dengan nada yang lugas tapi misterius, “Aku adalah anak semata wayang dari ibuku.”
Tiara tercenung, ia tak mengerti apa yang telah disampaikan pria asing di depan matanya saat ini. Pria itu juga tak lagi tertarik untuk mendekati Tiara, melainkan mengubah haluannya untuk melangkah mendekati batu nisan dan memunggungi Tiara. Tiara memperhatikan pria tersebut dengan saksama, mendapati pria itu mengangkat tangan kanannya lantas membuka telapak tangannya ke atas lalu dari telapak tangannya yang terbuka memancarkan cahaya berwarna putih terang.
Tiara terkejut melihat apa yang ada ditangannya pria itu dan segera berlari menghampirinya, bergegas dan mengabaikan rasa takutnya untuk meraih tangan itu. Tiara tak bisa memikirkan apapun kecuali rasa curiga bahwa akan terjadi penyerangan terhadap batu nisan milik Bibi Meredith. Tiara menarik tangan tersebut dengan paksa, mencoba menurunkan agar pria itu tak dapat melakukan apapun.
“Hentikan!” hardik Tiara sembari memeluk tangan kanan yang kokoh milik pria itu tanpa ragu.
“H-h-he-hei, apa yang kau lakukan?” Pria itu terlihat panik mendapati Tiara memeluk tangannya dan memancarkan sorot mata penuh peringatan dan permusuhan dari wajahnya yang padahal sebelumnya terlihat tak waspada terhadap apapun.
“Jangan merusak makam Bibi Meredith!!!” hardik Tiara tanpa ragu.
Pria itu terkejut dan sorot mata Tiara yang tadinya terasa menakutkan kini terlihat lucu baginya. Tiara terlihat seperti kucing kecil yang sedang mencoba mengaum seperti singa dan itu membuatnya tak bisa menahan diri untuk tak tertawa terbahak-bahak.
“HAHAHAHAA! Apa yang kau pikirkan?” pria itu tertawa lepas membiarkan tangan kanannya masih dipeluk Tiara dan tangan kirinya menutupi wajahnya yang memerah karena tertawa tanpa henti.
Tiara hanya tertegun mendapati reaksi dari pria yang dipikirnya akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Pada akhirnya Tiara berangsur-angsur melonggarkan cengkeramannya pada tangan kanan pria itu dan melepasnya dengan sempurna. Tiara meluruskan kedua tangannya dengan tegang di setiap sisi tubuhnya, sebab ia kesal. Tiara mendengkus kesal karena merasa sedang dipermainkan.
Pria itu masih terus tertawa dari terbahak-bahak hingga terkekeh dan terbatuk karena terlalu banyak tertawa. Sedangkan Tiara sendiri mematung dengan raut wajah cemberut yang masih kesal dan takkan mereda jika pria itu tak minta maaf padanya.
“Hei, maafkan aku.” ucap pria itu tiba-tiba yang membuat Tiara terperangah.
“Aku hanya ingin memberkati makam ibuku, karena baru hari ini aku bisa kemari.” ucapnya lagi dengan tenang.
Suasana di antara mereka Kembali hening seketika karena Tiara begitu terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan pria itu. Tanpa mempedulikan reaksi Tiara yang Tengah mematung, pria itu kembali mengangkat tangan kanannya dan membentangkan telapaknya lantas dari telapak tangannya mulai memancarkan sinar putih terang yang sama seperti sebelumnya. Tiara yang terlanjur mengalami krisis kepercayaan terhadap siapapun di dunia asing itu tanpa terencana segera kembali menghampiri pria itu dan menangkup telapak tangan kanan milik pria itu dengan kedua telapak tangannya yang mungil.
“Sial! Aku tidak bisa percaya begitu saja!” gumamnya dengan lirih.
“Hei, aku benar-benar hanya ingin memberkati makam ibuku. Aku ini anaknya, namaku Norman.” ucap pria itu dengan kesabaran yang terpampang nyata dalam menghadapi sikap curiga Tiara.
“Nona manis, seharusnya aku yang curiga kepadamu. Memangnya kau siapa sampai sejak tadi kau hanya terus menatap tajam kepada batu nisan ibuku? Aku bahkan membiarkanmu beberapa waktu dan hanya mengawasimu dari balik pohon tanpa berpikir sedikitpun untuk mengganggumu.”
Mendengar semua yang dikatakan Norman membuatu Tiara merasa malu hingga ia tak bisa menutupi raut wajahnya yang memerah dan terasa panas, tidak sepertinya kedua telapak tangannya yang terasa dingin dan masih menangkup telapak tangan kanan Norman.
Tiara perlahan-lahan menurunkan lagi kedua telapak tangannya. Wajahnya tertunduk malu dan kali ini ia menahan dirinya untuk tak menghalangi apapun yang akan dilakukan Norman. Tiara memperhatikan dengan saksama yang sedang dilanjutkan Norman. Ternyata dari telapak tangannya yang bercahaya, muncul sebuah buket bunga dengan sekumpulan bunga mawar putih yang aromanya semerbak dan terlihat indah. Saat itu Tiara merasa semakin malu lantaran ia benar-benar menampakkan kecurigaan terhadap seseorang yang tak sepantasnya ia curigai.
“Nona manis, terima kasih karena tadi menahanku dengan tujuan melindungi makam ibuku. Meskipun itu sebuah kesalahpahaman, namun aku menyukai niatmu.” Ucap Norman dengan nada lemah lembut dan ditutup dengan senyuman manis untuk Tiara.
Tiara tercengang, ia mengangkat wajahnya perlahan dan memperhatikan dengan saksama langkah kaki Norman yang kini menghampiri batu nisan, berlutut, lantas meletakkan buket bunga miliknya dengan perlahan. Norman mengucapkan beberapa kata dengan lirih yang tak begitu terdengar oleh Tiara sebab Indera pendengaran Tiara sedang terganggu oleh hawa panas yang membuat kedua telinganya memerah. Wajahnya pun tak kalah merah merona lantaran tersanjung atas ucapan terima kasih yang diucapkan Norman. Pria itu seperti tahu bagaimana menyenangkan hati Perempuan dengan kata-kata manis dan didukung oleh wajahnya yang tampan dan senyumannya juga sangat menyentuh hati. Pada akhirnya Tiara terlupa sejenak bahwa ia sedang di tempat asing dan tadinya ia sedang sangat kesal hingga sampai berpikir untuk menyalahkan batu nisan yang tak tahu apa-apa. Bertemu dengan pria seperti Norman membuat Tiara merasa untuk pertama kalinya ia bertemu manusia yang sesungguhnya. Tiara diam-diam jadi membuat perbandingan di mana ia tersadar bahwa Wildan dan Wilona itu seperti penyihir dalam buku-buku dongeng, sedang Norman adalah manusia sesungguhnya. Bukan cuma sekadar manusia biasa melainkan pria tampan mempesona yang membuat mendung di pagi buta pun lenyap seketika dan berubah menjadi cahaya fajar berpelita indah nan hangat sempurna. Tiara tersenyum kecil menikmati apa yang sedang berkecamuk dalam ruang pikirannya.
Tiara segera menghapus senyum kecil yang tampak dari bibir mungilnya lalu memasang wajah datar namun telah menghilangkan sikap waspada yang tinggi ketika mendapati Norman menoleh ke arahnya. Tiara tetap berdiri mematung lantaran tak tahu apa yang sebaiknya ia lakukan sekarang. Haruskah ia pergi menjauh atau cukup menunggu Norman menghampirinya kembali?
Seakan mengerti apa yang ada dalam pikiran Tiara, Norman segera bangkit dari sikap berlututnya lalu menghampiri Tiara yang kini berdiri tegang sembari sibuk memilin jari-jemarinya dengan gelisah.
“Tiara, benar?” tanya Norman memastikan ia tak salah mengingat nama perempuan manis di hadapannya setelah ia berhasil memangkas jarak yang membentang di antara mereka berdua.
Tiara hanya mengangguk cepat dengan kedua tangannya masih sibuk saling memilin jari-jemarinya.
Kali ini giliran Norman yang menangkup kedua tangan Tiara. Telapak tangan Norman terasa hangat dan karena ukurannya yang sedikit lebih besar dari kedua tangan Tiara maka rasanya seperti sedang ditenangkan oleh sarung tangan hangat.
“Apa kau merasa tak nyaman? Apa aku membuatmu takut? Sudah kubilang aku bukan hantu.” Norman menjelaskan dengan lambat-lambat kepada Tiara sembari tetap menangkup kedua tangan Tiara untuk menenangkan.
Berhadapan terlalu dekat dengan Tiara membuat Norman jadi memperhatikan penampilan perempuan tersebut. Tiara terlihat sedikit berantakan mulai dari anak-anak rambutnya hingga pakaian yang dikenakannya juga terlihat agak kumal. Tiara memang hanya menggunakan pakaian yang dipakainya sejak semalam sedang rambutnya yang terlihat berantakan itu karena ia segera beranjak ke makam Bibi Meredith setelah bangun dari tempat tidur yang ditumpanginya semalaman. Tiara tak berpikir panjang bahwa bisa saja ia bertemu seseorang lantaran semalam dari cerita yang disampaikan Tiara menangkap keadaan bahwa di rumah terasing dari kota itu hanya ada Wilona, Wildan, dan Bibi Meredith. Tak terpikir bahwa akan muncul Norman di hadapannya.
Norman mengernyitkan dahinya setelah memindai penampilan Tiara. Kedua manik matanya yang berwarna hijau zamrud cerah tertuju pada kalung yang digunakan Tiara. Norman sangat mengenali kilat merah darah yang ada pada bandul kalung itu. Bukan hanya karena sinar kilauan dan bentuknya, Norman sangat tidak asing dengan aura kuat yang memancar pada bandul permata merah tersebut. Sejak masih kecil Norman terbiasa menatap kilatan merah dari sepasang mata milik Wildan dan Wilona. Kilatan yang sama persis dari bandul kalung yang dikenakan Tiara.
“Apakah itu… Ratnaraj?” tanya Norman lirih dengan tatapan matanya yang menghunus tajam pada kalung milik Tiara.
Tiara dengan sigap melepaskan kedua tangannya dari genggaman Norman dan segera menggenggam erat bandul kalung miliknya.
“Benarkah?” tanya Norman lagi untuk memastikan.
Tiara hanya tetap menggenggam erat bandul kalungnya dengan wajah cemas hingga Norman tersadar bahwa dia tidak salah terka. Untuk sesaat Norman merajut benang-benang merah kusut di dalam kepalanya. Siapa perempuan bernama Tiara yang ditemuinya sekarang? Kenapa perempuan itu menggunakan kalung permata merah serupa ratnaraj? Bagaimana perempuan itu bisa muncul di rumah ibunya bahkan berdiri di depan batu nisan ibunya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Tiara melangkah mundur dengan cepat dan ketika Norman mencoba melangkah maju untuk menjaga jarak yang dekat di antara mereka berdua, Wildan menghampiri dengan kasar, mendorong Norman menjauh dari Tiara. Norman sedikit terkejut dan terhuyung meski ia masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Tiara melihat Norman tetap tersenyum ramah seakan ia tak peduli dengan sikap Wildan yang tak sopan. Sedangkan Tiara saat ini tak bisa menebak bagaimana raut wajah Wildan yang Tengah memunggunginya dan memutus bentangan jarak antara Tiara dan Norman.
“Sedang apa kau di sini?!” tanya Wildan dengan tegas dan nadanya begitu tajam.
“Tentu saja mendatangi ibuku.” jawab Norman dengan tetap ramah.
Tiara hanya bisa diam membisu di balik punggung Wildan dan sebelum dirinya berprasangka buruk terhadap Norman yang disikapi ketus oleh Wildan, Wilona menghampiri dan menenangkan Wildan.
“Wildan! Apa yang kau lakukan?” tanya Wilona dengan nada penuh teguran.
“Apa?! Aku bahkan tidak membuatnya terjatuh! Kenapa kau memarahiku?!” celetuk Wildan dengan ketus.
“Wilona, aku tidak apa-apa.” ucap Norman dengan tetap ramah untuk menenangkan Wilona.
Wilona yang bingung dengan situasi yang terjadi mendadak pada akhirnya memilih untuk menarik Tiara masuk ke dalam rumah. “Norman, datanglah lain waktu, aku akan menjelaskan semuanya.” ucap Wilona dengan lembut dan mengisyaratkan tangannya agar Norman pergi.
Norman menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia memilih pergi tanpa memperhatikan sikap tak bersahabat yang ditunjukkan Wildan.
Tiara sendiri meskipun mematuhi ajakan Wilona untuk masuk ke dalam rumah, kejadian yang tampak di depan matanya membuatnya bertanya-tanya.
“Kenapa sikap Wildan begitu kasar kepada Norman?”
“Tapi kenapa Wilona seakan peduli dengan Norman dan Norman pun patuh pada Wilona?”
Namun yang paling menganggu Tiara adalah sekelibat ingatan tentang tatapan nanar Norman terhadap bandul permata ratnaraj yang ia kenakan.
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 7. Alkisah (Bagian 1)
1 Desember 2023 in Vitamins Blog
****
“TURUNKAN AKU!!!”
Tiara mengucapkan kata-katanya dengan tegas hampir serupa perintah yang tak dapat dibantah atas alasan apapun ketika menyadari ia tak lagi dibawa berlari kencang oleh Wildan untuk menembus pekatnya malam di jalan setapak yang begitu sepi dan hening dengan lampu-lampu sorotnya di kanan-kiri yang menjadi saksi bisu kecepatan Wildan yang tak lazim untuk dimiliki manusia biasa.
Setelah memastikan bahwa dirinya kini tengah berada di beranda sebuah rumah yang tampak tenang dan tak menguarkan aura berbahaya sedikitpun, Tiara memberanikan diri memerintahkan Wildan untuk melepaskan tubuhnya yang sudah sangat lama berada dalam dekapan Wildan, dalam gendongannya.
Wildan yang terlihat tak begitu ambil peduli dengan sikap Tiara yang terlihat tak suka dengan caranya hanya menunjukkkan ekspresi datar dan menyempatkan diri untuk memutar kedua bola mata amber miliknya dengan malas sebelum akhirnya menjatuhkan tubuh Tiara tanpa sungkan sedikitpun.
“Aduh!” pekik Tiara cepat ketika mendapati tulang ekornya mendarat kasar di permukaan lantai yang beruntung dialasi bentangan keset tebal nan empuk yang terbuat dari sulaman-sulaman kain perca berwarna-warni hingga saling menumpuk satu sama lain dan menciptakan ketebalan yang pas hingga mampu menahan tubuh Tiara agar terhindar dari hentakkan keras dengan ubin lantai secara langsung.
Wildan sendiri sebenarnya sudah memperhitungkan hal itu, sehingga ia merasa tak perlu memiliki rasa kasihan berlebih untuk Tiara yang kini terlihat sedikit merintih untuk rasa sakit yang sebenarnya tak seberapa. Payah. Lemah.
“Bangunlah, ayo masuk,” ajak Wildan yang kini telapak tangan kanannya telah menggenggam panel pintu dengan mantap dan siap untuk membukanya.
Tiara terburu-buru bangkit dari tempatnya, menepuk-nepuk halus pada rok gaun berwarna peach dan bernuansa pastel yang melingkar mengelilingi pinggang langsingnya hingga ujung kainnya menjuntai mencapai sebatas lututnya.
“Tidak mau!” tolak Tiara dengan tegas dan terdengar menyebalkan dari nada bicaranya setelah selesai melakukan tindakan membersihkan seluruh noda yang mungkin mengotori gaunnya meskipun secara kasat mata jelas sekali penampilan Tiara baik-baik saja kecuali anak-anak rambutnya yang terlihat berantakan akibat diterpa angin berkali-kali ketika dibawa berlari kencang oleh Wildan. Buru-buru Tiara merapikan rambut panjang lurus miliknya yang tergerai polos dengan menggunakan jari jemarinya. Tiara juga berusaha menyisir rambutnya dengan menggunakan sela-sela kelima jari pada kedua telapak tangannya. Raut wajahnya jelas sekali terlihat sangat kesal bahkan sengaja tak ingin melihat ke arah Wildan sedikitpun dengan berpura-pura sangat fokus pada apa yang sedang dilakukannya, merapikan rambut panjangnya.
Wildan melirik sekilas dan menipiskan bibirnya yang menyimpan geram tertahan. Ia sudah sangat lelah, pun perutnya terasa lapar. Melihat rumah yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk beristirahat telah berada tepat di hadapannya, membuat Wildan tak ingin menunggu lama lagi untuk tetap berada di luar. Wildan ingin segera masuk. Langkah kakinya seakan dibujuk paksa untuk segera melewati batas ambang pintu utama rumah tersebut sehingga ia sangat amat tidak peduli dengan penolakan Tiara yang terasa merepotkan untuk ditanggapi lebih jauh.
“Silahkan kalau mau tetap berada di luar, aku tidak akan menahan keinginanmu. Hanya saja, jika kau merasa ada ancaman berbahaya menghampirimu, kau bisa segera masuk, aku tidak akan mengunci pintu untukmu. Ini sudah sangat larut malam, aku tak menjamin di luar sini membebaskanmu dari dinginnya malam yang menusuk terlebih lagi kebanyakan makhluk-makhluk nocturnal di sini bukanlah hewan yang ramah pada manusia.” ucap Wildan enteng namun jelas sekali tersirat ancaman halus di dalamnya. Tubuhnya telah siap untuk bergegas masuk ke dalam rumah bersamaan dengan Tiara yang masih bergeming.
Tidak ingin berpikir lebih banyak lagi, Tiara seketika saja langsung bergidik ngeri terutama ketika Wildan mengucapkan ujung kalimatnya dengan penekanan yang begitu terasa mengancam jiwa.
Dia tak punya hati!
Bisa-bisanya dia membiarkan perempuan lemah sepertiku berada di luar sendirian begini?
Lupa akan kekerasan hatinya yang melakukan penolakan tegas terhadap tawaran Wildan sebelumnya, Tiara buru-buru melangkahkan kakinya mengekor langkah Wildan yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Belum sempat Wildan menutup daun pintu rumahnya, Tiara menahannya dan merangsek masuk dengan cepat karena begitu ketakutan atas ancaman halus yang dilontarkan Wildan secara tersirat. Wajahnya sedikit malu ketika menyadari membiarkan dirinya masuk rumah berarti dia sudah menjilat ludahnya sendiri.
Wildan kini telah menutup pintu utama rumahnya. Sebuah guratan senyum tipis menghiasi bibir Wildan yang tak diperhatikan dengan saksama oleh Tiara sebab sepasang mata hazel milik Tiara kini tengah sibuk memindai ke dalam isi rumah yang terlihat rapi, nyaman, dan damai. Diam-diam Tiara bersyukur memilih untuk masuk daripada bertahan dengan egonya untuk tetap berada di luar.
Apa jadinya dengan nasibnya jika Tiara bertahan di luar sana?
Lagipula, Tiara bahkan tidak tahu kenapa ia berada di tempat ini?
Tempat asing yang entah kenapa tidak terasa asing, seakan ia sudah pernah berada di sini sebelumnya.
“Duduklah,” Wildan mempersilahkan Tiara untuk menempati salah satu sofa empuk di dalam ruang tamu dan meskipun ada keraguan jelas terpancar dari dalam diri Tiara, namun akhirnya ia tergoda untuk duduk juga, membebaskan dirinya dari disorientasi halus yang menyerangnya karena terlalu lama terguncang dalam dekapan Wildan ketika berlari kencang.
Wildan sendiri memilih duduk di sebuah kursi goyang dari kayu yang berada di sudut ruangan. Itu adalah kursi goyang milik Bibi Meredith selama ini, dan sejak kepergian Bibi Meredith beberapa hari lalu, kursi itu menjadi tempat favorit Wildan untuk bermalas-malasan sekaligus untuk mengenang setiap sentuhan kasih sayang dari sosok wanita paruh baya yang disaksikannya menua hingga renta seiring berjalannya waktu lantaran disibukkan dengan mendampingi tumbuh kembang Wildan dan Wilona sejak mereka masih harus bergantung dengan orang lain untuk mengurus diri hingga menjadi semakin mandiri dan tumbuh menjadi dua sosok manusia tangguh di bawah naungan kilatan tak bersahabat dan teror dari para penduduk Kota Thames.
Bibi Meredith adalah orang tua kedua baginya setelah orang tua kandungnya sendiri yang hampir-hampir tak dapat diingat lagi sosoknya oleh Wildan kecuali rasa pedih yang terus melekat dari rintihan Ayah dan Ibunya ketika memohon dengan begitu lemah dan mengenaskan kepada si Tua Bangka brengsek untuk melepaskan Wildan dan Wilona yang tak mengerti apapun. Jika bukan Bibi Meredith yang dengan beraninya meraih sosok-sosok kecil tak berdosa secara diam-diam ketika sosok brengsek itu terlalu sibuk memuja keangkuhannya di atas ketidakberdayaan kedua orang tua Wildan dan Wilona yang terluka parah bahkan ajal telah siap melepaskan diri dari pangkal tenggorokan mereka, lalu membawa mereka berdua kabur dari tempat yang begitu menyesakkan dada untuk diingat kembali, mungkin Wildan dan Wilona hanya akan tumbuh menjadi jiwa kosong dalam genggaman penguasa dzalim sebagai tahanan seumur hidup untuk kepentingan dirinya sendiri.
Wildan dan Wilona mungkin tidak akan mati oleh siksaan apapun, hanya saja terkungkung untuk selamanya. Abadi.
Bibi Meredith selama hidupnya dengan segenap hatinya memastikan bahwa kedua jiwa yang begitu disayanginya itu tidak akan menjadi jiwa yang kotor dan ternoda oleh nafsu manusia tamak lantaran dibutakan oleh keserakahan.
Bibi Meredith ingin melihat Wildan dan Wilona menjadi jiwa yang bebas, menjadi manusia seutuhnya sebagaimana takdir menuliskan garis mereka ketika dilahirkan kedunia ini karena cinta yang menggelora di hati kedua orangtuanya.
Manusia dilahirkan sudah sepantasnya hidup sebagai manusia seutuhnya. Jiwa yang bebas, yang diberikan akal untuk berpikir, lantas bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Menjadi laki-laki, menjadi perempuan, sebagaimana ketentuan yang telah dibawa mereka sejak lahir. Dan, tidak ada yang salah dari penciptaan manusia sejak awal mulanya, kecuali manusia sendiri yang melampaui batas dari takdir yang digariskan untuk mereka.
Dalam kasus Wildan dan Wilona, pihak ketigalah yang berusaha melampaui batas atas takdir hidup mereka berdua. Membuat garis kehidupan Wildan dan Wilona terasa kacau balau hingga Bibi Meredith harus bekerja lebih keras menjaga kesucian jiwa mereka. Wildan sangat menyayangi Bibi Meredith.
Memperhatikan Wildan yang terlihat sedang dalam perenungan mendalam sembari melempar pandangannya ke pekarangan rumah dari kaca jendela membuat Tiara merasakan de javu sekali lagi, seakan dia sudah pernah melihat pemandangan itu sebelumnya.
“Kenapa rasanya pria ini tidak asing sama sekali?” batin Tiara sedikit terheran-heran.
Wildan menjentikkan jarinya cepat lalu membiarkan tubuhnya dibuai manja oleh kursi goyang yang didudukinya. Tidak ada penjelasan apapun untuk Tiara atas tindakan menjetikkan jari yang dilakukannya secara singkat dan cepat. Wildan hanya diam, seakan Wildan sedang menunggu waktu, menunggu sesuatu, dan itu membuat Tiara mengerutkan dahinya dalam-dalam lantaran bingung.
Haruskah ia duduk manis atau adakah yang perlu dijelaskan di sini?
“K-k-kenapa kau bisa berlari dengan begitu kencang?” tanya Tiara memecah keheningan yang tidak ia sukai.
Wildan hanya melirik sekilas ke arah Tiara lalu kembali memejamkan matanya dan membiarkan tubuhnya rebah sempurna di atas kursi goyangnya.
Tiara mendengus kesal, “Pria ini memang tidak punya adab sama sekali!” hardiknya dalam hati.
“Hei, aku sedang bertanya. Manusia yang memiliki sopan santun seharusnya menanggapi ketika ditanya!” celetuk Tiara lantas menatap tajam ke arah Wildan yang kembali melirik ke arah Tiara dengan malas ditambah menaikkan sebelah alisnya sembari berpikir cepat tanggapan yang menurutnya “pantas” untuk perempuan menyebalkan itu.
Aku lapar, aku capek, tidak bisakah aku tenang sejenak menikmati kedamaian di rumahku sendiri? Dasar, perempuan bawel.
“Apa kau tahu, berapa lama aku terduduk di Taman tadi untuk memulihkan tenaga? Apa kau tahu, tadinya sebelum kau muncul aku tengah berkelahi dengan belasan makhluk sialan?” tanya Wildan sembari bangkit dari kursi lalu langkahnya perlahan-lahan menghampiri Tiara dan tatapannya sangat mengintimidasi hingga membuat Tiara sedikit memundurkan punggunggnya karena ngeri.
“Lariku sangat kencang yaa? Apa rasanya seperti kecepatan serigala?” tanya Wildan lagi yang langkahnya semakin dekat.
Serigala? Apa maksudnya?
“Jadi jika aku tak memiliki sopan santun, apa sebaiknya tidak usah disebut manusia saja?” tanya Wildan lagi penuh teka-teki.
Bukan manusia? Serigala? Aku tidak mengerti.
Tiara memaksakan diri untuk berpikir cepat dalam kepanikan yang nyata. Hingga akhirnya ia menyimpulkan secara mendadak dari imajinasinya yang liar dan di luar batas logikanya sendiri.
“Ma-ma-manusia serigala?” gumam Tiara pelan namun tertangkap oleh telinga Wildan.
Kilat mata Wildan setelah mendengar dugaan Tiara terasa begitu puas hingga Tiara mendadak dihinggapi rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi gemetaran.
“Apa kau tahu? Energiku sangat terkuras. Berapa lama waktu yang diperlukan sistem percernaan untuk kembali menuntut asupan makanan, Tiara? Aku sudah melewati jam makan malamku. Dan kau pasti tahu kan, kaum karnivora, oh bukan, serigala, yaa serigala. Serigala sangat suka makan daging segar, bukan? Hmmm…” Wildan mengucapkan seluruh rangkaian kata-katanya dengan menyeringai lebar ke arah Tiara yang terlihat semakin ketakutan. Tubuh gemetarnya semakin menjadi-jadi.
Tiara hanya bisa menelan ludahnya sendiri, tak ada sepatah kata apapun yang mampu ia ucapkan.
Apa ini akhir dari hidupku?
Kenapa aku selalu begitu bodoh mempercayai orang asing begitu saja?
Tiara semakin memundurkan punggungnya hingga terasa memaku di sandaran kursi sofa dan buru-buru menutup matanya lantaran tak sanggup lagi melihat kenyataan mengerikan di depan matanya.
Sekali lagi, Tiara hanya bisa pasrah!
Masih dapat ditangkap oleh telinga Tiara derap langkah kaki perlahan milik Wildan yang semakin mendekati tubuhnya bahkan aura yang menguar dari tubuh Wildan terasa telah melingkupinya.
“Tiara, aku… la… par….” ucap Wildan lirih di salah satu telinga Tiara yang membuat Tiara sentak menjerit keras.
“Tuk!”
Ketukan halus dari telunjuk kanan milik Wildan mendarat sempurna di dahi Tiara hingga membuat Tiara menghentikan jeritan pendek melengkingnya seketika seakan Wildan telah berhasil menemukan tombol otomatis untuk menghentikan kelakuan Tiara.
“Roarrr!” raung Wildan yang lebih mirip seperti auman kecil yang diucapkannya dengan lirih dan lebih mirip seperti ledekan tepat di hadapan wajah Tiara sesaat setelah Tiara selesai mengerjapkan kedua matanya hingga terbuka sempurna dan terbelalak mendapati wajah Wildan sudah berada sangat dekat dengan wajahnya.
“Bodoh, aku manusia biasa dan aku memang lapar.” ucap Wildan enteng lalu melengos kembali ke kursi goyang miliknya dan meninggalkan Tiara yang masih berusaha menata perasaannya yang campur aduk oleh berbagai rasa yang rumit untuk dijelaskan.
Dia, mempermainkan aku?
Dia, pria sialan!
Belum sempat Tiara melakukan agresi beruntun untuk mengutuk kelakuan Wildan, kali ini Tiara terkejut dengan kehadiran dua piring sajian makanan dan dua cangkir teh panas yang melayang-layang melesat menuju meja di hadapannya. Bahkan dalam keadaan melayang tanpa keseimbangan yang baik, semua sajian itu masih mampu mendarat sempurna.
Lagi-lagi Tiara terperangah, “Bagaimana bisa?”
Wildan bangkit dari duduknya, segera mengambil piring miliknya dan memilih duduk di sofa dekat Tiara.
“Makanlah dulu, hentikan wajah bingungmu yang terlihat bodoh. Setelah ini aku akan mengajakmu bertemu seseorang.”
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 8. Alkisah (Bagian 2)
19 November 2023 in Vitamins Blog
****
Bertemu seseorang?
Siapa?
Kendati Tiara diliputi perasaan ragu untuk mematuhi perintah Wildan, namun perutnya yang terasa lapar mendorongnya untuk mengabaikan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyerang pikirannya. Keraguan mulai pupus berganti dengan kepercayaan yang dibangun Tiara secara paksa dalam dirinya.
Sampai detik ini hanya Wildan yang bersamanya dan bagaimanapun juga Tiara tidak kekurangan satu apapun dari jiwa dan raganya hingga sekarang.
Selain itu, meskipun Tiara menunjukkan sikap tidak ramah, jauh di dalam dirinya memiliki dorongan kuat untuk menggantungkan nasib dan memberi kepercayaan penuh pada sosok pria yang terlihat tengah sibuk makan tanpa memedulikan sorot mata Tiara yang sedang menilai dirinya lebih jauh.
Wildan makan dengan sangat lahap yang menunjukkan pria itu memang sangat kelaparan!
Bagaimanapun juga hidangan yang tersaji di depan mata Tiara memang terlihat begitu menggoda secara tampilan sehingga sangat menggugah selera, dan aroma yang menguar dari hidangan tersebut berhasil mengusik indera penciuman Tiara yang semakin membuat Tiara tak dapat bertahan lagi untuk mengabaikan makanannya. Aromanya saja seperti mencoba meyakinkan Tiara bahwa rasanya memang lezat dan akan memuaskan indera pencecap Tiara tanpa rasa penyesalan.
Sudahlah, aku memang harus makan!
Tiara dan Wildan akhirnya membunuh waktu yang perputaran detiknya terus berjalan bagaikan rotasi bumi di angkasa dengan menikmati makanan milik mereka dengan khidmat. Setelah satu suap, Tiara sungguh terkejut betapa nikmatnya makanan yang sedang ia makan. Ia bahkan lupa bahwa ia tengah berada di tempat asing dan sedang bersama pria asing. Makanan itu terlalu menghipnotis hingga Tiara abai untuk bersikap mawas diri. Tiara bahkan tak bisa menahan ekspresi terkesima yang terus menerus menghiasi wajahnya setiap kali ia menambah suapannya. Rasanya, enak!
Tiara telah mencapai suapan terakhirnya, sedangkan Wildan terlihat masih sibuk mengunyah hidangan di piring keduanya.
Iya, kedua!
Ditengah-tengah momen Tiara menikmati makanan, sepiring hidangan lagi-lagi melayang dan mendarat sempurna di depan Wildan. Rupanya Wildan belum merasa cukup dengan hidangan di piring pertamanya. Entah itu karena Wildan terlewat sangat lapar atau karena dia adalah pria dewasa yang membutuhkan lebih banyak asupan makanan daripada para perempuan atau mungkin Wildan itu… rakus?!
Tiara tak tahu pasti dan tak ingin mempertanyakan lebih jauh. Tiara tak ingin terjebak dengan rasa ingin tahu yang hanya akan menjerumuskan dirinya ke dalam perdebatan panjang menyebalkan dengan Wildan nantinya. Tiara sudah cukup merasa tenang dan damai dengan situasi mereka berdua saat ini yang hanya asyik dengan makanan mereka masing-masing.
Tiara mengedarkan pandangannya sekali lagi ke sekeliling ruangan untuk menyibukkan dirinya yang masih menunggu Wildan selesai makan dalam keheningan hingga Tiara dapat mendengar kecapan yang sedikit mengganggu dari cara Wildan mengunyah makanan dengan penuh hasrat.
Sepertinya memang rakus!
Kali ini pandangan mata hazel Tiara terpaku pada sebuah pintu berwarna putih yang menempel langsung dengan salah satu sisi tembok ruangan. Ada keterikatan yang tak dapat dijelaskan hingga Tiara terdorong untuk bangkit dari duduknya, melangkah mendekati dua daun pintu yang lebih mirip lemari di dalam tembok tanpa meminta izin terlebih dulu kepada Wildan.
Wildan sendiri tidak mengambil perhatian lebih terhadap gerakan Tiara. Diam-diam Wildan merasa paham kenapa Tiara sangat tertarik mendekati pintu putih tersebut.
Karena disitulah Tiara terakhir berada sebelum akhirnya meninggalkan rumah ini.
Selain itu, mungkin ada kenangan tertinggal yang mengusik jiwanya, sebuah pemandangan tak nyaman dari tubuh Wilona yang bersimbah darah hitam yang terpaksa disaksikannya.
Tiara melangkahkan kakinya dengan sangat perlahan, ada rasa tak nyaman yang menggelayuti hatinya ketika ia semakin mendekati pintu putih tersebut. Tangan Tiara bergetar halus ketika terayun bebas di udara untuk kemudian menyentuh daun pintu putih tersebut.
Tiara terperanjat. Matanya terpaku dan tubuhnya menegang. Sekelebat potongan-potongan ingatan yang rasanya sudah cukup lama tersimpan dalam ingatannya menyeruak, seakan ingin tumpah dari ruang kepalanya dan menyajikan layar imajiner di depan matanya untuk Tiara tonton bagai alur film pendek yang diputar cepat dan acak.
Darah hitam yang mengalir dari celah pintu?
Perasaan takut yang menyerang Tiara saat itu?
Wanita cantik yang tergeletak mengenaskan?
Tunggu! Semua itu bukan mimpi melainkan Tiara memang pernah ada di sini.
Dan jikalau semua itu hanyalah mimpi lainnya, bertahun-tahun lamanya Tiara melupakan atau mungkin mengabaikan dan berpikir ia hanya selalu dihantui mimpi tentang sebuah taman sepi dengan suara menggema yang memanggil-manggil namanya.
Kali ini Tiara menyadari sesuatu. Tiara selalu memimpikan semuanya namun hanya ingatan pendek yang tersisa dan mampu diingat Tiara setiap kali ia terbangun dari tidurnya.
Tiara terperanjat untuk kedua kalinya, pikirannya mulai menjurus pada hal yang paling penting untuk dipertanyakannya.
“Di mana Wilona?” tanya Tiara lirih yang membuat Wildan setengah tidak percaya akan pertanyaan Tiara.
“Kau sudah ingat?” Wildan bertanya balik dan mengabaikan jawaban yang diharapkan Tiara.
“Di mana Wilona?” tanya Tiara lagi, sangat menuntut jawaban.
“Di sini.” ucap Wilona singkat yang membuat Tiara terkejut lantas memalingkan wajahnya ke arah sumber suara. Wilona terlihat berdiri dengan tubuh yang rapuh di ambang lorong yang menghubungkan ruang tamu tersebut dengan ruangan-ruangan lainnya.
“Wilona, kau baik-baik saja?” pekik Tiara sebelum akhirnya mengatupkan kedua telapak tangan ke depan mulut mungilnya sebagai rasa tidak percaya akan apa yang sedang dilihatnya.
Wilona sedikit mengernyitkan dahinya menyadari kehadiran sosok wanita asing di hadapannya. Mata ambernya menyempatkan diri untuk mencuri pandang ke arah Wildan yang terlihat tidak peduli dengan drama dua wanita saling terkejut satu sama lain. Wildan masih sibuk menikmati makanan ronde keduanya.
Wilona akhirnya memindai cepat ke arah Tiara dari ubun-ubun hingga ujung kakinya lalu sama seperti Wildan, Wilona segera menyadari siapa wanita di depannya ketika mendapati kilat Ratnaraj dari bandul kalung Tiara hanya dengan sekali pandang.
“Tiara?” gumam Wilona nyaris tidak percaya dengan sosok Tiara yang jauh berbeda.
Baru beberapa jam yang lalu, tapi perempuan ini mampu tumbuh dewasa dengan cepat?
Tapi sekali lagi sama dengan cara berpikir Wildan, Wilona tidak begitu heran mengingat kemunculan Tiara yang tiba-tiba di Taman Rosetta. Selain itu, Wilona menyadari asal muasal Tiara sepertinya berasal dari dimensi lain yang berada di belahan dunia lainnya yang menjadi rahasia semesta dan itu sudah melampaui batas nalar Wilona untuk mencari tahu lebih jauh.
“Jika aku baru berada di sini beberapa jam yang lalu, bukankah seharusnya keadaan di sini sangat kacau? Lalu bagaimana kau….” Tiara meneguk air liurnya dan tak mampu melanjutkan kalimatnya.
“Tidak mati?” sambung Wilona.
Tiara hanya mengangguk cepat sebagai bentuk setuju atas ucapan Wilona yang tadinya terlalu sulit untuk dikatakannya.
Wilona tersenyum hangat kemudian melangkah mendekati Wildan dan bermaksud duduk di samping saudara kembarnya. Tiara sendiri mengikuti arah langkah Wilona lalu memilih duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan sepasang manusia kembar tersebut.
Tiara tahu akan ada penjelasan-penjelasan yang diungkapkan kali ini dan Tiara siap mendengarkan.
***
Wilona berdehem beberapa kali sebelum kemudian mulai bercerita sedang Wildan yang sudah selesai makan memilih menyandarkan punggungnya dengan malas dan memejamkan matanya seakan tidak tertarik dengan sajian dongeng yang akan membuatnya bosan.
Perutnya merasa sangat kenyang, sekarang saatnya untuk santai sejenak.
“Kau benar Tiara, rumah ini tadinya sangat kacau. Tapi, kau sudah lihat sendiri kan bagaimana makanan dan minuman mampu tersaji secara ajaib di depanmu?” Wilona membiarkan pertanyaannya mengambang di udara dan hanya dibalas dengan anggukkan pelan oleh Tiara.
“Sebelumnya aku sudah mengatakan padamu tentang Bibi Meredith yang telah tiada beberapa hari yang lalu. Beliau yang merawat kami sejak kecil, sejak kami terpisah dari kedua orang tua dan kemudian tinggal disini hingga sekarang.” Wilona menghentikan sejenak ceritanya, memberi waktu kepada Tiara untuk mencerna informasi yang ia berikan.
“Bibi Meredith memiliki kemampuan sihir dan rumah ini telah diberkati olehnya sehingga abadi dan mampu memperbaiki diri dan mengurus seluruh keperluan di dalam sini jika kami sedang tidak ingin melakukan hal-hal yang seharusnya bisa kami lakukan sendiri seperti menyiapkan makanan, dan lain-lain.” ucapan Wilona lagi-lagi dijeda untuk memperhatikan Tiara yang mengangguk-angguk mengerti.
“Tidak banyak manusia yang memiliki kemampuan sihir di sini, bahkan hanya bisa dihitung jari dan Bibi Meredith adalah satu dari belasan manusia yang diberkati,” ucap Wilona lirih, ada rasa pilu menyerangnya ketika mengenang kembali mengenai Bibi Meredith.
“Ratnaraj yang memilihmu merupakan satu dari pecahan tiga Ratnaraj itu sendiri. Sebuah batu permata dengan kekuatan magis yang bertahun-tahun lalu memicu sebuah konflik berkepanjangan di sini, Kota Thames yang merupakan satu-satunya kota yang kami kenal di bawah kekuasaan pria serakah bernama Marvin.”
“Pecahan tiga?” sanggah Tiara tiba-tiba sambil memegang bandul kalung miliknya.
“Iya, tiga.” ucap Wilona meyakinkan.
“Lalu, di mana yang dua lagi dan apa hubungannya denganku?” tanya Tiara lagi dengan rasa heran yang membuncah.
“Satu-satu Tiara, aku akan menjelaskan secara perlahan,” ucap Wilona lagi sembari tersenyum lembut.
“Orang tua kami tadinya adalah pemimpin tertinggi di tempat ini. Kami mungkin menyebut tempat ini sebagai kota, tapi kau bisa menyamakan sistem pemerintahan di sini dalam bentuk pemerintahan tunggal yang mencakup seluruh isi dunia yang kami kenal ini, entah istilah apa yang kau kenal untuk mewakili keadaan di dunia kami ini. Bisa dibilang, tempat ini hanyalah Kota Thames ini saja, tidak ada tempat lainnya. Paman Marvin dan Bibi Meredith adalah dua bersaudara yang dikaruniai kemampuan sihir. Penyihir sendiri sejatinya adalah orang-orang baik, mereka ditempatkan di posisi-posisi penting dalam sistem pemerintahan Kota Thames. Paman Marvin sendiri adalah penasehat tinggi Ayah kami. Dan, Bibi Meredith adalah pendamping utama Ibu kami. Ketika kami dilahirkan, kami begitu rapuh sehingga orang tua kami berpikir untuk menggunakan Ratnaraj yang merupakan pusaka turun temurun di tempat ini agar kami mampu bertahan hidup, sebab kamilah penerus kepemimpinan selanjutnya.”
Tiara hanya terus berusaha fokus dengan apa yang disampaikan Wilona. Kepalanya tak henti-hentinya mengangguk-angguk untuk terus mencerna informasi yang diterimanya.
“Paman Marvin adalah satu-satunya orang yang tidak setuju dan menganggap orang tua kami telah menyalahi aturan pusaka. Ratnaraj seharusnya dijaga, bukan digunakan. Yaa, aku rasa ada benarnya juga. Tapi pihak-pihak lain merasa setuju mengingat kami ke depannya akan menjadi pemimpin selanjutnya. Kami harus menjadi kuat untuk itu.”
“Jadi, yang dimaksud dengan pecahan tiga?”
Wildan kini telah duduk tegak dan bersamaan dengan Wilona tanpa aba-aba keduanya menatap tajam ke arah Tiara yang membuat Tiara merasa tak nyaman.
Dan, betapa terkejutnya Tiara ketika menyadari kilat merah menyala dari bola mata amber kanan milik Wilona dan Wildan yang cahayanya seakan menghunus jantung Tiara hingga Tiara tak dapat menahan diri untuk terperangah kemudian menutup mulutnya dengan telapak tangan.
“Itu, Ratnaraj lainnya?” tanyanya cepat dan dibalas dengan anggukkan mantap oleh Wildan dan Wilona.
“Pecahan terakhir yang ada pada kalungmu itu sengaja disisakan sebagai tanda bahwa pusaka Ratnaraj yang menjadi jantung tempat ini masih ada. Ketika kami menginjak usia sepuluh tahun, orang tua kami termasuk Paman Marvin dan Bibi Meredith mengetahui bahwa Ratnaraj yang bersemayam dalam diri kami ternyata membuat kami menjadi abadi. Aku dan Wildan terjatuh ke dalam jurang ketika tengah bermain di luar. Itu kesalahanku yang tidak hati-hati dan berdiri di tepi jurang hanya karena rasa penasaran akan apa yang ada di dasar jurang itu, ketika kakiku tergelincir, Wildan segera berlari untuk menolongku dan itu malah membuat kami terjatuh bersama. Jurang itu dalam dan manusia biasa sudah pasti tidak akan bisa terhindar dari maut. Ibu yang menyaksikan kami terjatuh dari kejauhan dengan kekalutan yang begitu dalam segera meminta Bibi Meredith mengangkat tubuh kami dengan sihirnya. Semua orang berkumpul di tepi jurang, begitu takut namun juga penasaran bagaimana wujud mayat kami. Dan….”
“Mereka terkejut menemukan kami tetap hidup dengan tidak kekurangan satu apapun kecuali darah kami yang ternyata berwarna hitam berlumuran di sana-sini, itupun tak lama menghilang seakan tak pernah terjadi apa-apa. Kami menyembuhkan diri kami dengan sendirinya.” lanjut Wildan tegas.
“Paman Marvin yang mengetahui hal itu menjadi gelap mata, ia ingin pecahan ketiga dari Ratnaraj untuk dirinya sendiri. Ia telah menyusun rencana dan menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi orang tua kami, merebut Ratnaraj, mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin selanjutnya. Dan iya, dia mendapatkan keinginannya untuk menguasai Kota Thames tapi tidak dengan kekuatan magis ratnaraj.” lanjut Wilona menggantikan Wildan.
“Maksudnya?” sanggah Tiara lagi.
“Bibi Meredith berhasil membawa kabur kami dan diam-diam mengambil pecahan ketiga ratnaraj ketika Paman Marvin terlalu sibuk tanpa perasaan menghabisi kedua orang tua kami pada malam yang mengenaskan itu. Dengan kekuatan sihirnya yang tak kalah kuat dari Paman Marvin, Bibi Meredith membangun tempat ini dalam sekejap, menjadikan tempat ini sebagai perlindungan abadi untuk kami, juga menjaga ratnaraj terakhir dan mengutuk Paman Marvin bahwa suatu hari akan tiba saatnya Paman Marvin akan menghadapi ajalnya oleh kekuatan magis ratnaraj ketiga itu sendiri yang telah merubah jiwa sucinya menjadi gelap gulita, kelam dan keji. Sampai saat itu tiba, Paman Marvin sebaiknya habiskan waktunya untuk menikmati kekuasaan semunya saja.” terang Wilona dengan menyimpan kebencian yang mendalam.
“Sekarang saat itu tiba, sudah waktunya Paman Marvin yang terhormat menerima kutukannya.” ucap Wildan dengan seringai tajam dan dipenuhi semangat membunuh.
“Kau telah dipilih oleh Ratnaraj terakhir, Tiara. Kau-lah yang akan menghabisi nyawanya.” sambung Wilona.
Tiara sentak berdiri dari duduknya, ia tak percaya dengan apa yang sudah didengarnya.
Membunuh?
Tiara harus membunuh nyawa?
Tidak mungkin!
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 6. Dejavu
14 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
10 tahun kemudian….
“Tap, tap, tap, tap!”
Derap langkah kaki jenjang milik Tiara terdengar mengetuk ubin lantai secara bergantian dengan cepat. Di sepanjang koridor yang sepi, suara ketukan dari hak sepatu setinggi lima senti pada alas kaki Tiara yang berwarna hitam legam dan mengkilap terdengar menggema dan mengudara bebas tanpa distraksi dari suara-suara lainnya, kecuali keheningan.
Perempuan itu tengah terburu-buru, sangat tergesa karena sedang berusaha secepat mungkin dan penuh harap mampu menggapai panel pintu sebuah ruangan tepat waktu untuk membukanya, tidak terlambat. Sebuah ruangan yang di dalamnya telah dipenuhi tidak lebih dari lima sosok manusia lanjut usia yang menunggu tanpa kesabaran yang bisa diajak berdamai bila Tiara terlambat barang sedetik saja. Hidup mereka sudah terlalu dipenuhi kejenuhan lantaran usia yang senja, sehingga kegiatan menunggu adalah hal yang tak mampu ditolerir lagi. Terlebih mengingat kasta mereka sebagai dosen-dosen senior, terlalu tinggi untuk sekedar berbaik hati memberi waktu mereka yang berharga kepada seorang mahasiswi biasa seperti Tiara yang begitu berani menyodorkan dirinya untuk ujian skripsi tunggal. Hanya dia sendiri, tanpa rekan-rekan senasib seperjuangan untuk ikut meramaikan momen penting tersebut.
Yaa, Tiara. Gadis berusia 23 tahun itu tengah berada pada penentuan nasibnya sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir yang telah selesai berjuang menciptakan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang menjadi tolak ukur kelayakannya untuk menyandang gelar sarjana.
Keberuntungan memang selalu berpihak pada Tiara. Meski tadinya ia harus berlomba dengan waktu, sebab meskipun ia sudah menyiapkan segalanya, ia terlupa kelengkapan berkas sepele yang memaksanya untuk izin sejenak keluar dari ruangan. Pada akhirnya Tiara mampu kembali tepat waktu dan setelahnya semua yang terjadi di dalam ruangan berjalan mulus hingga akhir tanpa cela sedikitpun. Tiara yang tampil menggunakan dress terusan selutut berwarna peach dengan nuansa pastel nan lembut yang mengintip dari balik jas almamater berwarna putih tulang yang dikenakannya, menambah kesan anggun pada diri Tiara yang memiliki rambut hitam lurus kecokelatan dengan ujung surainya hampir mencapai batas pinggangnya dan sengaja ia gerai polos tanpa hiasan apapun untuk mengesankan penampilan yang sederhana dan elegan. Penampilan yang mencerminkan pribadi Tiara seutuhnya.
Selesai, satu kewajiban telah terlaksana.
Setelah beramah tamah ala kadarnya dan selesai membereskan sisa-sisa kegiatan sidang skripsi hingga ruangan yang dipakainya kembali rapi seperti sedia kala, kini Tiara hanya ingin segera pulang. Hari juga sudah malam, hitam pekat telah menyelimuti bentangan langit yang membuat Tiara rindu rumah agar ia bisa menata hatinya yang masih menyisakan degupan tak terkendali saat tampil di depan para dosen serta melepas penat dari tubuh yang sudah sangat memberontak mengingat berhari-hari ia menguras energinya terlalu banyak untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang skripsinya hari ini.
Ah, aku rindu kamarku!
Tiara melepas jas almamaternya dan mengampitnya pada lengan kanannya kemudian kini melangkahkan kakinya dengan semangat untuk menuju lahan parkir tempat ia memarkir mobilnya. Lahan parkir berada di seberang gedung di mana Tiara tengah berada. Terdapat jalan raya yang membelah area keduanya di mana jalan tersebut seringkali ramai dengan kendaraan mahasiswa yang lalu lalang.
Baru saja Tiara hendak melangkahkan kakinya untuk menyeberangi jalan, langkah Tiara terhenti dan perhatiannya tertuju pada seekor kucing hitam kecil yang terlihat linglung dan berada hampir mendekati area tengah jalan yang tak berada jauh dari dirinya. Kucing kecil malang yang berdiri dengan susah payah hanya untuk sekedar bertumpu pada keempat kaki mungilnya hingga menunjukkan tubuh gemetar halus, membuat hati luluh ketika melihatnya, “Ya ampun, kucing itu bisa saja tertabrak kendaraan kalau tetap berada disitu, warna hitamnya nyaris serupa malam,” gumam Tiara lalu buru-buru mendekat untuk memindahkan kucing tersebut.
Kucing itu mungkin tidak berada tepat di tengah jalan, namun kesialan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bukan?
Terlebih lagi bukan hal baru, di jalan itu, seringkali terdapat beberapa mahasiswa yang merasa keren ketika mengendarai motor-motor besar yang mereka miliki. Mereka secara tak tahu diri melesat dengan kecepatan tinggi seolah jalan tersebut diciptakan hanya untuk mereka saja. Tiara tak bisa membayangkan bagaimana nasib kucing tersebut bila tertabrak salah satu dari mereka yang Tiara yakini bahkan jika mereka menyadari kehadiran sosok kucing kecil tersebut, kemungkinan terlambat untuk menghentikan kuda besi yang mereka banggakan pastinya sangat besar.
Kadang semesta terkesan tidak adil atau naas yang digariskan untuk suatu makhluk menular pada makhluk lainnya yang mencoba peduli.
Baru saja Tiara selesai berjingkat perlahan untuk kemudian berjongkok agar dapat menggendong kucing kecil malang tersebut, salah satu kuda besi yang sudah ada dalam kekhawatiran Tiara sebelumnya melesat tajam ke arahnya, sangat dekat hingga Tiara hanya bisa memeluk kucing malang dalam dekapannya tersebut sembari memejamkan matanya erat-erat. Sebuah usaha konyol yang seakan dipercaya Tiara secara ajaib mampu menolong situasinya saat itu, terhindar dari marabahaya hanya dengan menutup mata!
“KYAAAA!!!” hanya teriakan melengking tercekat yang mampu dilakukan Tiara dengan tubuh yang tak dapat bergerak sedikitpun, mematung bagai batu.
Tubuh Tiara terasa melayang, tidak merasa sakit, hanya merasa seakan jiwa raganya tertarik oleh suatu daya tarik yang dalam sekejap saja membuat tubuhnya melesak pada suasana yang asing menyapa indera peraba miliknya.
Apa aku tertabrak?
Tidak sakit.
Apa aku baik-baik saja?
Tanda tanya besar berkecamuk dalam diri Tiara yang masih mempertahankan kedua mata hazelnya untuk tetap terpejam. Hening, tidak ada satu suarapun yang tertangkap oleh kedua telinga Tiara. Tiara takut untuk membuka mata dan memastikan kenyataan yang tengah ia hadapi saat ini.
“Wanita, bisa engkau berdiri?”
Suara berat seorang pria yang terasa dekat di tengkuknya membuat Tiara terperanjat hingga ia dengan cepat membuka matanya dan terbelalak.
Tiara segera berdiri dengan sigap dan mendapati pemandangan yang begitu asing tersaji di depan matanya.
Tempat apa ini?
Pekat malam yang sama seperti terakhir kali Tiara berada dalam kesadarannya sepenuhnya sebelum menutup rapat-rapat pelupuk matanya, namun hawa di tempat itu terasa asing. Rasa asing yang sepertinya pernah dirasakan Tiara untuk waktu yang sudah sangat lama. Bukan! Setelah memindai secepat kilat, Tiara seperti kembali ke dalam mimpi yang selama ini terus menghantuinya. Mimpi yang sama hampir setiap malam sejak sepuluh tahun yang lalu, menampilkan sebuah taman kosong nan sepi yang hanya menggaungkan suara seseorang yang terus memanggil namanya.
Aku bermimpi lagi?
“Hei, siapa kau?”
Tiara tersentak ketika mendapati suara berat itu lagi-lagi menyapanya dari belakang tubuhnya. Tiara membalikkan badannya secepat kilat dan keterkejutannya semakin bertambah ketika melihat sosok pria bertubuh kokoh tengah duduk menyandarkan seluruh tubuhnya pada bangku taman yang ia duduki seolah pria tersebut berusaha menghapus lelah tak terperi bila dilihat dari nafasnya yang tersengal.
Tiara tertegun, tak dapat mengucapkan sepatah kata apapun.
Pria itu adalah Wildan, ia memang terlalu lelah setelah menumpas seluruh makhluk boneka sialan yang mengejarnya dengan nafsu membunuh tak terkendali. Wildan menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk bertarung hingga penat setelah melepas kepergian Tiara.
Wildan sejatinya merasa heran dengan manusia tamak yang mengirim boneka-boneka laknat miliknya untuk terus menghadapi Wildan sepanjang malam.
Bukankah Si Tua Bangka brengsek itu sudah sangat tahu bahwa mengharapkan kematian Wildan dan Wilona adalah sesuatu yang mustahil?
Apa akal sehatnya semakin tumpul karena menyadari ajalnya semakin dekat?
Manusia bodoh!
Wildan menegakkan kepalanya, memindai cepat pada sosok perempuan di depan matanya. Setelah ia melepas kepergian gadis kecil lugu yang dengan putus asa dipercayakan Wildan untuk membawa Ratnaraj bersamanya entah kemana ia pergi menghilang, kali ini siapa lagi yang muncul?
Sepasang bola mata amber milik Wildan terpaku saat mendapati pancaran kalung berbandul permata merah yang melingkar di leher jenjang perempuan dihadapannya.
“Kau, Tiara?” tanyanya singkat dengan penuh keheranan yang sangat mengganggu logikanya.
Bola mata amber itu memiliki keterikatan yang mendalam dengan kekuatan magis Ratnaraj yang bersemayam di dalam kalung milik Tiara, sehingga Wildan mampu menyadari keberadaan Ratnaraj hanya dengan sekali pandang.
Tiara yang merasa terintimidasi dengan pertanyaan singkat Wildan, hanya mampu mengangguk pelan sebagai tanda mengiyakan pertanyaan yang dilontarkan Wildan.
Mengingat kehadiran Tiara sebelumnya dalam wujud gadis kecil belasan tahun yang secara ajaib muncul di Taman Rosetta, Wildan tak merasa aneh jika kali ini Tiara ternyata kembali sebagai sosok wanita dewasa. Tidak ada waktu untuk terlalu penasaran tentang bagaimana cara semesta menghadirkan Tiara secara ajaib dengan takdir yang membelenggunya sebagai jiwa yang terpilih untuk menggenggam Ratnaraj terakhir.
Hanya saja, itu tak membuat Wildan mampu menahan diri untuk bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Tiara dengan langkah perlahan tapi pasti, lalu meloloskan sebuah pernyataan yang mengejutkan.
“Aku baru saja melepasmu beberapa jam yang lalu dalam wujud gadis kecil polos nan lugu. Sungguh ajaib sekali kau muncul kembali sebagai sosok perempuan dewasa yang memesona, Tiara. Kau cantik.”
Semburat rona merah memancar halus di kedua pipi Tiara. Pria yang mendekatinya saat ini meskipun terasa menakutkan dan asing dengan tampilannya yang aneh, terlebih lagi pria itu terlihat sedikit kacau dipenuhi peluh dan lelah yang tergambar di sana-sini, tak dapat dipungkiri tetap saja menguarkan pesona yang tak dapat dijelaskan Tiara dengan kata-kata. Tiara seperti merasa sedang kagum pada pria tersebut bukan untuk pertama kalinya. Terlebih lagi pria itu mengatakan hal manis yang membuat jiwanya seakan melayang bebas di udara untuk sesaat. Memujinya.
Wanita mana di muka bumi ini yang tak suka dengan pujian? Bahkan jika pujian itu adalah dusta, wanita akan memilih memungkirinya dan menelan bulat-bulat pujian yang diterimanya sebagai kesejukan bagi jiwanya yang selalu haus akan kasih sayang.
Tubuh wildan semakin mendekat hingga memangkas jarak dengan tubuh Tiara. Tepat di depan matanya, Tiara dapat mengamati bibir tipis milik Wildan bergerak kembali untuk mengucapkan kata-kata.
“Berapa usiamu sekarang? Kenapa dadamu terlihat rata?” tanya Wildan lagi tanpa rasa sungkan, bahkan ekspresi wajahnya terlihat datar dan terasa menyebalkan.
JLEB!
Ekspresi wajah Tiara seketika saja langsung menegang dan menggelap. Tanpa aba-aba, kedua tangannya segera berayun bebas di udara untuk mendorong tubuh Wildan menjauh darinya.
“Pria tak bermoral!” bentak Tiara lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong tubuh tegap milik Wildan hingga Wildan yang tenaganya belum pulih seutuhnya nyaris kehilangan keseimbangannya untuk berdiri kokoh.
“Hei, apa salahku? Aku hanya bertanya,” ucap Wildan lagi masih tak merasa berdosa sedikitpun.
“Dengar, aku tidak kenal siapa dirimu. Aku juga tidak tahu bagaimana kau tahu namaku. Pergi dari hadapanku, dasar pria mesum!” celetuk Tiara dengan ketus lalu beranjak melangkah serampangan menuju jalan setapak satu-satunya yang ia sadari ada di tempat itu.
“Tiara! Apa kau tidak tahu siapa aku? Apa kau tahu dimana kau berada?” tanya Wildan dari balik punggung Tiara yang membelakanginya namun pertanyaan itu berhasil merantai langkah kaki Tiara.
Mendapati langkah kaki Tiara yang terhenti dengan ragu, membuat Wildan segera sadar bahwa Tiara yang kali ini dilihatnya sepertinya tidak mengingat apapun yang terjadi beberapa jam waktu yang lalu. Ini tidak boleh dibiarkan, Wildan harus mengulang kembali penjelasan mengenai sebab keberadaan Tiara di Taman Rosetta, dan satu-satunya cara adalah dengan membawa Tiara kembali ke rumahnya.
“Tiara, ikutlah denganku,” ajak Wildan tegas.
“Tidak mau! Memangnya kau siapa?” bantah Tiara yang masih mematung di tempatnya berdiri.
Wildan melangkah tegas mendekati Tiara kembali sembari mengucapkan beberapa kata, “Dengar, namaku Wildan. Aku rasa kau terlupa apapun yang baru saja terjadi di tempat ini. Ikut denganku, tempat ini tidak aman untukmu. Aku tidak ada pilihan lain selain memaksamu.”
Baru saja Tiara akan kembali melakukan aksinya untuk tegas menolak, tubuhnya sudah berada dalam dekapan Wildan dan dibawa berlari dengan cepat menyusuri jalan setapak satu-satunya di Taman Rosetta itu.
De Javu!
Tiara merasakan ingatan sekelebat muncul dalam pikirannya, keadaan ini tidak asing!
“Jangan bergerak, aku akan sangat cepat! Kalau kau memberontak, kau akan jatuh dan terluka!” ancam Wildan yang membuat nyali Tiara menciut saat mencoba menggeliat dari dekapan Wildan.
Pada akhirnya Tiara hanya bisa, pasrah!
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 5. Ratnaraj
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
Jalan setapak satu-satunya di area taman tersebut ternyata begitu panjang, sehingga dapat dipastikan akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencapai ujungnya. Beruntung Tiara saat ini sedang berada dalam dekapan Wildan yang mampu melesat dengan sangat cepat. Perlahan-lahan Tiara bisa melihat mereka semakin mendekati titik terang. Cahaya yang tadinya hanya tertangkap dari sorot lampu taman yang berjejer rapi di tepi jalan dengan pancaran sinarnya yang redup kini berganti dengan sumber cahaya yang lebih terang. Sekumpulan cahaya yang sangat terang, seakan mampu mengalahkan kegelapan malam.
Ini, dimana?
Wildan dan Wilona telah berhenti berlari. Mereka telah sampai di ujung jalan lainnya dan kali ini menatap lurus pada sekumpulan cahaya terang yang berasal dari lampu-lampu pijar rumah penduduk. Mereka sedang berada di pinggiran kota.
Wildan menurunkan Tiara dengan hati-hati, memberi waktu untuk Tiara mengumpulkan keseimbangan agar dapat berpijak sempurna pada hamparan bumi. Kepala Tiara memang sedikit pusing karena sudah mengalami guncangan halus terus menerus selama berada di dalam dekapan Wildan.
“Apa sudah merasa lebih baik?” tanya Wilona masih dengan caranya yang begitu lemah lembut dalam bertutur kata.
Tiara hanya tersenyum simpul dan mengangguk lemah.
“Tiara, kita sudah sampai di pinggiran Kota Thames. Sementara ini kami akan membawamu ke rumah kami yang berada tidak jauh dari sini. Kau masih kuat untuk berjalan kaki sedikit?” tanya Wilona memastikan keadaan Tiara yang memang sedikit meragukan dari sosoknya yang begitu kecil dan kurus, terkesan sangat rapuh dan lemah.
Sekali lagi Tiara hanya mengangguk. Tidak ada tanda-tanda keraguan dari diri Tiara terhadap apapun yang disampaikan Wilona. Saat ini baginya Wilona adalah tempat ia menuju ketika tak tahu lagi harus bagaimana di tempat asing yang sepertinya sangat jauh dari tempat ia seharusnya berada.
Gadis kecil tak berdaya yang memilih untuk meletakkan kepercayaan kepada orang asing yang dalam sekejap mampu membuatnya merasa nyaman.
Rasa nyaman yang bagi Tiara sudah cukup untuk menghapus keraguan apapun yang bisa muncul dalam benaknya. Tiara lebih mendengar kata hatinya. Saat ini hati Tiara berbisik padanya bahwa ia harus ikut dengan Wilona dan Wildan untuk menemukan jalan pulang dari tempat asing ini.
****
“Kita sudah sampai,” ujar Wilona ketika mereka telah berada di pekarangan luas sebuah rumah yang berada terpisah dari sekumpulan rumah penduduk yang Tiara lihat selama dalam perjalanan.
Apa yang dikatakan Wilona memang benar, mereka hanya perlu berjalan sedikit memutari tepian batas kota yang terbuat dari dinding bata kokoh yang tidak begitu tinggi, hanya sebatas tinggi dada manusia, hingga mereka menemukan sebuah bangunan rumah sederhana yang berdiri kokoh, tidak begitu luas, dan agak sedikit aneh karena letaknya terasing dari lingkungan dalam kota. Satu hal yang membuat Tiara kagum, pekarangan rumah yang luas itu terlihat rapi dan terawat serta dihiasi berbagai tanaman bunga berbagai jenis.
“Kenapa rumah ini tidak berada di dalam dinding yang membatasi kota kecil itu?” tanya Tiara tiba-tiba.
Yaa, gadis kecil yang jiwanya masih sangat haus pengetahuan dan hal-hal baru beserta rasa ingin tahu yang berlebih tak bisa menahan diri untuk mempertanyakan apapun yang mengganggu benaknya.
“Kami bukan penduduk kota, kami berbeda.” celetuk Wildan singkat yang kemudian melengos pergi melewati Tiara untuk segera masuk ke dalam rumah.
“Apa maksudnya?” batin Tiara. Tapi kali ini Tiara berhasil menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Sosok Wildan agak membuatnya tak nyaman. Tiara tak mau bermasalah dengannya.
“Sudahlah, ayo kita masuk,” ujar Wilona kemudian menggandeng tangan Tiara seperti seorang kakak yang sedang menuntun adik perempuannya. Sekali lagi, Tiara hanya patuh tanpa rasa waspada sedikitpun. Yaa, karena memang tidak perlu.
Tiara kini tengah duduk manis di kursi ruang tamu. Meskipun ia ingin lebih jauh mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan hingga menelisik ke dalam ruangan-ruangan lainnya, ia masih ingat tata krama yang diajarkan oleh ibunya ketika sedang bertamu di dalam rumah orang lain.
“Tiara, kalau bertamu harus duduk manis yaa, tidak boleh ingin tahu apapun kecuali yang diperlihatkan oleh sang tuan rumah,” kata ibunya pada suatu waktu kala Tiara begitu tidak menjaga diri untuk menghindari bersikap lancang memasuki kamar-kamar di rumah salah satu keluarga mereka yang membuatnya terpukau. Sejak saat itu Tiara selalu mengingat kata-kata ibunya setiap kali ia diajak bertamu dimanapun.
Wilona telah kembali dari sebuah ruangan yang sepertinya merupakan dapur dan membawakan tiga cangkir teh panas di atas nampan. Salah satu cangkirnya diletakkan di atas meja tepat di hadapan Tiara sebagai pertanda minuman tersebut sengaja dibuat untuk disuguhkan padanya. “Minumlah, kau pasti haus,” ucap Wilona mempersilahkan Tiara. Tiara sekali lagi mengangguk dan segera meraih cangkir teh tersebut untuk kemudian meminumnya.
Wilona kini duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan tempat dimana Tiara tengah duduk. Ia memberi waktu untuk Tiara menikmati teh terlebih dulu, sebelum kemudian mengajaknya bicara. Wildan sendiri memilih duduk menjauh di sudut ruangan, pada sebuah kursi goyang yang terbuat dari kayu jati nan kokoh berwarna cokelat tua. Tempat dimana Wildan tengah duduk tepat berada di dekat jendela besar yang membuatnya mudah melihat ke arah luar untuk mengawasi situasi di pekarangan depan rumah.
“Tiara, apa kau tahu kenapa kau bisa berada di taman tadi?” tanya Wilona tiba-tiba.
Tiara hanya menggeleng lemah. Ia mencoba mengingat apapun tapi tidak ada satupun hal yang membuatnya memahami sebab keberadaannya sekarang. Bahkan Tiara masih berpikir bahwa saat ini ia tengah bermimpi dan sedang menerima dengan pasrah peran yang harus dijalani dalam mimpinya ini. Mimpi aneh yang terasa nyata.
Wilona meletakkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kaca tebal dan terlihat berkilauan di atas meja. Ia menyodorkan kotak tersebut pada Tiara agar Tiara dapat melihatnya lebih dekat dan saksama.
“Aku rasa ini yang membawamu kemari,” ucap Wilona singkat sembari mempersilahkan Tiara untuk membukanya.
“Ini, apa?” tanya Tiara begitu dikuasai rasa ingin tahu ketika telah membuka kotak tersebut. Kilau merah nan cantik dari sebuah batu kecil seukuran pupil matanya membuat Tiara begitu tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh. Bahkan batu itu seakan sengaja memancarkan sinar yang menyilaukan ketika jari-jemari Tiara tak dapat bertahan untuk tidak menyentuhnya.
“Wah!” Tiara begitu terkesima ketika mendapati batu tersebut bercahaya tiba-tiba. Tidak begitu terang namun menyilaukan sepasang pupil milik Tiara.
“Hah? Yang benar saja!” keluh Wildan dari tempatnya duduk sembari mendengus kesal saat memperhatikan interaksi antara Wilona dan Tiara. Ia tidak percaya akan batu bertuah yang mereka jaga selama ini bereaksi terhadap gadis kecil nan rapuh yang bahkan mungkin tidak mengerti apapun meskipun dijelaskan seribu kali tentang apa yang sedang mereka hadapi.
“Tiara, aku dan Wildan hidup di rumah ini sejak kami berusia sepuluh tahun di bawah asuhan Bibi Meredith. Beliau telah tiada beberapa hari yang lalu. Beliau-lah yang menjaga batu ini agar tidak jatuh di tangan orang yang salah. Sebelum meninggal, Bibi Meredith berpesan dalam hitungan beberapa hari kedepan, seseorang akan muncul di Taman Rosetta, jiwa terpilih untuk memiliki batu ini,” terang Wilona sembari kedua mata ambernya terlihat berkaca-kaca mengenang kepergian Bibi Meredith yang ia sayangi. Tiara mendengarkan dengan saksama meskipun ia masih tidak begitu paham akan penjelasan Wilona.
Batu apa?
Jiwa terpilih apa?
Kenapa?
“Sial!” hardik Wildan tiba-tiba ketika Wilona akan melanjutkan ceritanya untuk Tiara.
“Ada apa?” tanya Wilona sedikit khawatir dan segera meningkatkan kewaspadaannya.
“Mereka datang. Aku rasa mereka sudah mengetahui hal ini,” ujar Wildan masih tetap menatap ke arah jendela kaca.
Wilona segera menyimpan kotak kaca ke dalam saku mantelnya yang isinya telah dikembalikan Tiara dengan terburu-buru. Segera ia melihat ke arah luar melalui jendela lainnya yang berada tak jauh dari jangkauannya. Tiara sendiri ikut mengintip karena rasa penasaran sekali lagi menguasainya.
Mata Tiara terbelalak, membulat penuh menemukan apa yang mengalihkan perhatian Wilona dan Wildan. Di pekarangan rumah yang luas telah berbaris rapi belasan manusia yang berpenampilan aneh. Pekarangan yang tadinya indah kini terasa suram. Mereka semua terlihat serupa dengan tubuh yang terbungkus kain ketat berwarna hitam. Tiara pikir mereka bukan manusia, sebab mereka terlihat seperti boneka kain hitam polos yang mampu bergerak sendiri. Tidak ada bedanya satu sama lain, bahkan dari satu tubuh hanya bisa dibedakan sisi depan dan belakang melalui topeng putih polos yang terkesan sebagai penutuh wajah. Tiara bahkan tidak yakin mereka semua memiliki wajah.
“Para boneka. Si tua bangka itu pasti mengirim mereka setelah menyadari ajalnya sudah semakin dekat,” ucap Wildan dengan sinis. Sorot matanya begitu tajam dengan aura membunuh.
“Kita tidak boleh lengah, mereka bisa saja sangat buas sekarang,” ucap Wilona lalu beranjak dari jendela.
Wilona membawa Tiara ke sebuah pintu lemari di ruang tamu tersebut yang sejajar dengan dinding. Itu adalah lemari yang menyatu langsung dengan dinding rumah.
“Tiara, tetaplah di sini. Apapun yang terjadi, kau harus tetap di sini hingga salah satu dari kami membawamu keluar. Apa kau mengerti?” ucap Wilona terburu-buru. Tiara hanya mengangguk cepat, ia begitu gugup saat ini.
Segala sesuatu terjadi begitu cepat. Sesaat setelah Wilona menutup pintu tersebut, suara berisik dan serangan-serangan bertubi memecah keheningan ruangan. Tiara tidak berani mengintip dari balik celah pintu lemari. Ia menutup kedua matanya dan berlutut sembari terus berdoa Wilona dan Wildan akan baik-baik saja.
Tiara begitu ketakutan. Keributan dari balik pintu lemari terasa begitu kacau. Ketika Tiara merasakan sebuah cairan lengket dan hangat mengenai lututnya yang tengah bersimpuh, ia segera membuka mata dan terkejut mendapati sebuah cairan berwarna hitam pekat masuk dari celah pintu. Itu membuat Tiara mendadak berteriak.
Tiba-tiba saja pintu lemari terbuka dan Wildan segera menggendong Tiara lalu melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiara sempat melihat tubuh Wilona terkapar di depan pintu lemari tempatnya bersembunyi. Cairan pekat berwarna hitam itu dari tubuh Wilona! Dia, terluka!
Tiara tak tahu harus bersikap apa, ia hanya membiarkan dirinya pasrah dalam gendongan Wildan yang semakin menjauh dari kekacauan lalu mereka kini sudah kembali berada di taman tempat semuanya bermula, Taman Rosetta.
“Pergilah Tiara….”
Tiara tercenung, hanya bisa diam mematung masih tak berhenti menatap sepasang mata amber yang kini menatapnya dengan kilatan tak bersahabat.
Pria dihadapannya itu tak mau mengulang kata-katanya untuk kedua kalinya, mendekatinya dengan bahasa tubuh yang diliputi kegeraman hingga membuat Tiara sedikit melangkah mundur dari tempatnya berdiri.
Tubuh tegap dan kokoh itu kini hanya berjarak beberapa senti dari tubuh mungil Tiara. Melingkupinya, hingga Tiara harus sedikit mengangkat dagunya agar tetap dapat menatap lekat sepasang iris amber yang terlihat didera kecemasan.
Tiara merasakan telapak tangannya digenggam dengan cepat, meninggalkan sebongkah batu kecil berkilauan berwarna merah darah di telapak tangan mungilnya.
“Itu adalah Ratnaraj, satu-satunya yang tersisa. Bawalah bersamamu, hanya Kau yang bisa menjaganya, Tiara.”
Ketika sosok dingin itu mulai beranjak pergi meninggalkannya, Tiara segera menyusulnya lalu menggenggam tangan kekar di hadapannya, membuat jari kelingking tangan kanan mereka saling bertautan.
Bola mata amber itu kembali menatapnya, kali ini dengan diliputi oleh tanda tanya besar atas tindakan Tiara. Sebelum sebuah pertanyaan lolos dari kerongkongannya, Tiara segera angkat bicara.
“Ini disebut sebagai Pinkie Promise. Aku sedang berjanji padamu,” ucapnya cepat.
“Aku berjanji bahwa aku akan kembali dan Aku berjanji akan menjaga Ratnaraj untukmu.”
“Tiara, ratnaraj akan membawamu kembali pulang ke tempatmu berasal, duduklah di bangku itu, genggam ratnaraj dengan kedua tanganmu, berpikirlah untuk kembali ke tempat terakhir kau berada. Sekarang! Kita tidak punya banyak waktu!” perintah Wildan yang segera dipatuhi Tiara.
Meskipun masih banyak pertanyaan yang mengganjal seperti keadaan Wilona dan apapun yang tengah menimpa mereka dengan sangat cepat, Tiara memilih memikirkan kembali jalan pulang. Semoga semua ini hanya mimpi.
Sebuah gaya tarik seperti menyedot jiwa dan raga Tiara yang tengah duduk di bangku taman sembari memejamkan matanya. Dan ketika Tiara membuka mata perlahan, jarak pandangnya kini telah berbatas oleh atap ruangan yang ia kenal sebagai plafon ruang perpustakaan mini.
Hujan di luar sudah reda dan mendung telah berganti cerah. Tiara bangkit dari tempatnya berbaring, segera merapikan semua buku yang tergeletak serampangan di sekitarnya lalu bercermin sebentar di depan cermin yang tergantung di dinding samping pintu toilet.
Tiara meyakinkan dirinya bahwa ia hanya tengah bermimpi. Wajahnya bersih, tak ada noda kotor sedikitpun melekat pada tubuhnya. Tiara rasa semua itu memang hanya mimpi. Tiara menarik nafas lega dan beranjak keluar dari perpustakaan untuk kembali pulang ke rumahnya.
Tapi Tiara tak menyadari sebuah kalung hadiah ulang tahun dari orangtuanya, berbandul batu permata merah yang melingkar di lehernya, kini memiliki pancaran sinar yang berbeda. Disitulah ratnaraj bersemayam.
Dan semesta dimana ratnaraj berasal telah mendengar janji Tiara.
Akan tiba saat di mana Tiara harus kembali dan menepati pinkie promise yang telah ia ucapkan, bahkan jika itu hanyalah janji gadis kecil yang tak mengerti apapun.
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 4. Sepasang Manusia
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
Tiara hanya bisa tertegun, tak sedikitpun ingin bangkit dari tempatnya terduduk kaku. Rasa sakit yang terasa pada tulang ekornya kini dalam pengabaian Tiara, sebab saat ini ia lebih tertarik untuk memperhatikan dengan saksama penampilan pria asing di depan matanya.
Pria itu memakai pakaian serba hitam dan tak terlihat seperti model pakaian yang biasanya Tiara temukan selama ini. Pria pemilik rambut pendek berwarna hitam legam lurus yang setiap surainya nampak menyentuh sedikit pada kedua daun telinganya itu menggunakan semacam kaos ketat berwarna hitam yang kemudian dilapisi semacam mantel kulit berwarna senada. Mantel lengan panjang yang ujung bawahnya mencapai lutut itu menyembunyikan sebuah sarung pedang yang sabuknya disampirkan pria itu pada lingkaran pinggangnya. Celana panjang yang dikenakannya pun juga berwarna hitam, dipadukan dengan sepasang sepatu boots selutut yang terlihat tebal, kokoh, bahkan mungkin berat jika diperhatikan dari alasnya yang merupakan sol karet yang cukup tebal. Penampilannya yang serba hitam terkesan misterius dan kontras dengan kulit tubuh yang tak tertutup pada bagian leher dan wajahnya yang tergolong pemilik pigmen kulit putih cerah.
“Hei! Bangun!” bentak Pria itu lagi ketika melihat Tiara tak bergeming sedikitpun.
Jantung Tiara berdegup kencang seakan siap melompat dari rongga dadanya. Pria yang tengah berdiri di hadapannya tak sedikitpun melunakkan sikapnya meski Tiara hanyalah seorang gadis kecil bertubuh kurus dan terlihat lemah serta jelas sekali menunjukkan rasa takut yang begitu kuat.
Raut wajah Tiara begitu mendung, air matanya tak bisa dipertahankan lagi. Alih-alih mematuhi perintah si pria untuk segera berdiri, Tiara malah mulai menangis sesenggukkan. Dan tak sampai sepersekian detik berlalu, tangisnya mulai pecah menjadi raungan yang tak terkendali. Tiara ketakutan!
“Hei, diam!” bentak pria itu.
Pria itu terlihat kesal. Sepasang mata hazel milik Tiara segera menutup rapat ketika ia mendapati Pria itu mulai menghampirinya dengan gusar seakan ingin menyerangnya tanpa belas kasihan.
“BUKK!”
Bunyi dentuman keras membuat Tiara menjerit tertahan masih dengan matanya yang setia terpejam seakan kelopak matanya memiliki kekuatan ajaib untuk melindungi seluruh tubuhnya dari serangan hanya dengan cara sederhana, menutup mata!
Tiara menunggu rasa nyeri yang diperkirakannya akan segera muncul dari bagian tubuhnya yang terkena pukulan.
Tapi….
“WADAWWW! SAKIT!”
Sebuah jeritan yang terdengar keras membuat Tiara terkejut hingga memaksanya kembali membuka mata karena terserang rasa penasaran dari asal suara yang menggelegar itu. Ia tak merasakan sentuhan apapun mengenai tubuhnya dan rintihan rasa sakit yang baru saja didengarnya berasal dari pria yang tadinya akan menyerangnya.
Mata Tiara seketika terbelalak melihat pemandangan tak masuk akal di depannya. Pria itu kini tengah terduduk sembari memegang kepala dengan kedua tangannya, persis seperti anak kecil yang sedang kesakitan. Itu benar-benar tak seperti dugaan, pria itu meringis!
“Sialan! Wilonaaaaaaaa….!” pekiknya.
Kali ini mata Tiara tertarik untuk menatap ke arah sosok manusia lain yang berdiri angkuh di samping pria itu dan sekilas membuat Tiara merasa terpukau.
Seorang wanita!
Wanita yang sangat cantik!
Wanita itu terlihat sebaya dengan si pria berjubah hitam. Berbeda dengan si pria, kali ini secara tidak langsung Tiara dapat menyimpulkan nama wanita itu kemungkinan adalah Wilona.
“Bodoh, apa yang kau lakukan? Cukup bercandanya!” ucap wanita itu tegas sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
“Hei, tadi kau bilang aku boleh menyapa dengan caraku!” ucap pria itu yang kini sudah berdiri tegak membusungkan dadanya di hadapan si wanita.
Pria itu memang tinggi menjulang. Wanita yang tengah berdiri di hadapannya bahkan hanya sejajar dengan bahunya saja. Tapi, tatapan mata wanita itu seakan tidak gentar dengan gertakan si pria. Wanita pemilik mata amber yang sama dengan si pria, bahkan mereka rasanya terlihat serupa, begitu berani melemparkan sorot pandang yang lebih tajam dan menusuk kepada si pria.
Mereka kini tengah asyik berdebat ringan dan seakan mengabaikan kehadiran Tiara yang masih diam termangu tak tahu harus mengambil sikap bagaimana atas kejadian yang baru saja tersaji di depan matanya. Sepertinya sepasang manusia di hadapannya itu adalah saudara kembar, hanya saja yang satu pria dan satunya wanita. Tapi mungkin saja Tiara salah menduga. Yang bisa Tiara pastikan adalah keduanya berparas nyaris mewakili kesempurnaan penciptaan manusia.
Tampan dan cantik!
Tiara si gadis kecil merasa bingung, ada apa sebenarnya?
Dalam benaknya tak kunjung berhenti mempertanyakan, siapa mereka?
Kendati Tiara tengah dalam titik kebingungan, rasa takut yang sebelumnya melingkupinya kini telah menguar, lenyap begitu saja sejak kemunculan si wanita. Wanita itu seperti malaikat penolong untuk Tiara. Setidaknya ia tak merasa sendirian lagi.
Wanita cantik, sungguh mempesona. Sepasang mata ambernya terlihat lebih bersinar dari si pria. Mata itu tak setajam mata si pria yang sekarang Tiara tak bisa memastikan mau menyebutnya sebagai pria yang menakutkan atau pria yang kekanak-kanakkan setelah adegan yang baru saja tertangkap olehnya. Wanita itu memiliki aura yang lembut bahkan meskipun saat ini ia terlihat tengah melontarkan berbagai omelan tak berujung untuk si pria.
Wanita itu memiliki surai rambut berwarna hitam kecokelatan, panjang bergelombang mencapai batas siku kedua lengannya. Samar-samar di bawah sinar rembulan, kesan warna kecokelatan pada rambutnya terlihat berkilauan. Pakaiannya sendiri tak jauh berbeda dengan si pria, hanya saja sepatu bootsnya terlihat lebih feminim serta sabuk yang melingkar di pinggangnya tidak digunakan untuk membawa sarung pedang tunggal, melainkan pada sisi kiri dan kanan pinggangnya terdapat seperti dua pedang kecil yang berbentuk seperti garpu tala. Melihat mereka berdua berdiri berhadapan sembari masih sibuk berdebat membuat Tiara semakin yakin keduanya adalah saudara kembar. Mereka terlalu serupa jika ingin dikatakan sebagai sepasang kekasih atau sekedar kakak beradik.
Satu hal yang masih menyisakan tanda tanya besar bagi Tiara, mengapa mereka harus memiliki senjata tajam pada diri mereka? Untuk apa?
“Jaga sikapmu, Wildan!” ucap wanita itu tegas mengakhiri perdebatan.
Oh, ternyata namanya Wildan.
Wanita itu kini mengabaikan Wildan yang menunjukkan wajah bersungut-sungut kesal. Sepertinya pukulan yang dihadiahkan Wilona pada kepalanya sangat tidak bisa ia terima sedikitpun seakan itu sangay meruntuhkan harga dirinya. Wilona melangkah perlahan tapi pasti untuk menghampiri Tiara. Ia mendekat dan menunjukkan senyum manis yang menghangatkan perasaan Tiara lalu diulurkan tangannya agar dapat membantu Tiara kembali berdiri.
“Apa kau baik-baik saja?” tanyanya dengan lemah lembut, jauh berbeda dari caranya bersikap terhadap Wildan.
Tiara hanya mengangguk pelan lalu tanpa ragu menyambut telapak tangan berbalut sarung tangan lateks berwarna hitam milik Wilona. Terasa dingin ketika kulit telapak tangan Tiara bersentuhan langsung dengan bahan sarung tangan milik Wilona.
“Siapa namamu?” tanyanya lagi setelah Tiara telah berdiri sembari menepuk-nepuk rumbai rok selututnya yang agak kotor oleh dedaunan kering di lantai taman.
“T-t-tiara, Tante….” ucap Tiara agak ragu memberi sapaan yang pantas untuk wanita cantik dihadapannya. Tapi wanita itu jauh lebih tua darinya sehingga ia merasa memanggilnya tante merupakan sebuah sikap tepat untuk menghormati Wilona.
“BWAHAHAHAHA!” tawa Wildan mendadak meledak tak terkira mendengar ucapan Tiara. Raut wajahnya menunjukkan kepuasan tak terperi.
Wilona sendiri kini menekuk wajahnya yang kemudian menunjukkan rona gelap karena merasa terintimidasi oleh gelak tawa penuh kepuasan dari Wildan yang berdiri sedikit berjarak di belakangnya.
“Tiara, gadis kecil yang baik, apa aku terlihat seperti seorang tante-tante untukmu?” ucap Wilona memaksakan diri tetap bertutur lemah lembut dengan nada bergetar nan lirih hampir tak tertangkap oleh kedua telinga Tiara, terlebih lagi ucapan Wilona terdistraksi oleh tawa terbahak-bahak milik Wildan yang masih terus membahana tanpa jeda.
“Diam!” rutuk Wilona yang kemudian menolehkan kepalanya ke arah Wildan sembari memberi tatapan membunuh.
Wildan segera berdiri tegak seolah siap melakukan hormat bendera, namun tangan kanannya lebih digunakan untuk menarik garis pada bibirnya yang terkatup rapat tanda patuh oleh perintah Wilona. Tentu saja itu tidak bertahan lama sebab Wildan kini masih berusaha menahan cekikikan yang nyaris lolos dari kerongkongannya.
Wilona menjadi kesal.
Tiara jadi merasa bersalah.
“Maaf nona, saya tidak bermaksud mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Saya hanya bingung,” ucap Tiara berusaha bersikap sopan dan berharap permintaan maafnya dapat memperbaiki suasana hati Wilona.
Wilona menghela nafas panjang, ia kini memilih tidak memperpanjang pembahasan yang dirasa tidak penting untuk terus dilanjutkan, “Sudahlah, lupakan saja,” ujarnya.
“Tiara, kenalkan aku Wilona dan pria bodoh yang kau lihat di belakang itu adalah Wildan,” ucap Wilona memperkenalkan diri dengan ramah.
“Wilona, Wildan,” ucap Tiara mengulang kedua nama yang didengarnya agar ia dapat mengingatnya dengan baik.
“Benar sekali,” ucap Wilona lagi mengapresiasi perilaku sederhana yang dilakukan Tiara.
“Panggil saja aku Wilona yaa,” tambahnya lagi. Tiara hanya mengangguk tanda mengerti.
“Kalau dia, kau bisa memanggilnya sesukamu, bahkan jika kau ingin kau boleh memanggilnya bodoh sekalian!” rutuk Wilona sambil melirik Wildan yang terlihat tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Wilona untuknya.
“Apa, apakah kalian kembar?” tanya Tiara kemudian mencoba menemukan jawaban dari rasa penasaran yang masih mengganggunya.
“Benar sekali gadis cantik, kami kembar,” jawab Wilona mengiyakan pernyataan Tiara.
“Hei, sebaiknya kita segera pergi dari sini.” celetuk Wildan yang kini memperlihatkan raut wajah waspada.
Wilona mengangguk tanda mengerti dengan ucapan Wildan. Kali ini Wildan melangkah maju mendekati Tiara, “Gadis kecil, kita harus pergi dari tempat ini, agar lebih cepat, sebaiknya kau ikut denganku saja.”
Tiara yang sedikit bingung dan baru saja ingin mengajukan pertanyaan kini harus terkejut untuk kesekian kalinya. Wildan tanpa aba-aba segera menggendongnya dan mereka kini melesat pergi menyusuri jalan setapak dengan kecepatan yang tak seperti milik manusia pada umumnya sebelum Tiara sempat bereaksi melakukan penolakan atau memberi sikap apapun yang pantas atas apa yang dilakukan Wildan.
Tak ada sepatah kata apapun yang terlontar dari ketiga manusia yang hanya terus melesat dalam kegelapan malam. Tiara sendiri tak dapat melihat pemandangan apapun disekitar yang tengah mereka lewati. Mereka begitu cepat!
Tiara hanya bisa membenamkan wajahnya dalam-dalam di dada bidang milik Wildan dan melingkarkan erat kedua tangannya pada tengkuk Wildan sebagai usahanya menjaga diri agar tak lepas dari pegangan Wildan yang terlihat menggendongnya tanpa kesulitan meskipun tengah berlari sangat kencang. Wilona sendiri sama cepatnya dengan Wildan dan berusaha tetap menjaga agar dirinya terus melesat berdampingan bersama kembarannya itu.
Ini, mau kemana?
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 3. Asing
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
Tiara merasakan seluruh tubuhnya terasa sejuk berlebihan seolah semilir angin yang begitu dingin sedang menusuk hingga menembus seluruh tulang belulang yang dibalut oleh kulit tipis dari tubuh mungilnya.
“Dingin,” batin Tiara yang masih tetap memejamkan kedua matanya dan memeluk tubuhnya sendiri erat-erat. Tiara merasa sangat enggan untuk terbangun dari tidurnya dan membutuhkan kehangatan.
Lambat laun Tiara semakin merasa tidak nyaman, ia mulai menggigil. Suara denting bertalu-talu yang berasal dari dentuman hujan deras di luar perpustakaan mini yang tadinya terasa begitu berbaik hati menjadi lagu pengantar tidurnya, kini terasa lenyap tak berbekas, begitu hening dan hanya meninggalkan jejak rasa dingin yang menusuk dan seakan tak jenuh mengusik tidur Tiara.
Tubuh Tiara terasa sedikit ngilu. Seingat Tiara, ia sedang membaringkan tubuhnya di atas karpet beludru lembut dengan ketebalan yang empuk sehingga sangat nyaman disaat terakhir ia akan sampai pada kondisi terlelap. Tapi, saat ini Tiara merasakan tubuhnya seperti sedang terbaring di atas papan kayu keras yang terasa lembab dan sekali lagi, dingin.
Sayup-sayup sembari mengumpulkan kesadaran, Tiara bahkan bisa merasakan rintik hujan seakan menjelma menjadi percikan halus yang meskipun terasa jarang-jarang namun sepertinya sedang menghujam langsung mengenai kulit tipis tubuhnya.
Aku di dalam ruangan kan?
Apa ada atap yang ternyata bocor?
Tiara mulai merasa ada yang ganjil dan perlahan-lahan ia memaksakan diri membuka kedua pasang matanya. Samar-samar Tiara dapat menangkap pemandangan yang terasa berbeda dari yang seharusnya ia kenal sedang terpampang nyata di depan mata kepalanya. Kedua bola mata Tiara membulat penuh, ia terbelalak seketika.
Semuanya gelap, dingin, lembab, dan asing!
Tiara terperanjat, ia segera bangkit dari tidurnya dan terduduk, “Hah! Aku ada di mana?” pekiknya dalam hati.
Ini tempat apa?
Tiara mendapati dirinya tengah duduk di sebuah bangku taman yang sepi, pada malam hari yang pekat dan hanya diterangi sorot sebuah lampu taman yang enggan bersinar terang, lebih redup dari sinar rembulan, dan Tiara juga sendirian. Hanya gerimis halus yang turun terus menerus setia menemaninya. Tiara terus mempertanyakan keadaan yang sedang menimpa dirinya, adakah semua ini nyata atau ia sedang bermimpi?
Tiara menepuk kedua pipinya dengan kedua telapak tangan mungil nan halus miliknya, berpikir bahwa itu akan membuatnya terbangun dari ilusi alam bawah sadarnya yang sedang mempermainkan logikanya.
Ini mimpi, ‘kan?
Tak kunjung tersadar dan merasa sudah lelah menepuk halus kedua pipinya yang dikhawatirkan Tiara hanya akan menimbulkan memar tak wajar bila ia menambah lagi dan lagi tepukan pada wajahnya, Tiara memutuskan menghentikan apa yang sudah ia lakukan.
Tiara memperhatikan suasana sekitar taman dari posisi duduknya. Taman itu seperti akhir dari sebuah jalan setapak. Area dari tempat dimana ia duduk adalah sebuah taman air mancur berbentuk lingkaran yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup semacam semak belukar berupa dedaunan kecil yang rimbun berwarna hijau segar, terlihat indah dengan bunga-bunga berwarna putih bersih yang memancarkan cahaya tersendiri di bawah sorot lampu taman. Sedikit ragu memastikan tapi Tiara berpikir bebungaan yang dilihatnya adalah sejenis mawar putih.
Mungkin?
Sisi luar dari batas lingkaran taman hanyalah memperlihatkan sekumpulan pohon-pohon rimbun tinggi menjulang seolah membentuk seperti hutan buatan dalam kota. Tiara tidak begitu berani menelisik lebih jauh menembus kegelapan diantara pepohonan yang melingkupi area taman. Sepintas lalu ia takut menemukan banyak sepasang mata berkilat dari hewan-hewan nokturnal penghuni hutan yang barangkali tengah mengintainya dari dalam sana.
“Tempat apa ini?” batin Tiara dengan menyimpan rasa kalut dan takut yang sulit ia gambarkan.
Di tengah area taman terdapat kolam air mancur dengan diameter yang tidak cukup besar, yang pada bagian pemancar air di tengah-tengah kolam tampak berbentuk seperti bunga besar yang tengah merekahkan kelopaknya namun tak memancarkan air sedikitpun. Sepertinya bagian pemancar air tersebut sudah tidak berfungsi untuk waktu yang cukup lama.
Tempat di mana Tiara duduk adalah sebuah bangku taman satu-satunya di tempat itu. Tiara memperhatikan bangku taman yang tengah didudukinya memiliki ukiran-ukiran pada keempat kakinya yang terbuat dari besi berwarna hitam, begitupun pada bagian lengan bangku. Tidak ada yang istimewa dari bangku tersebut, biasa saja. Hanya sedikit aneh mengetahui bangku tersebut hanya ada satu-satunya di taman itu, serta hanya bisa digunakan oleh sepasang manusia saja. Seperti bangku taman yang biasa digunakan para pasangan untuk bermesraan di taman umum tanpa tahu malu.
Sepasang kekasih yang mengira dunia tercipta hanyalah sebagai milik mereka berdua saja, semacam itu.
Tiara menghela nafas panjang sebagai cara untuk menenangkan dirinya sendiri. Tiara memang terlihat tenang dan seakan masih berada di titik linglung atas apa yang sedang menimpanya. Tiara tidak berpikir untuk lari menghambur pergi secara membabi buta, pun tidak tahu apakah duduk diam di tempat itu akan memberi dia jalan keluar. Ia hanya masih merasa percaya bahwa ia sedang bermimpi, mungkin setengah bermimpi, mungkin juga ini sebuah petualangan yang tak bisa dicerna dengan logika. Entah, Tiara tidak tahu. Ini seperti distorsi baginya.
Tiara mulai beranjak dari duduknya. Gerimis halus masih menemaninya malam itu. Insting Tiara mulai aktif dan menyadari bahwa berdiam diri di tempat itu tidak akan memberikan pencerahan apapun. Ia tahu ia sedang berada di ujung sebuah jalan setapak dan lebih baik ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak tersebut hingga mencapai ujung lainnya. Barangkali di ujung jalan lainnya ia akan menemukan sesuatu yang lebih berarti. Toh, jalan itu walaupun hanyalah sebuah jalan kecil yang tampaknya hanya mampu memuat dua manusia bila berjalan bersisian, setidaknya dipenuhi oleh lampu sorot di tepi kanan-kirinya, meski redup.
Manusia terkadang lebih baik berjalan menuju cahaya, bukan berdiam diri apalagi semakin jauh memasuki kegelapan.
Tiara tidak mau terlalu berpikir banyak lagi, tubuhnya sudah tidak tertarik terus-terusan dihujam gerimis halus yang lambat laun akan menjadikannya tubuhnya semakin basah. Ia harus pergi dari tempat itu dan berharap ada persinggahan lain yang memiliki tempat untuk berteduh atau lebih baik lagi sebuah jalan pulang, kembali ke tempat di mana seingatnya raganya tengah berbaring pulas di karpet beludru lembut dalam perpustakaan mini.
Barangkali ini memang mimpi yang masih ingin Tiara bermain peran di dalamnya, masih enggan mengembalikan jiwa Tiara kembali bersatu bersama raganya.
****
Baru saja Tiara mulai membuat langkah pertama untuk menyusuri jalan tersebut, mendadak ia merasa ingin memetik satu saja bebungaan yang menurutnya adalah sejenis mawar putih. Alangkah cantiknya menyusuri jalan setapak dengan langkah-langkah kecil yang menggemaskan sembari memainkan sekuntum bunga putih bersih dengan kedua telapak tangannya. Tak lupa senyum ceria yang tersungging indah selama sepanjang perjalanan, pastilah akan menyenangkan.
Begitulah khayalan Tiara.
Rasa takutnya sedikit mulai sedikit mulai sirna setelah ada harapan yang menyelimuti Tiara akan sumber cahaya di ujung jalan, ditambah dengan khayalannya yang sedang memuja dirinya sendiri.
Tiara membelokkan langkah kakinya menuju tepi taman, mendekati salah satu bunga putih yang terlihat paling merekah indah di matanya, begitu menggoda untuk dimiliki.
Telapak tangan mungil Tiara telah berayun bebas di udara dan siap untuk memetik bunga tersebut bersamaan dengan tiba-tiba saja sebuah tangan yang terlihat kekar dan lebih besar dari ukuran tangannya dibalut oleh sarung tangan hitam pekat dari bahan lateks telah berhasil menepisnya dengan cara memukul punggung telapak tangan Tiara dengan kasar, “Plak!”
Tiara terperanjat dan dengan cepat menoleh ke sisi kanannya di mana telah berdiri sosok tinggi menjulang berjubah hitam yang lagi-lagi terasa asing.
“Aaah!” pekik Tiara yang kemudian dengan cepat memaksa mulutnya untuk terkatup dengan kedua telapak tangan mungilnya.
Langkah Tiara pun mundur ke belakang beberapa langkah hingga ia akhirnya tersungkur di lantai karena tak mampu mengendalikan keseimbangan tubuh lantaran terpengaruh kepanikan yang berhasil memberi benturan keras pada tulang ekornya.
“S-s-siapa?” gumam Tiara lirih, menggantikan reaksi meringis yang seharusnya ia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia tengah kesakitan.
Sepasang mata hazel milik Tiara bersirobok dengan mata amber yang kini tengah menatap tajam ke arah Tiara dari sudut ekor matanya. Tiara terbelalak dan jantungnya tak bisa berhenti berdegup kencang. Berdetak seperti dentuman-dentuman keras yang menguasai seluruh jiwa raganya hingga seluruh panca inderanya terasa mengalami disfungsi sesaat.
Kenapa saat dia sendirian sebelumnya rasanya tidak semenakutkan saat sekarang ia bertemu dengan sosok seorang manusia?
Seorang pria dewasa, seorang Tuan?
Sosok pria itu tidak buruk rupa, bukan sejenis pangeran yang menjelma menjadi makhluk buas atau apapun yang mengerikan dari beberapa buku dongeng yang pernah dibaca oleh Tiara. Itu sosok pria seperti manusia pada umumnya, bahkan meskipun Tiara masih seorang gadis kecil berusia 13 tahun, ia bisa menilai dengan baik bahwa pemilik mata amber itu adalah pria yang terlihat berpenampilan menarik, tampan dan rupawan, hanya saja auranya lebih menakutkan daripada ancaman lainnya yang mungkin bisa menghampiri Tiara saat ini.
Pria itu tidak bergeming dari tempatnya berdiri, pun tak menoleh sedikitpun ke arah Tiara yang masih tersungkur bahkan mematung sempurna seakan siap mati mendadak, seakan ia merasa sudah cukup melihat Tiara hanya dengan lirikan tajam saja. Dalam kepanikannya, hanya sebuah gerakan kecil yang bisa dilakukan Tiara, menenggak air liurnya sendiri.
“Berani sekali kau berniat merusak taman ini?” ucap suara berat yang berasal dari pria di depan mata Tiara. Suara itu terdengar lirih namun terasa mencekam di telinga Tiara. Rasanya Tiara ingin menangis, kali ini ia benar-benar merasa berada di tempat yang tak seharusnya.
“Bangun!” perintahnya.
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 2. Solitude
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
Ya, sesekali Tiara juga berpikir seegois itu, ingin perpustakaan itu untuk dirinya sendiri.
Tiara melihat jam sudah menunjukkan pukul 09.15 waktu setempat. Sudah lima belas menit berlalu dari jadwal buka perpustakaan, tapi Tiara belum melihat satupun pengunjung mendatanginya. Padahal biasanya akan ada segelintir anak yang mulai berdatangan bahkan sebelum Tiara sempat mempersiapkan segalanya terlebih dulu. Karena itulah, Tiara selalu menyempatkan diri untuk berbenah ruangan sebelum pulang sehingga ketika ia harus menghadapi situasi kehadiran anak-anak yang lebih awal dari jadwal buka perpustakaan, ia tak perlu khawatir dengan kelayakan ruangan yang memang sudah dibersihkan sebelumnya. Cerdik sekali.
Tiara menghampiri pintu, memastikan bahwa dia tidak salah memasang papan di depan pintu masuk. Barangkali papan tersebut masih bertuliskan “TUTUP” hingga para pengunjung yang mungkin sudah datang akhirnya kembali pergi karena kelalaian Tiara. Tiara berharap ia tidak melakukan kesalahan fatal semacam itu, meski terkesan sepele, namun memupuskan harapan pengunjung yang datang karena kelalaian semacam itu akan membuat Tiara dihantui rasa bersalah.
“Hmm… Tulisan di papan sudah benar,” gumam Tiara.
Tiara melihat ke arah luar, membuka pintu dan mendongakkan kepalanya ke langit. Tiara melihat awan yang setahunya sangat cerah telah berubah gelap. Sangat gelap dalam sekejap hingga rasanya mustahil tak akan turun hujan.
Benar saja, belum sempat Tiara masuk kembali ke dalam ruang perpustakaan, hujan turun bergerilya tanpa aba-aba, langsung menghujam ke bumi dengan angin yang ikut berhembus riang seolah menambah kekacauan saat itu.
Tiara segera masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Meski hujan tak mungkin membuka gagang pintu dengan tangan kosong, Tiara tetap mengunci pintunya dari dalam.
Dilihatnya dari balik kaca pintu perpustakaan, suasana di luar sudah menjadi basah, dingin, dan agak kacau. Pepohonan yang berdiri kokoh berdampingan di pinggir jalan meliak-liuk diterpa angin, sebagian dedaunan beterbangan tak mampu lagi berpegangan dengan dahannya. Jalanan terlihat tergenang sedikit air yang aktif bergerak mengikuti arus kelandaiannya.
“Astaga, bagaimana mungkin ini terjadi?” Tiara berdecak heran, hanya bicara dengan dirinya sendiri.
Tiara kembali duduk di kursinya. Tiara duduk menopang dagu sembari melihat sekeliling ruangan perpustakaan yang rapi dan nyaman meskipun sebenarnya dari balik pintu kaca perpustakaan Dia masih bisa melihat suasana yang agak kacau di luar sana akibat ulah nakal si hujan deras dan angin ribut.
“Hmm… Aku harus mengabari Ibu di rumah,” gumam Tiara lalu kemudian menggunakan telepon yang ada di meja administrasi, sebuah telepon berwarna abu-abu rokok berbentuk kotak dan memiliki tombol putar memenuhinya.
Kemudian Tiara memutar beberapa angka yang akan menyambungkannya pada telepon yang sama baik bentuk dan warnanya yang saat ini bertengger manis di meja sudut ruang tamu rumahnya.
Syukurlah tak perlu menunggu lama hingga Ia bisa mendengar suara parau milik Bibi Paula yang mengangkat teleponnya.
“Halo, kediaman Keluarga Ferdinan,” sapa Bibi Paula dengan suara yang dibuat lembut dan santun.
“Halo, Bi… Ini, Tiara….” sambut Tiara dengan sedikit menaikkan volume suaranya agar Bibi Paula dapat mendengarnya dengan jelas mengingat suaranya yang memang kecil ditambah dengan gemerisik suara derasnya hujan dari luar perpustakaan yang berhasil meredam suaranya.
“Iya, Non… Mau dijemput?” tanya Bibi Paula, mencoba menebak maksud dan tujuan Tiara menelepon ke rumah dari ruang perpustakaan.
“Bukan… Tolong sampaikan sama Ibu, kalau Tiara baik-baik aja. Tiara disini saja sampai hujan reda dan pulang sendiri,” cercah Tiara terburu-buru menjelaskan dan merasa ingin segera mengakhiri telepon karena merasa sangat tak nyaman dengan suara berisik hujan di luar ruangan.
“Baik, Non….” Jawab Bibi Paula dengan nada kepatuhan yang santun.
Tiara buru-buru menutup teleponnya dan tersenyum riang setelahnya. Ia merapikan gaunnya yang agak lembab terkena cipratan halus dari rintik hujan yang sempat tertiup angin ke arahnya ketika tadi menengok awan gelap di luar ruang perpustakaan mininya.
Gaun merah mudanya mungkin agak sedikit lembab tapi Tiara tahu itu bukan masalah besar, suhu tubuhnya akan membantu mengeringkan pakaiannya dengan sendirinya jika hanya sebatas lembab.
Tiara berdiri di tengah ruangan, berkacak pinggang, menghembuskan nafas pendek, tersenyum riang dengan sedikit menampilkan raut wajah yang kocak. Bola matanya berputar dan menyisir seluruh ruangan perpustakaan.
Hening, tenang, nyaman, dan suasana hujan di luar bukanlah sesuatu yang menakutkan baginya melainkan ini adalah momen yang menyenangkan untuk Tiara.
Tiara mengangkat kedua tangannya setinggi mungkin, melepaskan perasaan riang yang meronta-ronta di dalam dadanya dengan memekik kegirangan tanpa tahu malu sebab ia sadar takkan ada orang lain yang akan menyadarinya tingkahnya saat ini. Tiara, sendirian.
“Yeayy, Aku sendirian!” soraknya penuh rasa gembira yang membuncah seakan sepasang sayap kupu-kupu tengah berkepak-kepak di balik punggungnya.
“Sendirian, di perpustakaan mini, hujan lebat, akhirnya aku mendapatkan momen ini!” pekiknya dalam hati dan yang terlihat hanyalah telapak tangannya yang kurus menutupi mulutnya yang dipaksanya terkatup menahan tawa cekikikan yang mencoba keluar dari pita suaranya.
Tiara memeluk tubuhnya sendiri, mengusap kedua lengannya, dan secara sadar merasakan suhu di dalam ruangan sudah terlalu dingin. Diambilnya remote mesin pendingin kemudian menaikkan suhunya sedikit untuk memperoleh kesejukan yang tepat untuk tubuhnya saat ini.
Tiara merogoh tas selempang yang sedari tadi Ia gantungkan secara asal di sandaran kursinya. Tiara mencari kotak bekal dan botol minuman yang sudah dibawanya dari rumah. Membawanya dengan hati-hati dan meletakkannya di salah satu meja baca.
Kali ini Tiara mengambil beberapa buku secara acak dari dalam rak. Tiara mengambil masing-masing satu buku dari kedelapan rak yang berdiri kokoh memenuhi sisi kanan dan kiri dinding ruangan hingga kini tangan kecilnya telah memeluk delapan buku dengan agak kewalahan. Tiara kembali membawanya dengan perlahan, meletakkannya di meja baca dimana Ia letakkan bekalnya sebelumnya.
Tiara duduk bersimpuh, mencari posisi duduk senyaman mungkin dan mulai membuka bekalnya terlebih dulu. Suhu dingin pada akhirnya membuat tubuhnya terlalu banyak mengubah kalori menjadi energi untuk menghangatkan tubuhnya dari dalam sehingga Tiara harus kembali mengisi lambungnya dengan asupan makanan untuk menggantikan kalori-kalori sebelumnya yang telah hilang atas jasanya menguatkan suhu tubuh Tiara.
Pada intinya, Tiara lapar.
Dua buah roti panggang berbentuk segitiga hasil dari cetakan mesin toaster memenuhi ruang kotak bekal Tiara. Roti panggang dengan isian parutan keju cheddar dan krimer kental manis adalah favorit Tiara. Tiara melahap bekalnya dengan riang.
Selesai melahap habis semua roti panggang di dalam kotak bekal, Tiara membuka botol minumnya yang lebih mirip seperti termos mini. Botol tersebut mampu mengawetkan suhu panas cairan di dalamnya, sehingga susu cokelat milik Tiara masih hangat seperti baru saja diseduh. Tiara menenggak minumnya tanpa jeda, membiarkan sensasi hangat dari susu cokelat dengan perisa manis yang menerobos kerongkongannya kini terasa nyaman di lambungnya.
Kenyang. Puas.
Tiara mengemas bersih seluruh peralatan makannya, memasukkan kembali ke dalam tas selempangnya dan kemudian kembali duduk untuk menikmati buku-buku yang sudah di ambilnya dari rak buku.
Satu persatu Tiara mulai membaca buku pilihannya, ditemani hujan lebat yang seolah tak jenuh untuk bertahan dengan gemerisiknya.
Tak ada tanda-tanda hujan akan reda, namun Tiara tak peduli. Semua keadaan yang terjadi saat ini seperti momen sempurna bagi Tiara.
Hari minggu, sendirian di perpustakaan mini, ditemani hujan lebat yang menyenangkan bagi Tiara. Tiara sungguh menikmati kesendirian yang tercipta.
Tiara takkan bosan membunuh waktu dengan diam di dalam ruangan perpustakaan mini bertemankan buku-buku yang siap menghantarnya dalam imajinasi tanpa batas atau sekedar memasukkan wawasan-wawasan baru sebagai santapan lezat untuknya yang haus berbagai ilmu pengetahuan.
Ya, membaca adalah suatu kesenangan tersendiri bagi Tiara.
Pada akhirnya, meskipun rasa bosan tak mungkin menyerang Tiara, namun sejuknya ruangan, rasa nyaman dalam kesendirian, dan alunan gemerisik hujan yang berdentum tiada habisnya sukses menciptakan rasa kantuk yang hebat untuk Tiara. Di buku keempat yang dibacanya, Tiara merasa matanya mulai lelah.
Tiara mengambil bantal lesehan yang besar dan empuk. Meletakkan kepalanya di atas bantal dan membaringkan tubuhnya di karpet bulu beludru yang empuk dan membuatnya merasa semakin mengantuk. Semakin berat hingga Ia menyingkirkan buku yang sedang di bacanya, diletakkan tepat di samping tubuhnya secara sembarangan.
“Tutup mata sejenak sepertinya tidak masalah….”
****
Bersambung~

Pinkie Promise: 1. Tiara
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
Di suatu pagi yang cerah, ketika matahari telah bersinar hangat dan bersahabat sehingga begitu menyenangkan untuk disambut dengan jiwa yang bersemangat, dari sebuah rumah bernuansa putih dan dikelilingi hamparan rerumputan hijau sehingga terkesan kontras satu sama lain, terlihat seorang gadis belia yang berusaha keras menggeser pintu rumahnya yang lebih mirip seperti bingkai kaca berbentuk persegi empat berukuran besar layaknya sisi-sisi dinding lainnya.
Dari dalam rumah, dengan terburu-buru seorang wanita paruh baya menghampirinya dan membantunya menggeser pintu lalu kemudian menuntun gadis tersebut untuk duduk di kursi putih yang tersusun elegan di teras rumah.
Perempuan paruh baya itu kemudian mengambil sepatu mungil berwarna cokelat dari rak sepatu di sudut teras untuk dikenakannya ke sepasang kaki jenjang milik gadis belia yang tengah duduk manis sambil memainkan kunci dalam genggamannya.
“Bibi, aku bisa memakainya sendiri. Terimakasih bantuannya,” ujar gadis belia itu dengan santun sebagai bentuk penolakan halus atas bantuan yang akan diberikan oleh asisten rumah tangganya, Bibi Paula.
Bibi Paula membalas dengan anggukan hormat lalu kemudian segera kembali masuk ke dalam rumah.
Gadis belia yang kini sedang sibuk mengenakan sepatunya itu bernama Tiara. Tiara adalah seorang gadis berusia tiga belas tahun dan saat ini Ia sedang berada dalam masa liburan setelah selesai menuntaskan masa pendidikan dasarnya.
Tubuhnya terlihat kurus dan rapuh dengan tangan mungilnya yang kini terlihat bersusah payah mengenakan sepatunya. Penampilannya terlihat polos dan bersih, bahkan jari-jemarinya terlihat halus, seakan Ia adalah salah satu manusia yang beruntung tak pernah mencicipi sulitnya kehidupan. Rambut hitam lurusnya tergerai bebas dan sesekali menghalau pandangannya ketika angin sedikit nakal berhembus di depan wajahnya hingga Ia tak henti-hentinya menyibak rambutnya ke belakang telinganya.
Tiara menatap awan yang berarak bebas di langit, begitu indah dan menenangkan seolah hari minggu kali ini akan menjadi cerah sepanjang hari.
Ia tak sabar untuk segera beranjak dari tempat duduknya dan menikmati langkah-langkah kecil yang akan menuntunnya ke sebuah tempat yang belakangan ini menjadi tempat favorit baginya menghabiskan masa liburan, Perpustakaan Mini.
Diliriknya jam tangan berwarna hitam polos yang melingkar manis di pergelangan tangannya yang kini telah menunjukkan pukul 08.30 waktu setempat. Tiara harus segera pergi untuk memastikan ruangan perpustakaan mini yang akan dibukanya tepat dipukul 09.00 telah bersih dan nyaman untuk didatangi pengunjung.
Tiara mengambil tas selempangnya dan menyampirkan di pundaknya. Tas tersebut terlihat sangat lebar dan diisi dengan sebuah buku besar serta alat tulis yang dikemas dalam satu kotak kecil, juga seikat tumpukan kartu keanggotaan dan hal lainnya yang diperlukan untuk keperluan administrasi perpustakaan.
Baru saja Tiara akan melangkah pergi meninggalkan halaman rumahnya, seorang wanita yang terlihat lebih muda dari wanita paruh baya sebelumnya muncul di ambang pintu dengan sebuah kotak bekal di tangan kanannya dan sebuah botol minuman di tangan kirinya.
“Tiara…!” teriaknya sambil mengangkat kedua tangannya, memastikan Tiara yang sudah melangkah agak jauh dari batas halaman rumah dapat melihat apa yang ada dalam genggamannya.
“Ah… Lupa!” Tiara berbalik dan menepuk jidatnya sendiri ketika menyadari bahwa dirinya telah melupakan bekal untuk menemaninya menghabiskan waktu di perpustakaan.
Tiara sedikit berlari kecil menyusuri jalan setapak yang terbuat dari susunan paping block dari batas halaman hingga kembali ke teras rumahnya. Tas selempangnya ikut bergoyang bersama dengan gaun merah mudah polos yang menggantung di bawah lututnya ketika Ia tengah sibuk berlari.
“Hati-hati, Tiara…” tegur Ibunya yang kemudian menyerahkan kedua benda di tangannya untuk kemudian dimasukkan Tiara ke dalam tas selempangnya.
“Roti keju dan susu cokelat, kan?” tebak Tiara dengan senyum riang.
“Iya. Jangan lupa perpustakaan tutup jam 2 yaa….”
Tiara mengangguk tanda mengerti dan kemudian kembali melangkah kecil menyusuri sepanjang jalan di pemukiman perumahan tempat dimana Ia tinggal untuk segera mencapai perpustakaan mini yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Tiara tinggal di sebuah kawasan elit yang merupakan perumahan khusus fasilitas milik karyawan sebuah perusahaan besar milik negara.
Sebagai salah satu perusahaan yang sangat menunjang investasi negara khususnya dalam bidang sumber daya alam, sangat pantas bagi seluruh karyawan yang mengabdi di perusahaan ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terjamin serta terisolir dari hiruk pikuk kota metropolitan yang terlalu caruk maruk dengan ketimpangan sosial masyarakatnya.
Di perumahan ini, terdapat banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh karyawan beserta keluarga yang mereka miliki seperti sekolahan, perpustakaan, lapangan tenis, lapangan golf, lapangan basket, kolam renang, gedung fitness, rumah sakit, taman, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu.
Para karyawan perusahaan ini benar-benar hidup dengan layak dan tak perlu bersusah payah keluar dari zona aman mereka di kawasan elit ini jika hanya ingin menikmati gaya hidup yang berkelas.
Ayah Tiara merupakan salah satu karyawan yang telah cukup lama mengabdi di perusahaan ini, setidaknya sejak dua tahun sebelum menikah dengan Ibunya. Cukup lama untuk paling tidak sangat layak menduduki jabatan berpengaruh dalam perusahaan.
Kedudukan Ayah Tiara kali ini menjadikan sang Ibu yang secara otomatis menjadi bagian dari kesatuan unit yayasan yang notabene diurus oleh para istri karyawan mendapati amanah untuk mengurus fasilitas perpustakaan mini di pemukiman mereka yang memang selama ini berada di bawah kendali yayasan.
Mengingat Ibu Tiara yang masih harus mengurus adik Tiara yang merupakan seorang bayi laki-laki berusia dua tahun, maka Tiaralah yang menggantikan Ibunya untuk mengurus perpustakaan yang harus dibuka setiap hari minggu.
Ini bukanlah hal yang membebani Tiara dan Ibu Tiara pun tak menyangka mendapatkan kemudahan ini dalam menjalani amanah yayasan.
Tiara yang masih belia begitu bersemangat dan antusias serta sangat ahli dalam mengurus perpustakaan. Kecintaannya akan apa yang dilakukannya begitu terpancar dari binar matanya yang selalu muncul setiap akan pergi berangkat di hari minggu pagi menuju perpustakaan.
Dan seperti minggu-minggu ceria Tiara sebelumnya, kali ini Tiara melangkah dengan riang menyusuri jalan di pemukiman rumahnya. Perumahan yang begitu luas dan sejuk dengan pepohonan yang rimbun di setiap sisi jalan membuat Tiara merasa nyaman melangkahkan kakinya walaupun Ia sedang berjalan sendirian. Perpustakaan mini yang ditujunya tidak terlalu jauh dari rumahnya, hanya berada di ujung jalan yang menghabiskan waktu semenit dua menit untuk Tiara sampai disana.
Langkah kaki Tiara terhenti, Ia telah sampai di sebuah gedung kecil yang lebih mirip ruang kantor bernuansa putih hampir sama dengan desain eksterior rumah tinggalnya. Sebuah papan plang berwarna putih bertulisan deretan huruf cetak berwarna hitam tebal hingga membentuk kata PERPUSTAKAAN MINI berdiri tegak di halaman.
Tiara menghampiri pintu utama yang hanya terdiri dari satu daun pintu dengan kaca yang memenuhi hampir separuh pintu dan sisanya berbentuk ventilasi yang membantu sirkulasi udara keluar masuk ruangan. Dari balik pintu kaca tergantung papan yang bertuliskan “TUTUP”.
Buru-buru Tiara merogoh kantung gaunnya yang berada di sisi kanan dan kiri. Tiara sedikit cemas mengingat dirinya sempat memainkan kunci pintu perpustakaan ketika sedang duduk di teras rumahnya. Terlalu panik hingga Ia mulai membuang tas selempangnya ke lantai dan berjongkok untuk merogoh seluruh isi dalam tasnya. Beruntung akhirnya Ia bisa menemukan kuncinya di dalam tas selempangnya yang terselip di dalam buku besar miliknya.
“Huffh….” Tiara menghela nafas panjang dan mendekap kunci di dadanya sebagai rasa syukur karena Ia tak melupakan benda paling penting pagi ini.
Tiara segera membuka pintu perpustakaan, masih ada waktu sekitar lima belas menit sebelum waktu buka untuk Tiara melakukan persiapan dan memastikan kebersihan dan kenyamanan ruang perpustakaannya untuk para pengunjung.
Tiara membuka jendela yang hanya ada sepasang dalam ruangan 4×4 meter itu. Meskipun perpustakaan mini tersebut merupakan ruangan yang memiliki fasilitas mesin pendingin untuk menyejukkan ruangan, Tiara memilih membuka pintu dan jendela terlebih dulu untuk mengurangi aroma debu yang menguar di segala penjuru ruangan.
Lantai ruangan ditutupi oleh karpet bulu beludru tebal berwarna hijau zamrud, dan terdapat empat rak buku besar menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri ruangan, memenuhi dinding hingga tak ada celah kosong sedikitpun. Di sisi depan adalah sepasang jendela yang tadi dibuka oleh Tiara juga pintu untuk memasuki ruangan.
Di sisi dalam terdapat meja dan kursi tempat Tiara duduk dan melangsungkan kegiatan administrasi dan mengawasi kondisi perpustakaan. Disampingnya ada sebuah pintu untuk menuju ke ruangan kecil yang merupakan toilet umum.
Para pengunjung nantinya bisa duduk lesehan di bentangan karpet yang juga menyediakan empat meja kecil dan beberapa bantal empuk. Perpustakaan mini ini pada dasarnya merupakan fasilitas kegiatan membaca yang diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia dua belas tahun, biasanya hanya segilintir wanita dewasa yang merupakan para ibu dari pengunjung anak-anak yang masih harus berada di bawah pengawasan orangtua yang ikut bertandang.
Tak banyak yang perlu Tiara rapikan untuk buku-buku yang berderet rapi di rak, semua sudah di lakukannya setiap kali Ia mau menutup perpustakaan. Sehingga ketika tiba waktu buka seperti saat sekarang ini, Tiara tak perlu kerepotan dengan buku-buku yang berantakan.
Ketika dirasa semua sudah tertata rapi, Tiara menutup kembali sepasang jendela yang sudah dibukanya, merapikan tirainya, menyampirkan di sudut kedua bingkai jendela dengan lengkungan yang presisi satu sama lain sehingga terlihat indah menghias jendela. Tiara lalu menutup pintu dan membalik papan yang bertuliskan “TUTUP” menjadi “BUKA”.
Kini Ia menghempaskan tubuh mungilnya di kursi tempat dimana semestinya dia berada, meraih remote mesin pendingin ruangan, menyalakannya, lalu mulai membuka buku besarnya untuk diisi laporan kegiatan perpustakaan hari ini.
Tiara memperhatikan sekeliling ruangan perpustakaan mini yang lebih mirip seperti sebuah kamar pribadi kelas deluxe dalam sebuah hotel. Hanya saja lebih mirip seperti kamar pribadi istimewa bagi seorang pecinta buku.
Rasa bahagia begitu meliputi Tiara yang menyukai keheningan dan kerapian yang diciptakannya sendiri di perpustakaan mini ini.
Seringkali Tiara berharap tidak ada pengunjung yang tertarik untuk datang, entah karena malas, acara keluarga, atau apapun yang menghambat rencana akhir pekan mereka untuk berkunjung ke perpustakaan mini ini hingga Tiara dapat menikmati sendiri semua kenyamanan di dalamnya.
Ya, sesekali Tiara juga berpikir seegois itu, ingin perpustakaan itu untuk dirinya sendiri.
****
Bersambung~

Pinkie Promise: Prolog
10 Oktober 2023 in Vitamins Blog
****
“Pergilah Tiara….”
Tiara tercenung, hanya bisa diam mematung masih tak berhenti menatap sepasang mata amber yang kini menatapnya dengan kilatan tak bersahabat dan suara yang tengah mengusirnya untuk pergi itu terdengar begitu lirih dan menyeramkan.
Pria dihadapannya itu tak mau mengulang kata-katanya untuk kedua kalinya, mendekatinya dengan bahasa tubuh yang diliputi kegeraman hingga membuat Tiara sedikit melangkah mundur dari tempatnya berdiri lantaran merasa ketakutan hingga tubuhnya terjebak oleh batang pohon besar yang berada di belakangnya.
Tubuh tegap dan kokoh itu kini hanya berjarak beberapa senti dari tubuh mungil Tiara. Melingkupinya, hingga Tiara harus sedikit mengangkat dagunya agar tetap dapat menatap lekat sepasang iris amber yang terlihat didera kecemasan.
Tiara merasakan telapak tangannya digenggam dengan cepat dan sangat erat yang meninggalkan sebongkah batu kecil berkilauan berwarna merah darah di telapak tangan mungilnya.
“Itu adalah Ratnaraj, satu-satunya yang tersisa. Bawalah bersamamu, hanya Kau yang bisa menjaganya, Tiara.”
Ketika sosok dingin itu mulai beranjak pergi meninggalkannya, Tiara segera menyusulnya dengan langkah tertatih-tatih lalu menggenggam tangan kekar di hadapannya erat-erat lantas membuat jari kelingking tangan kanan mereka saling bertautan.
Bola mata amber itu kembali menatapnya, kali ini dengan diliputi oleh tanda tanya besar atas tindakan Tiara. Namun sebelum sebuah pertanyaan lolos dari kerongkongannya, Tiara segera angkat bicara.
“Ini disebut sebagai Pinkie Promise. Aku sedang berjanji padamu,” ucapnya cepat begitu meyakinkan dari sorot matanya yang berpendar indah dan menatap dalam-dalam pada sosok di depannya.
“Aku berjanji bahwa aku akan kembali dan menjaga Ratnaraj untukmu.”
****

Yvonne’s Romance – #4 Percakapan
28 April 2023 in Vitamins Blog
****
Samar-samar suara gemerisik angin yang menerbangkan dedaunan kering menelusup dan mengantarkan gelombang suara yang menggetarkan kedua membran timpani di dalam sepasang telinga milik Yvonne.
Terasa sedikit berisik namun tak mengusik dan sedikitpun tak melunturkan semangat Yvonne untuk tetap memfokuskan kedua bola matanya membaca setiap deretan kata-kata yang membentuk kalimat-kalimat indah dari novel berbentuk buku tebal yang tengah ia baca dan terpaksa ia cintai dari hari ke hari tanpa henti.
Terpaksa mencintai, awalnya tidak mudah namun lambat laun, kebiasaan yang terpaksa itu membuat Yvonne terbiasa dan menemukan keindahan-keindahan tersembunyi di dalamnya ketika ia mulai belajar mencintai secara tertatih-tatih.
“Jika kau tak belajar mencintai sesuatu yang dengan terpaksa harus kau hadapi tanpa bisa berlari sedikitpun, lambat laun hanya kehampaan yang membutakanmu, lantas tak sedikitpun keindahan yang mampu kau rasakan, sedangkan di dunia ini, bahkan malam yang gelap gulita hingga begitu pekat yang terasa meremangkan bulu kudukmu, nyatanya mampu menjadi situasi yang membuatmu melihat jutaan bintang-bintang yang berpendar indah di langit, jika kau menyadarinya.”
Hari itu, di suatu suasana menjelang siang yang hampir sama seperti saat sekarang, entah sudah beberapa hari yang lalu hal itu terjadi, namun Yvonne sangat ingat bagaimana ia tengah terperanjat hingga kedua bola matanya mematung sempurna dan menatap dalam tanpa berkedip sedikitpun kepada sosok pria yang tengah duduk di depan matanya dengak kekaguman yang menyerang benaknya secara bar bar.
Pupil matanya terasa mengecil bagai lensa kamera yang sedang menjalankan mode mikro karena begitu fokus menatap sosok Nathan yang baru saja selesai melontarkan kata-katanya. Betapa fokusnya menatap Nathan sampai Yvonne bisa melihat garis senyum hangat milik Nathan sedang mengembang perlahan dengan kaku sebagai sebentuk cara yang bisa dipikirkan Nathan secara cepat untuk mencairkan suasana yang membingungkan dalam sepersekian detik ke menit yang begitu canggung di antara mereka berdua.
“Ah, itu bukan kata-kata yang kubuat sendiri, tapi dari novel itu, sekitar beberapa halaman lagi di belakang.”
Nathan mulai terkekeh dan dengan malu-malu mengucapkan kalimatnya secara perlahan yang menurutnya pantas untuk mencairkan suasana sembari menggaruk pelipisnya yang tidak gatal sedikitpun, melainkan hanya sebuah bentuk pengendalian diri saja.
Yvone mengerjapkan matanya dengan cepat, kesadaran segera meremanginya lantas wajahnya memerah menahan malu atas tindakan impulsif yang tercipta tanpa izin.
“Oh, begitu kah? Bagus sekali.” celetuk Yvone dengan cepat dan mengakhiri kalimatnya dengan tawa kecil yang begitu canggung.
Entah bagaimana situasi hari itu yang terasa canggung bisa kemudian berakhir dengan situasi yang kembali menyenangkan, namun Yvonne sangat tahu dan tak akan lupa bahwa Nathan selalu menempatkan dirinya menjadi nahkoda yang menyeimbangkan kapal yang terombang-ambing oleh gelombang rasa canggung yang menggelayuti perasaan dengan membabi buta saat mereka sedang duduk berdua.
Setiap kali gelombang pasang mulai bermain-main, dengan tenang Nathan mengatur kendali hingga Yvonne kembali fokus dengan tujuan.
Kenyataan yang terlampau banyak terjadi membawa Yvonne nyaris menghabiskan berlembar-lembar halaman novel yang menjadi tanggungjawabnya untuk saat ini kepada Lucas dan saat ini Yvonne termangu sendiri mendapati dirinya menemukan deretan kata-kata indah yang pernah diucapkan Nathan.
Nathan ternyata tidak berbohong.
Bagaimana bisa pria itu menyatakan dengan sempurna kalimat yang terpatri indah dalam selembar novel itu?
Seakan-akan ia mengucapkan dari hatinya?
Yvonne meletakkan novel dalam genggamannya ke atas meja kafe dan mengusap wajahnya beberapa kali dengan kedua telapak tangan mungilnya tanpa menghiraukam sedikitpun bahwa yang ia lakukan bisa memudarkan lapisan bedak tipis yang membantu mencerahkan wajahnya. Pada akhirnya ia mendaratkan kedua telapak tangannya di dasar rahangnya sehingga ia mulai terlihat tengah menopang dagu dan mengarahkan wajahnya ke luar jendela kafe.
Kedua matanya kini mulai meredup sembari mengamati dengan tenang suasana di luar kafe. Meski ia sedang berada di dalam ruangan yang suhunya dimanipulasi oleh pendingin ruangan yang bertengger di setiap sisi dinding kafe, ia bisa merasakan suasana di luar sana begitu hangat oleh cahaya matahari yang berpendar redup, tak terasa terik menyengat, dan berkolaborasi dengan semilir angin yang meniup daun-daun kering hingga berterbangan tak tentu arah dan dengan pasrah berlabuh di manapun angin dengan jahil membawa mereka.
Rasa bosan mulai menyelimuti Yvonne, ia telah selesai menunaikan tugasnya membaca lembaran novel yang menjadi tugasnya hari ini, namun ia terasa terlalu lama menanti kehadiran Nathan dan itu benar-benar tak seperti biasanya. Padahal Yvonne bermaksud menyampaikan sesuatu yang sangat tak sabar untuk ia ungkapkan kepada Nathan. Pagi tadi Yvonne terkejut oleh informasi yang disampaikan oleh Lucas kepadanya dan itu membuatnya begitu ingin segera bertemu Nathan juga menjadi alasan hari ini Yvonne menghabiskan lebih banyak lembaran halaman novel untum dibaca.
Tapi, di mana Nathan?
Yvonne terlalu lama menunggu, ia tahu dari posisi matahari yang nyaris sepenggalah naik hingga mencapai ubun-ubun, biasanya Nathan tak membuatnya lama menunggu seperti saat ini. Mereka biasa menyelesaikan diskusi mereka sebelum jam makan siang. Tapi saat ini bahkan Yvonne bisa merasakan lambungnya mulai meronta-ronta oleh gerak peristaltik yang mulai mencari korban untuk digerus dan Yvonne khawatir enzim dalam lambungnya mulai salah sasaran.
“Astaga, aku mulai lapar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat ini?” gumamnya dengan perasaan sedih.
Yvonne tidak tahu apa sebaiknya ia segera pulang saja atau tetap menunggu Nathan?
Apakah sebaiknya Yvonne memesan makanan atau memilih pulang untuk menikmati sajian dari jasa katering yang selalu disiapkan Lucas untuknya?
Yvonne tidak biasanya memesan makanan siang di kafe Nathan karena ia selalu mengingat sajian makanan yang pasti sudah tersedia di apartemen yang ditinggalinya dengan Lucas. Yvonne biasanya hanya memesan kopi atau makanan ringan seperti kue red velvet yang menjadi favoritnya untuk menemaninya membaca novel.
“Ya ampun, kenapa otakku terasa buntu? Aku bahkan tidak bisa memutuskan sesuatu untukku sendiri saat ini?”
Yvonne merasa bodoh, begitu miris dengan situasinya saat ini dan itu membuatnya terdiam beberapa saat dan meletakkan kepalanya di meja kafe dengan begitu menyedihkan.
“Ya ampun, Yvonne!” rutuknya dalam hati.
Yvonne teringat kartu nama yang pernah diberikan Nathan saat pertama kali mereka bertemu. Sedikit banyak Yvonne ingin sekali menghubungi Nathan melalui deretan nomor telepon yang tertera rapi di lembar kartu nama mungil yang masih tersimpan awet di dalam tas mungilnya namun Yvonne terlalu sungkan untuk melakukannya.
Interaksi mereka selama ini hanya sebatas bertemu di kafe tersebut, meski Nathan sudah pernah memberi kartu namanya, bukankah itu sebuah formalitas bentuk kesopansantunan dalam sebuah bentuk perkenalan resmi saja?
Tidakkah terlalu melampaui batas rasanya jika Yvonne menghubunginya saat ini hanya untum sekadar bertanya apa Nathan tidak berniat untuk menemuinya hari ini?
Setelah sekian banyak hari yang dilalui, bukan, lebih tepatnya setiap hari yang telah mereka lalui bersama, rasanya tetap saja seperti tidak tahu diri jika Yvonne mengusik rutinitas Nathan lebih jauh, ia sudah cukup bersyukur Nathan selalu ada membantunya dan menghiburnya ketika penat membaca novel.
Ya, rasanya begitu.
“Permisi…”
Yvonne terperanjat ketika suara yang terasa asing menyapanya. Seorang pramugara kafe datang menghampirinya dengan membawa sepiring spaghetti carbonara hangat yang wanginya begitu semerbak hingga semakin membangunkan rasa lapar yang berusaha ditahan Yvonne sedari tadi.
Tersadar akan sesuatu yang janggal, Yvonne segera menolak dengan cepat sajian nikmat yang disodorkan kepadanya sebab ia sangat yakin meski sedari tadi tengah melamun kikuk, itu tak membuatnya sudah gila untuk bertindak di bawah alam sadarnya memesan makanan tiba-tiba karena terganggu oleh rasa lapar.
“Maaf, kurasa kau salah menyajikan ini kepadaku. Aku tidak memesan makanan apapun.” tolak Yvonne dan sedikit melirik ke arah secangkir cappuccino-nya yang nyaris tandas dari cangkirnya lalu kemudian ia beralih melirik sepotong kue red velvet yang dipesannya sejak awal datang sudah tak lagi nampak wujudnya di atas piring kue miliknya kecuali sisa krimnya saja yang seperti melukis permukaan piring kue secara berantakan.
“Apa ini sebuah teguran karena aku tak juga pergi dari sini setelah semua menu yang kupesan sudah habis?” ucap Yvonne dalam hatinya yang begitu bertanya-tanya.
“Oh, ini diberikan secara gratis atas perintah Tuan Nathan,” ucap pramugara tersebut dengan singkat namun nada yang digunakan terasa santun.
“Tuan Nathan juga berpesan untuk menyampaikan permintaan maafnya karena tak bisa menemui Nona Yvonne hari ini sebab ada kegiatan yang harus dilakukannya sejak sedari pagi di luar kafe. Semoga sajian ini bisa menghibur Nona Yvonne yang tengah sendirian, selamat menikmati, saya permisi.” terangnya lagi lantas segera meninggalkan Yvonne yang masih diam membisu.
“Bagaimana jika aku yang tidak hadir hari ini?” gumam Yvonne sembari masih dalam kependiaman yang kokoh.
“Bagaimana jika sebelum sajian ini datang, aku sudah angkat kaki dari sini?”
“Bagaimana bisa Nathan seperti cenayang yang begitu percaya diri mampu membaca tindakan yang akan kulakukan, seakan ia tahu aku tetap menunggunya di sini?”
“Sialan! Aku seperti terlalu mudah ditebak!” hardiknya begitu memekik dalam hati dan menutup rasa haru yang baru saja merasukinya karena selalu merasa bingung oleh sikap baik Nathan.
Perasaan yang begitu campuraduk mulai menggelayuti benaknya, tapi yang pasti Yvonne mau tak mau harus tinggal lebih lama lagi untuk menikmati sajian yang sudah dihidangkan di depannya. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya, betapa ia merasa beruntung bertemu Nathan dan ia tahu ia harus merasa cukup sampai disitu saja, Yvonne sungguh tak berani berharap lebih dengan pertemanan mereka yang terjalin setiap harinya.
Bukankah pria tidaklah serumit wanita?
Ketika pria merasakan sesuatu pada hatinya maka ia menyatakan dengan pasti.
Ketika sesuatu itu terasa rumit pada diri seorang pria, maka cukuplah berpikir ia hanya pria yang sedang melakukan perannya, yakni berbuat baik, tidak lebih.
Yvonne memahami itu dengan baik dari hari ke hari, rasa nyaman dan kagum akan nahkoda yang tengah menaklukkan lautan hatinya tak seharusnya ingin dimiliki oleh penumpang gelap sepertinya, meski hal itu terkadang mengusik egonya.
“Sialan!” hardiknya lagi masih berisik di dalam benaknya sendiri.
“Bisa-bisanya aku kagum dan benci padamu, Nathan!” pekiknya lagi namun Yvonne segera larut menikmati makanan yang sudah cukup kurang ajar menggodanya.
Yvonne begitu menikmati makanannya hingga ia tak sadar dua orang wanita berpenampilan modis masuk ke dalam kafe dan mengambil posisi duduk tepat di sebelah meja miliknya.
Tentu saja Yvonne tidak peduli, tampilan mereka berdua yang terlihat mewah bukanlah indikator yang bisa membuat Yvonne menoleh ke arah mereka.
Tapi, ketika ia mendengar nama Nathan terucap dari bibir merah merona salah satu dari mereka, Yvonne melambatkan gerakan makannya, membiarkan seluruh fokusnya tertuju pada indera pendengarannya untuk terus mendengar percakapan di antara keduanya.
“Apa kau tahu kalau kafe ini milik Nathan?”
“Yaa, aku tahu karena itulah aku mengajakmu kemari, kau suka kan?”
“Yaa, aku suka. Tapi bukankah terasa canggung jika kita berada di sini? Kau sungguh tidak tahu malu untuk bertemu muka dengan Nathan.”
“Kenapa aku harus malu? Justru dia harus melihat perempuan cantik yang telah ditolaknya dulu ini sekarang semakin mempesona. Dia pasti menyesal.”
“HAHAHA, kau pikir begitu? Kau lupa dia itu patung es, sangat dingin. Bisa-bisanya kau tertarik padanya dan berusaha menarik perhatiannya bahkan dulu di saat perempuan yang dicintainya masih hidup.”
“Hidup seperti apa jika tidak berdaya? Lagipula sekarang perempuan yang ia cintai setengah mati itu sudah meninggal.”
“Hei, hormatilah mendiang.”
“Memangnya aku bicara apa? Itu kan fakta. Lagipula kau jangan khawatir, aku bukannya ingin mencari perhatian Nathan lagi, aku hanya mau melihat keadaannya sekarang saja, kudengar setelah kejadian itu dia hanya menyibukkan dirinya di dalam kafe ini.”
“Tapi, aku tidak melihat Nathan sedikitpun, bagaimana kalau kita memesan makanan sekaligus bertanya kepada pramugara?”
“Bagus juga, sia-sia riasan cantikku hari ini kalau Nathan tidak melihatku dengan pandangan penuh penyesalan, dasar patung es!”
Kedua perempuan itu mulai memanggil pramugara dengan lambaian tangan yang gemulai namun Yvonne sudah bisa menebak kekecewaan yang akan terpatri di wajah mereka karena Yvonne sudah tahu lebih dulu bahwa Nathan takkan hadir hari ini.
“Rasakan!” hardik Yvonne dalam hatinya.
Yvonne segera menghabisi makan siangnya dengan cepat, ia tak lagi ingin berlama-lama di kafe tersebut, lebih tepatnya ia merasa muak mendadak berada satu ruangan dengan kedua perempuan yang baru saja bercakap-cakap dengan sinis itu.
Selain itu, Yvonne merasa terganggu dengan beberapa kalimat yang telah sampai di telinganya.
“Nathan memiliki perempuan yang dicintai?”
“Pertanyaan macam apa ini? Hei, Yvonne, tentu saja itu wajar untuk seorang Nathan.”
“Tapi, meninggal? Siapa? Kekasihnya? Kejadian apa?”
Yvonne sedikit linglung dalam perjalanan pulangnya ke apartemen dan untungnya di siang hari apartemen kosong hingga membuat Yvonne bisa lebih terlena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam ingatannya.
Yvonne merebahkan tubuhnya dengan begitu pasrah di atas kasur empuk di dalam kamarnya. Ia tak suka dengan percakapan yang telah ia dengar, itu membuatnya berpikir berat hingga ia tak bisa menemukan solusi apapun untuk memuaskan hasrat keingintahuannya.
Mana mungkin ia bertanya kepada Nathan hal yang begitu sensitif semacam itu?
Kenapa aku harus mendengarnya? Aku tak ingin ikut campur!
Yvonne benar-benar lelah, ia terlalu letih setelah sibuk membaca beberapa lembar novel dan berusaha keras menenangkan jiwanya saat menanti tanpa kepastian akan kehadiran Nathan, kemudian ia terpaksa mendengarkan percakapan rumit yang kini mengganggu pikirannya.
Yvonne memilih memejamkan matanya rapat-rapat, menyerahkan sepenuhnya jiwanya untuk terlelap agar energi jiwa dan raganya bisa kembali membaik setelah istirahat yang cukup.
Ia tidak lupa bahwa ketika malam menjelang ia masih harus menunaikan kewajibannya menyampaikan ringkasan-ringkasan cerita dari beberapa lembar halaman novel yang telah selesai dibacanya hari ini.
“Sebaiknya aku tidur, aku harus istirahat.”
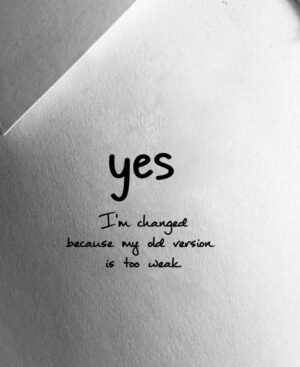
PROSA HATI – #3 Rahasia Hati
30 September 2022 in Vitamins Blog
Mengapa kau menelisik jauh ke dalam relung hatiku?
Mengapa kau mencari-cari retakan berserak yang kusimpan jauh dalam palung sukmaku?
Dan mengapa aku bertanya?
Sedang cinta yang kau miliki untukku adalah yang terbaik dari semua cinta manusia yang pernah tercipta dalam garis takdirku?
Kau mencinta dengan segenap jiwa dan ragamu,
Kau menyayangi ketidakberdayaan yang kumiliki tanpa ragu,
Kau dipenuhi dengan harapan-harapan bahagia yang kau hujani bertubi-tubi padaku dan terpancar nyata di bola-bola matamu yang luruh,
Aku si pendosa,
Yang merangkai dusta dalam bentangan garis-garis senyum kepalsuan serta menyenandungkan tawa riuh rendah yang kubenci semata-mata sebagai penghiburan sia-sia.
Dan kau tak butuh itu.
Kau menggapai jauh ke dalam diriku bagai cahaya terik yang jatuh tepat ke dalam retina mataku dengan pelik.
Aku memeluk diriku yang berserabut oleh penyangkalan-penyangkalan mengenai betapa rapuhnya diriku.
Aku ingin kuat,
Aku ingin kuat,
Aku ingin kuat.
Lantas kau berucap kata-kata mantra penenang yang bermuara dari kesunyian yang kubangun dengan kokoh dan bisu.
Aku malu,
Kepada manusia-manusia lain aliran saliva-ku nyaris mengering hingga mengerak perih hanya ‘tuk meratap kosong.
Setiap kali aku membenci diriku yang lemah, aku tak jemu mengadu pilu pada manusia-manusia lain yang kupikir akan menjadi penolong jiwaku yang letih.
Tapi kau bahkan mampu mengira dengan pasti setiap asa yang mengaduk-aduk relung jiwaku.
Kau tahu,
Kau selalu tahu,
Bahkan sebelum aku memberi tahu.
Kau melihat lelah dari senyum yang terpatri di wajahku,
Kau mendengar pilu dari tatapan mataku yang nanar,
Kau merasakan kekosongan dari jiwaku yang hampa,
Pada hati yang sudah mati ini, kau bisikkan harapan indah yang aku sendiri tak merasa ingin memilikinya.
Kau bilang hatiku tak pantas tercabik oleh belati yang merajam waktu yang telah berlari menjauh di belakangku.
Kau bilang hatiku selalu hidup setali tiga uang dengan udara yang kuhela sepanjang waktu.
Dan aku terisak dalam diam yang rumit.
Maafkan aku.
Maafkan aku.
Maafkan aku.
Aku si pendosa yang merangkai dusta sebagai penghiburan kosong pada indahnya harapan tulusmu.
Tentang rahasia hati yang kupaksa mati untuk selamanya.
Mati, selamanya.
***
Ditulis di penghujung September,
Dimabukkan oleh deras hujan yang dingin menusuk,
Ditemani sendu yang terlanjur menjadi candu yang kubenci dengan payah.

Yvonne’s Romance – #3 Pengalihan
29 Agustus 2022 in Vitamins Blog
“Hai, apa kegiatan membacamu lancar hari ini?”
Yvonne tersentak dari lamunannya ketika mendapati Nathan sudah berdiri di sampingnya. Senyum ramah milik Nathan menjadi pemandangan yang menyenangkan untuk Yvonne ketika ia menatap lekat pada wajah Nathan yang kemudian segera duduk di hadapan Yvonne.
Sedari tadi Yvonne memang menunggu Nathan menghampirinya, namun karena Nathan tak kunjung datang maka Yvonne memilih untuk melamun agar dapat membunuh waktu yang membosankan sebab ia sudah selesai membaca satu bab dari novel dalam genggamannya. Dan tidak seperti sebelumnya, kali ini Yvonne memang harus sedikit lebih berusaha untuk fokus membaca sehingga ia menjadi lebih lelah daripada sebelumnya dan rasanya seperti ia sedang berada di bawah tekanan. Ia kesulitan untuk fokus karena di dalam kepalanya terus menanti Nathan hadir lagi seperti kemarin, pertama kali mereka bertegur sapa. Tak jarang selama membaca Yvonne menebak-nebak alasannya sendiri karena begitu menanti kehadiran Nathan.
“Karena novel. Yaa, karena aku butuh teman untuk berdiskusi, itu saja.” ucap Yvonne pada dirinya sendiri setiap kali rasa penantian mulai mengganggunya.
“Yvonne, apa kegiatan membacamu lancar hari ini?” Nathan mengulang lagi pertanyaannya sebab ia tak mendapati Yvonne menjawab meski Nathan sudah memberi jeda waktu untuk mendengarkan jawaban dari Yvonne sehingga ia berasumsi Yvonne tadinya tidak dengar apa yang ia katakan dan ia perlu mengulangnya lagi.
Yvonne sedikit gelagapan setelah menyadari bahwa Nathan mengulang lagi pertanyaannya. Bukanlah itu artinya Nathan sungguh-sungguh menanti jawaban darinya? Sungguh tak elok rasanya kalau Yvonne tak segera memberi tanggapan atas pertanyaan tersebut.
“Oh, iya, lumayan, ada beberapa hal yang kurasa perlu kutanyakan, itu pun kalau kau bisa membantuku,” ucap Yvonne dengan cepat dan sedikit canggung lantaran ia sendiri menyadari bahwa jawabannya terlalu dibuat-buat, terlalu beralasan untuk menahan Nathan bersamanya dan ia khawatir Nathan menyadari hal itu.
Berada di tempat baru yang asing sendirian tentu rasanya sebuah kesempatan yang berharga mendapati seseorang untuk diajak bicara dengan nyaman, terlebih lagi Nathan tampak seperti manusia yang aman untuk diajak berinteraksi, setidaknya sejauh ini Yvonne merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan dari kehadiran Nathan.
Manusia makhluk sosial, bukan?
Cepat atau lambat Yvonne akan membutuhkan teman, itu saja alasan Yvonne bersyukur bertemu dengan Nathan.
Karena pada akhirnya ada seorang teman untuk diajak bercerita terlepas Nathan adalah pria yang memberi kesan menarik sejak pertama bertemu. Kesan yang menarik itu anggap saja bonus dari sebuah bentuk pertemanan baru.
“Aku tidak yakin apa aku bisa begitu membantumu, tapi akan kucoba sebaik mungkin. Boleh aku membacanya sekilas? Aku khawatir sedikit banyak terlupa dengan alurnya. Terakhir aku membacanya sepertinya beberapa tahun yang lalu.”
Yvonne menyerahkan novel miliknya, membiarkan Nathan meraihnya dan mulai membuka lembaran yang sudah ditandai oleh Yvonne. Nathan merogoh saku di bajunya, tepatnya di bagian dada sebelah kiri. Ia mengambil sebuah kaca mata baca dan mengenakannya, sedang Yvonne sedikit menahan rasa terkejut yang terpatri jelas di raut wajahnya hingga Nathan segera menyadarinya.
“Ada apa?” tanya Nathan sembari menelisik wajah Yvonne dengan khawatir.
“Ah, tidak ada apa-apa. Hanya kaget saja, ternyata kau berkaca mata, haha.” Yvonne mengakhiri kalimatnya dengan tawa yang sangat canggung bahkan ia sendiri merasa tidak enak dengan reaksinya yang mungkin akan disalahpahami oleh Nathan sebagai sikap yang tak sopan atau barangkali terkesan mengejek.
“Oh, kadang-kadang aku perlu memakainya untuk membaca tulisan-tulisan kecil seperti yang ada di novel ini. Kenapa? Wajahku jadi terlihat berbeda yaa? Mungkin karena frame-nya terlalu tebal dengan garis tegas atau lensanya berpengaruh dan memberi kesan berbeda pada mataku, kurang lebih semacam itu. Lagipula kau pertama kali melihatku tanpa kaca mata sebelumnya, jadi wajar saja yaa agak terkejut, aku bisa memaklumi itu.”
Tidak ada kalimat lainnya yang ingin didengar oleh Yvonne, bahkan ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Nathan serta bagi Yvonne saat ini hanya ada keinginan untuk menjerit dalam hatinya,
“Cukup! Jangan jelaskan apapun, hentikan topik tentang kaca mata ini! Jangan lanjutkan atau aku akan berlebihan memperhatikan wajahmu!”
Yvonne memutar otaknya untuk membuat pengalihan topik yang sempurna dan ia segera menemukan bahan ketika menatap secangkir cappuccino di depan matanya,
“Ah, kopi! Iya, kopi!” pekiknya dalam hati dengan girang karena menemukan sebuah solusi untuk menghindari ketidaknyamanan yang tercipta dalam dirinya.
“Cappuccino ini sungguh enak, kau tidak mau memesan satu untukmu?” sela Yvonne secepat kilat dan berhasil membuat topik baru sebagai pengalihan.
“Aku tidak minum kopi,” jawab Nathan singkat namun cukup membuat Yvonne terperanjat dan sepasang matanya yang sedari tadi dialihkannya dari wajah Nathan terpaksa menatap lekat kembali untuk mencari jawaban yang ia butuhkan di wajah pria itu.
“Kau bodoh yaa Yvonne? Mana mungkin kau berpikir akan muncul jawaban di wajahnya itu ‘kan? Kau sengaja melihat ke sana, kan? Cepat buang pandanganmu! Kau itu lemah dengan pemandangan semacam itu!” hardik Yvonne pada dirinya sendiri yang tentu saja hanya bergaung di dalam hatinya dan tak terungkap sedikitpun.
Yvonne segera membuang tatapannya ke arah meja bar kafe, membiarkan sepasang mata hazel-nya kini termanjakan oleh barisan mesin-mesin kopi yang terlihat indah untuk dipandangi. Tentu saja rasa terkejut atas jawaban Nathan masih mengganjal di hatinya, sebab Yvonne merasa heran bagaimana bisa seorang pemilik kafe yang didominasi oleh menu varian kopi mengatakan dirinya tak minum kopi? Rasa penasaran yang menguasai Yvonne akhirnya membuatnya angkat bicara kembali.
“Kau bercanda yaa? Kau benar-benar tidak minum kopi?” tanya Yvonne lagi sembari menopang dagu dan tetap membiarkan wajahnya menatap seluruh hiruk pikuk di balik meja bar kafe.
“Aku tidak bercanda. Aku sungguh-sungguh, nona Yvonne. Tubuhku tidak kompromi dengan kopi, aku lebih nyaman minum secangkir teh oolong dan sebenarnya aku sudah memesannya sebelum menghampirimu tadi. Pramusaji akan mengantarkannya nanti, aku memang bilang agar prioritaskan saja pesanan para pengunjung. Penikmat kopi saat ini sangat menjamur dan meminum kopi sudah menjadi gaya hidup yang sedang naik daun, jadi aku hanya mengikuti selera pasar saja. Dunia bisnis harus tahu memanfaatkan kesempatan demi keuntungan yang maksimal,” terang Nathan dengan ramah lalu mulai memasang wajah serius untuk mulai membaca novel.
“B-be-gitu yaa?” Yvonne menyeruput cappuccino miliknya dengan lambat-lambat seolah ia sedang sangat menikmati sesapannya padahal ia hanya berusaha mencari kesibukannya sendiri sembari membiarkan Nathan membaca novel dengan fokus, sedang pikirannya sendiri mulai melayang dan berkabut, menari-nari di dalam ruang pikirannya.
Pria itu baru dua hari ditemuinya tapi cukup banyak memberi kesan mengejutkan dan membuat Yvonne merasa lucu atas dirinya sendiri. Yvonne tak biasanya menerima dengan tangan terbuka saat pria-pria mencoba menghampirinya, bahkan jika itu hanyalah salam sapa penuh formalitas yang sepintas lalu. Meski ia sendiri tak punya alasan jelas bisa menyambut baik kedatangan Nathan, namun ia cukup yakin ia tidak salah membuat keputusan untuk berteman dengan Nathan.
Yvonne saat ini benar-benar tak berani melihat ke arah Nathan. Saat ini dihadapannya sedang ada seorang pria menggunakan T-shirt warna abu-abu polos berkerah lantas sedang fokus membaca sebuah buku lengkap dengan kaca mata bertengger di batang hidungnya. Cukup, Yvonne tidak boleh terlalu memandang ke arah Nathan, karena ia tahu akan ada degup tidak wajar di jantungnya yang tercipta oleh rasa terpesona. Itu bukan sebuah rasa yang terbawa oleh perasaan, namun hanya sesuatu yang disukai oleh Yvonne dan ia lebih suka tidak menunjukkannya agar tak ada salah paham yang disimpulkan dari sikapnya yang ambigu.
Tak berapa lama kemudian seorang pramusaji datang membawa secangkir teh hitam panas untuk Nathan. Setelah menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasihnya, Nathan kembali tenggelam membaca novel. Dan saat itu pula, Yvonne sempat berpikir bahwa ia sedang disajikan pemandangan indahnya rutinitas pria berkelas. Yvonne bahkan seakan terdistraksi sepersekian detik dengan imajinasinya di mana Nathan menyesap secangkir teh miliknya dengan elegan lantas berkata dengan aksen british sembari membenarkan sedikit letak gagang kacamatanya,
“I don’t drink coffee, I prefer a cup of tea, darling.”
“Astaga, apa aku pergi saja dari sini? Memalukan!” rutuk Yvonne dalam hatinya dan merasa sangat malu akan pikirannya sendiri yang tak tahu diri berputar-putar di ruang imajinasinya sekarang.
Yvonne benar-benar berusaha mengosongkan pikirannya dan mengalihkan segalanya dengan fokus mencecap berbagai kolaborasi rasa dalam secangkir cappuccino miliknya meski tanpa harus ditelisik lebih jauh, sebenarnya sudah jelas semua rasa yang tercipta berasal dari keseimbangan antara espresso, steamed milk, dan foam yang menjadi takaran paten untuk secangkir cappuccino.
Nathan tiba-tiba menutup buku novel yang ia baca dan meletakkan perlahan di atas meja, sangat hati-hati seakan ia takut buku itu memecahkan kaca meja kafe. Sebelum ia berbicara, ia menyesap beberapa kali pada secangkir teh miliknya lantas melepaskan kembali kacamata yang sedari tadi dipakainya untuk dimasukkan ke dalam saku bajunya lagi.
“Apa kau kesulitan lagi membayangkan beberapa latar tempat atau karakter yang dipaparkan oleh penulis? Apa kau mau aku menggambarkannya untukmu?” tanya Nathan sungguh-sungguh.
“Emm, tidak juga. Aku hanya ingin berdiskusi saja. Apa kau bisa mendengarkanku mencoba menceritakan kembali? Jika ada yang salah, kau bisa koreksi.” pinta Yvonne.
“Tentu saja, aku dengan senang hati akan mendengarkanmu. Kupikir kau akan memintaku menggambar beberapa hal sehingga aku sudah terlalu percaya diri membawa kertas dan alat tulis sejak awal menghampirimu,” ucap Nathan lagi sembari terkekeh.
“Kau sangat suka menggambar yaa? Kau sepertinya lebih tertarik menggambarkan sesuatu untukku daripada kuajak berdiskusi? Aku jadi iri padamu. Aku tidak pandai menggambar, tapi ada kalanya aku juga ingin bisa menggambar. Terutama ketika aku membaca komik, kadang itu memancingku berandai-andai menjadi ahli menggambar, paling tidak untuk satu gambar saja yang ingin kubuat seindah mungkin, sesuai seleraku, sesuai imajinasiku,” celetuk Yvonne sembari wajahnya menatap pada langit-langit kafe dan sama seperti sebelum-sebelumnya, matanya selalu dengan senang hati tertambat pada setiap tulisan-tulisan penuh makna yang terbingkai indah di setiap sisi dinding-dinding kafe.
“Memangnya apa yang ingin kau gambar?” tanya Nathan.
“Ah, bukan apa-apa, aku hanya ingin menggambar karakter keren dari pria ber- ….” Yvonne segera bungkam, hampir saja ia keceplosan.
“Eh?! Astaga! Nyaris saja!” pekik Yvonne dalam hatinya dan tubuhnya mulai membeku dingin.
“Pria bertubuh atletis! Iya, seperti itu!” sergap Yvonne segera melanjutkan kalimatnya yang sempat terjeda tanpa pikir panjang.
Memalukan!
Bahkan mengalihkan ke kalimat lain hanya membuatnya semakin merasa tampak buruk di depan Nathan. Rasanya seperti perempuan yang tak tahu malu mengatakan hal semacam itu!
Terpesona oleh tubuh?
Sungguh menggelikan dan sama sekali bukan selera Yvonne.
Nathan terkekeh mendengar penjelasan Yvonne dan ia juga bukan pria kemarin sore yang sedari tadi tak menyadari sikap Yvonne yang canggung dan salah tingkah. Nathan bukan pria yang tidak peka dengan perilaku Yvonne yang mudah sekali terbaca hanya dari raut wajahnya saja.
Terlalu mudah.
Meski sebenarnya Nathan ingin sekali mengerjai Yvonne seperti membalik kata-kata Yvonne mengenai tubuh pria atletis namun Nathan memilih mengurungkan niatnya. Walaupun rasanya sayang sekali mengingat itu bahan yang tepat untuk membalik kata mesum yang kemarin dilontarkan Yvonne mengenai opininya terhadap penulis novel yang mungkin akan membuat gambaran wanita seksi dari imajinasi yang mesum hingga berpuluh lembar, tapi Nathan tetap memilih membiarkan saja.
Nathan sudah cukup melihat Yvonne sangat kikuk dan ia tak ingin membuat Yvonne tidak nyaman sama sekali bersamanya.
Entah mungkin perasaan Nathan saja, namun ia menangkap situasi di mana sebenarnya Yvonne bukan perempuan yang suka didekati pria asing dan mungkin dirinya juga kebetulan saja beruntung di mana kehadirannya disambut hangat oleh Yvonne walau awalnya juga jelas sekali Yvonne terlihat membuat sikap waspada yang terlalu berlebihan.
Dan begitulah Nathan terus berhati-hati, sebab ia ingin membantu Yvonne hingga perempuan itu menyelesaikan novel yang ia baca. Tidak ada kepentingan lainnya, ia hanya tergerak karena novel itu, tidak lebih.
Lagipula jika memang Yvonne adalah seorang perempuan yang tak mudah menyambut pertemanan pria, maka Nathan tak lebih baik dari Yvonne. Butuh pemicu yang berbeda dari biasanya untuk membuat Nathan tertarik mendekat, sebab Nathan sendiri bukan pria yang sembarangan berkawan, terlebih terhadap perempuan.
Nathan cukup terkenal oleh orang-orang disekitarnya sebagai pria dingin yang tak boleh diusik untuk urusan hatinya, bahkan kehidupannya sepenuhnya adalah miliknya yang tak boleh dicampuri siapapun.
Nathan, pria keras kepala yang hanya ramah atas kehendaknya sendiri, bukan karena ingin menyenangkan orang lain.
***

Yvonne’s Romance – #2 Sofa Merah
20 Agustus 2022 in Vitamins Blog
Yvonne merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk yang terletak di tengah ruang kamar pribadinya. Sudah memasuki hitungan seminggu Yvonne tinggal di apartemen milik Lucas. Walaupun mereka tinggal bersama dalam satu atap, mereka tidak pernah banyak bertemu di dalam apartemen tersebut. Lucas lebih sering beraktivitas di luar dan berada di lokasi syuting dengan waktu yang tak menentu, namun saat ia memiliki kesempatan untuk pulang di malam hari, ia selalu menyempatkan diri untuk meminta Yvonne menceritakan hasil bacaannya dari novel yang telah dia berikan tempo hari, setidaknya sudah dua hari ini Lucas selalu pulang di malam hari dan menanyakan perkembangan Yvonne melaksanakan tugasnya membaca novel tersebut.
Tiga hari pertama kedatangan Yvonne, Lucas lebih banyak mencuri waktu dari kesibukan syutingnya untuk mengajak Yvonne jalan-jalan agar bisa mengenal lebih dekat suasana kota metropolitan yang dibanggakannya dan sudah berapa tahun belakangan ini menjadi rumah kedua bagi Lucas. Yvonne berterima kasih atas inisiatif Lucas meski jalan-jalan bersama Lucas juga tidak bisa dikatakan kegiatan yang menyenangkan bagi Yvonne karena Lucas selain bersikap dingin dan semaunya, ia juga terlalu banyak waspada hingga membuat Yvonne muak hingga rasanya ia ingin mengeksplorasi kota itu sendirian saja.
Tidak menyenangkan.
Kendati lebih banyak menumpuk kesal, Yvonne tak menuntut apapun, karena ia mau tidak mau harus mengerti bahwa untuk seorang Lucas, berhati-hati ketika berada di tempat umum sangatlah penting. Seorang publik figur tidak pernah tahu kapan ia bertemu dengan penggemarnya atau orang-orang yang bahkan berpotensi merusak popularitasnya sehingga menjadi waspada dan sangat berhati-hati sangatlah wajar untuk seorang Lucas.
Tiga hari rutinitas berkeliling kota yang diberikan Lucas tentu saja bukan sesuatu yang bisa diterima cuma-cuma oleh Yvonne. Setelah tiga hari yang tidak begitu menyenangkan bagi Yvonne, Lucas mulai memintanya untuk membuat ringkasan dari novel yang diberikannya sebagai imbalan atas kebaikan hatinya versi pola pikirnya sendiri, padahal Yvonne sama sekali tidak merasa berhutang budi apapun. Namun ketika Lucas membawa perihal tidak mengizinkan Yvonne tinggal di apartemennya apabila tidak bersedia membaca novel pemberiannya untuk meringkas alur cerita yang Lucas tak ingin membuang waktunya untuk duduk manis membaca semuanya, maka Yvonne terpaksa bertekuk lutut dan mengibarkan bendera putih, menyerah.
Yvonne tidak ingin pulang kembali ke kota kecilnya setelah akhirnya ia mampu terbang melintasi cakrawala untuk menjejakkan kaki di kota impiannya dan jika itu berarti ia harus bertahan dengan syarat dari orang tuanya untuk tinggal satu atap dengan Lucas, maka ia akan berjuang menyanggupinya sampai titik darah penghabisan, tekad bulat. Ia juga akan bertahan dengan sikap Lucas yang tak bisa ditebak terhadapnya.
Lucas mulai menunjukkan betapa sibuknya ia dengan pekerjaannya dan Yvonne yang masih belum punya arah tujuan mau tidak mau mulai membangun rutinitasnya sendiri yang didominasi dengan kegiatan membaca novel itu sebagai prioritas utama dan untungnya ia menemukan kafe yang nyaman untuknya, kafe milik Nathan.
Yvonne sebenarnya bisa saja menghabiskan waktunya di dalam apartemen seharian, hanya saja dia belum terbiasa dengan rasa sepi dan hidup sendiri di apartemen milik Lucas yang mewah tapi terasa hampa. Tidak ada siapapun kecuali asisten rumah tangga yang selalu datang untuk bersih-bersih di pagi hari selama beberapa jam. Untuk makan sehari-hari sudah tersedia jasa catering yang dipesan oleh Lucas hingga Yvonne benar-benar tak perlu mengkhawatirkan apapun untuk tuntutan hidup sehari-hari. Tapi semua itu tak membantu dalam mengatasi rasa jenuh dan hampa yang dirasakan Yvonne. Karena itu lah, Yvonne lebih memilih mencari suasana yang terasa nyaman dan menyenangkan di luar sana, menyusuri trotoar dari depan apartemen hingga mencari ujung jalan yang sanggup dilaluinya dengan berjalan kaki dan menyadari betapa banyak kafe di deretan apartemen tempat ia tinggal saat ini.
Meski ia sudah mengunjungi beberapa kafe yang berjejer rapi tersebut, hanya kafe milik Nathan yang membuatnya merasa nyaman. Sepasang matanya terasa dimanjakan, sepasang telinganya terbuai, sepasang kakinya tertuju tanpa perlawanan, rasanya ia bahkan ingin tambatkan hatinya saja di tempat itu sebab menghabiskan waktu seharian penuh di tempat itu rasanya sangat menyenangkan. Sudah tiga hari ini perasaan itu tidak memudar dan ia masih ingin terus berkunjung. Kebetulan sekali ternyata kesan pertama bertemu pemilik kafe itu terasa menyenangkan.
“Rasanya aku ingin cepat pergantian hari dan kembali ke kafe itu,” gumam Yvonne sembari menatap langit-langit kamarnya yang membiaskan cahaya lampu terang lantas menjelma menjadi kilat halus di mata hazelnya.
“Hari ini menyenangkan, beruntung rasanya bertemu dengan Nathan.”
Kedua kelopak mata Yvonne mulai meredup dan rasa kantuk mulai membuai kesadarannya. Pekat malam yang ia lihat dari balik kaca jendelanya seakan membujuknya agar segera mencicip lelap yang menjanjikan hari esok akan lebih menyenangkan untuk disambut dengan tubuh dan jiwa yang lebih kuat dan segar karena cukup beristirahat. Jadi, istirahatlah.
Rasanya Yvonne baru saja terlelap dalam hitungan sepersekian detik sesaat sebelum bunyi ketukan pintu yang keras dan tegas menyadarkan dalam satu sentakkan. Dan suara yang menyusul memanggil-manggil namanya disela jeda ketukan pintu kamarnya membuatnya memutar bola matanya dengan kesal.
“Lucas!” celetuk Yvonne dalam hatinya lantas senyum kecut ikut menghiasi bibir mungilnya.
“Yvonne! Apa kau sudah tidur? Kau belum laporan hasil bacaanmu hari ini, cepat ke ruang tengah!” teriak Lucas dari balik pintu dan langkahnya terdengar menjauh.
Yvonne mengusap kedua matanya dengan malas, rasanya ia baru saja akan masuk ke dunia mimpi yang menyenangkan namun segalanya rusak karena Lucas mengusiknya. Meski ia mengambil waktu lama untuk bangkit dari tempat tidurnya, pada akhirnya ia menyeret langkahnya dengan berat untu menuju ruang tengah di mana Lucas berada. Tak lupa ia mengambil buku novelnya untuk dibawa bersamanya saat menemui Lucas.
Mata Yvonne tertuju pada secarik kertas yang tergeletak di mejanya, gambar naga buatan Nathan. Yvonne meraih gambar tersebut, namun ia ragu membawanya. Ia tak ingin ada pembicaraan tentang gambar itu bersama Lucas, sehingga keraguannya membuatnya mengembalikan kertas tersebut di meja lantas berlalu menuju ruang tengah hanya dengan buku novelnya saja.
Rupanya Lucas tengah berbaring di sofa. Sebotol air mineral yang sudah tandas isinya tergeletak di atas meja tepat di dekat Lucas berbaring. Pantas saja meskipun Yvonne tidak menanggapi panggilan Lucas serta tak segera beranjak menemuinya, Lucas tak meneriakinya sama sekali. Hening, seakan menghilang begitu saja.
Yvonne mendekati dengan perlahan, sedikit berjingkat lalu mengambil tempat duduk di sofa lainnya yang hanya untuk satu orang. Yvonne menipiskan bibirnya ketika melihat betapa tenangnya Lucas berbaring di sofa tersebut. Sofa panjang berwarna merah menyala dan memiliki bentuk yang terkesan mewah, elegan dan harus Yvonne akui sangat cocok menjadi tempat untuk seseorang dengan tampang seperti Lucas berbaring di sana. Seperti singgasana, seperti pembaringan yang nyaman.
Yvonne mengernyitkan dahinya karena Lucas tak kunjung membuka matanya meski Yvonne sudah duduk manis dan siap memberi laporan atas bacaannya hari ini.
“Apa dia begitu lelah?” Yvonne mempertanyakan dalam hatinya lalu memerhatikan wajah Lucas yang tertidur dengan sangat lelap.
Benar-benar pantas, begitulah yang dipikirkan Yvonne. Ini adalah malam ketiganya melihat Lucas berbaring di sofa merah itu, namun biasanya Lucas hanya merebahkan tubuhnya dan tetap terjaga mendengarkan Yvonne bercerita. Hari ini Yvonne baru memperhatikan Lucas yang terlelap dengan saksama, pria itu benar-benar artis. Wajahnya nyaris sempurna untuk kategori pria tampan, jadi bagaimana mungkin Yvonne sedikitpun tak merasa beruntung mengenal Lucas dalam hidupnya?
Sudah hitungan tahun tidak melihat Lucas, dunia perantauan dan pekerjaan nampaknya telah banyak mengubah penampilan Lucas yang sekarang terlihat semakin berkelas. Wajahnya semakin tampan meski tak jauh berbeda dengan wajah Lucas di masa lalu yang dikenal Yvonne sebab memang seolah sudah menjadi takdir seorang Lucas untuk lahir dan tumbuh menjadi lelaki tampan yang mempesona.
Hidup di kota metropolitan memang pilihan yang tepat untuk Lucas hingga ia bisa menjadi salah satu dari jejeran artis papan atas yang digemari masyarakat.
Lucas dan Yvonne sudah bertemu sejak mereka masih kecil meski mereka memiliki rentang usia yang sedikit jauh. Lucas lebih tua beberapa tahun dari Yvonne, namun keduanya selalu terlibat dalam beberapa kegiatan masa kecil bersama lantaran ibu mereka bersahabat sangat kental dan mereka berdua juga tahu bagaimana terobsesinya ibu mereka untuk menjodohkan mereka di masa depan.
“Aku ini lebih tua darimu lima tahun, kau seharusnya memanggilku kakak,” gerutu Lucas di suatu hari ketika mereka berusia belasan tahun.
“Tidak mau. Tinggimu saja hanya berbeda sedikit dariku, kau juga tidak terlihat dewasa karena suka menggangguku, jadi untuk apa?” rutuk Yvonne sembari membusungkan dadanya dengan angkuh.
Yvonne teringat bahwa tubuh Lucas tidaklah setinggi sekarang bahkan nyaris dijangkau oleh Yvonne ketika mereka berada di usia remaja. Dan sekarang melihat Lucas terbaring di sofa merah andalannya hingga sepasang kakinya yang semampai melewati batas sofa dan tergantung bebas hingga nyaris menapakkan kakinya di lantai membuat Yvonne tersadar bahwa Lucas tak lagi bocah yang pantas ia rendahkan ukuran tubuhnya. Yvonne bahkan jadi tersenyum lucu setelah memperhatikan tubuh Lucas sekarang, lengan yang berotot khas para lelaki jantan dan dadanya yang terlihat bidang membuat Yvonne terkekeh.
“Sejak kapan tubuhnya jadi seperti itu? Dia pasti berusaha keras mendapatkannya?” gumam Yvonne sambil terkekeh kecil.
“Heh, apa yang kau tertawakan? Apa kau sudah puas memperhatikanku seperti itu? Wajahmu itu seperti mau melahap orang, tahu!” celetuk Lucas tiba-tiba sembari membuka matanya sedikit dan melirik tajam ke arah Yvonne.
Yvonne segera merengutkan wajahnya, menunjukkan rasa kesal yang terang-terangan dan meraih bantal sofa yang berada di balik punggungnya lantas melempar dengan keras ke arah wajah Lucas.
“Aduh! Sakit! Wajahku ini berharga!” celetuk Lucas dan segera terduduk sembari mengusap wajahnya.
“Bersyukurlah aku tidak melempar buku novel yang kubawa ini ke wajahmu melainkan hanya bantal empuk.”
“Iya, iya. Sudahlah, aku lagi lelah. Jadi, apa hasil bacaanmu hari ini?” Lucas kembali membaringkan tubuhnya di sofa sembari menunggu jawaban Yvonne.
“Kalau kau lelah, sebaiknya kau pergi tidur. Kau pikir sofa itu tempat tidur kedua? Lama-lama warna merahnya memudar dan bentuknya rusak karena selalu kau tempati seperti itu.” omel Yvonne lagi.
“Akuakan pergi tidur di kamarku setelah mendengar laporanmu hari ini, cepatlah, aku tidak punya banyak tenaga untuk mendengar hal lain.” Lucas mendengkus karena tak sabar.
“Memangnya kalau kau berbaring seperti itu, apa bisa menjamin kau tidak tertidur dan meninggalkanku berceloteh sendirian?” tanya Yvonne lagi bersikeras menjadi kritis.
“Astaga, Yvonne, dari kemarin dan kemarinnya lagi aku selalu berbaring di sofa ini mendengarkanmu dengan penuh perhatian. Hari ini aku memang sangat lelah tapi aku takkan meninggalkan satu hari untuk menunda memahami isi novel itu. Kau tahu kan aku mendapat kesempatan dari produser untuk memerankan tokoh utama dari novel itu dan hanya punya waktu satu bulan untuk memahami segala isinya agar aku bisa mendalami peran dengan baik. Setidaknya begitulah yang diharapkan produser dariku, sebuah pengalaman membaca dan pemahaman yang baik akan seluruh jalan ceritanya. Jadi, ceritakanlah.”
Yvonne terdiam, ia tersadar hal-hal yang terlupa karena selalu menganggap Lucas makhluk yang menyebalkan. Benar, Lucas selalu berusaha keras seperti itu menjalani kehidupannya, bersungguh-sungguh dan mampu fokus dalam keadaan apapun. Yaa, wajar segala sesuatu yang diraihnya memang sepadan dengan apa yang ia usahakan. Menjadi artis bukan tentang merawat diri, bersenang-senang, hidup berlebihan atau bermalas-malasan berbaring di sofa merah nan mewah sepanjang hari. Ada usaha, ada upaya, ada kerja keras hingga semua mampu diraih seperti sekarang.
“Yvonne, aku menunggu.”
Yvonne tersadar dari renungannya ketika Lucas berkata singkat dan dingin seperti itu. Pria itu masih berbaring sembari memejamkan matanya rapat-rapat namun Yvonne bisa merasakan betapa telinga pria itu menanti untuk menangkap getaran yang menjelma menjadi kalimat-kalimat yang bersumber dari suara Yvonne.
Sebelum akhirnya Yvonne bersuara, ia membuka novelnya dan menyadari suatu hal ketika ia menatap lembaran yang telah ia tandai. Ia terlupa, bahwa hari ini tidak ada alur cerita yang perlu dipahami melainkan hanyalah deskripsi-deskripsi makhluk naga yang digambarkan dengan detail hingga beberapa halaman.
“Lucas, sepertinya hari ini kau memang bisa segera istirahat. Hari ini aku membaca bagian yang terbaru tapi itu hanya menggambarkan sosok seekor naga yang muncul di sebuah hutan terlarang dan warnanya hitam pekat.” terang Yvonne bersemangat.
“Begitu kaah? Baiklah, aku mau tidur.” celetuk Lucas setelah mendengarkan penjelasan Yvonne dan rasanya ia bersyukur bahwa ia bisa segera melengos pergi ke kamarnya.
Lucas pergi menuju kamarnya, meninggalkan Yvonne yang masih terduduk sendirian sembari melihat punggung Lucas yang semakin menjauh dan menghilang dibalik pintu kamarnya sendiri.
Keheningan terbentang, Yvonne sendirian dan merutuk dalam gumaman yang hanya terdengar di telinganya sendiri, “Dasar, bisa-bisanya dia yang tadi memanggil sekarang malah pergi meninggalkan. Cih.”
Yvonne kembali ke kamarnya, merebahkan kembali tubuhnya ke kasur empuk yang dirindukan. Melepas penat dan kesal lantas pikirannya melayang menanti hari esok.
“Kenapa rasanya ingin segera hari esok? Aku ingin ke kafe itu, membaca dan berdiskusi dengan Nathan.” gumam Yvonne lagi lalu lambat laun ia tertidur bersiap menjelajahi alam mimpi yang bisa mengejutkannya dengan alur cerita apapun.
***

Yvonne’s Romance – #1 Buku Tebal
14 Agustus 2022 in Vitamins Blog
“Kau harus membaca novel ini sampai selesai, setidaknya setiap hari kau harus ceritakan ringkasan satu bab-nya di malam hari. Kau harus membuatku memahami isi ceritanya, kau mengerti?”
Yvonne menutup dengan keras buku novel tebal yang tengah ia baca. Kalau saja ia tidak sedang berhutang budi pada Lucas, ia pasti tidak akan repot-repot mengisi waktunya sepanjang hari untuk mencoba memahami isi cerita dalam novel di genggamannya yang sama sekali membuatnya tak berminat. Buku novel itu sangat tebal, bahkan bagi Yvonne novel itu lebih cocok menjadi bantal tidurnya jika saja buku novel itu mampu menjelma menjadi tumpukan bulu angsa nan empuk yang menumpuk dalam satu buntalan kantung kain putih lembut.
Buku novel itu memang terkesan seperti buntalan kain berbentuk kotak layaknya bantal, hanya saja ukurannya lebih kecil seperti bantal kuno milik masyarakat Jepang di zaman Edo. Bagi Yvonne yang tidak begitu tertarik dengan cerita fiksi fantasi, membaca satu bagian saja cukup membuat dia lelah dan selalu ingin segera menutup buku novel tersebut. Sampulnya sendiri dari material yang keras, sehingga saat Yvonne menutupnya dengan kesal, bunyinya cukup menarik perhatian orang lain di sekitarnya termasuk oleh pria yang tiba-tiba muncul di depan matanya.
“Hai, kau baik-baik saja?”
Yvonne terperanjat menyadari pria yang asing baginya tiba-tiba menyapanya dan sudah berada di depan mejanya entah sejak kapan.
“Siapa? Apakah pelayan kafe?”
Yvonne memerhatikan dengan saksama sosok pria di hadapannya. Kedua bola matanya yang membulat penuh dengan iris warna hazel yang indah memindai dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa memperhitungkan kesopansantunan yang harus ia jaga. Pria itu tidak terlihat seperti para pelayan kafe yang sudah tiga hari ini berinteraksi dengan Yvonne. Tidak memakai seragam khas para pelayan kafe seperti papan nama, sepatu sneakers, maupun baju T-shirt berwarna cokelat cappuccino polos yang biasanya ia lihat. Perasaannya seketika merasa was-was dan ia berusaha membentengi diri dengan tatapan tak bersahabat dan berpikir jika pria itu maju selangkah lagi untuk berniat jahat kepadanya, maka buku novel menyebalkan di gengggamannya akan segera menjadi senjata untuk melindungi dirinya.
Setidaknya sekali saja buku novel itu akhirnya bisa berguna baginya, kan?
“Oh, maaf, aku tidak bermaksud jahat. Aku pemilik kafe ini. Ini kartu namaku, Nathan.”
Seakan memahami sikap Yvonne yang tidak bersahabat, pria yang mengenalkan dirinya sebagai Nathan buru-buru memperkenalkan dirinya dan menyodorkan kartu namanya dengan cepat. Yvonne sendiri mengambil kartu nama tersebut dengan hati-hati dan membaca setiap tulisan yang tercetak di permukaan kartu dengan saksama. Setelah memahami deretan tulisan yang tercetak di kartu mungil tersebut, barulah Yvonne menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan pemilik kafe, bukan pria pengunjung tak bermoral yang sering kali mendatangi sebuah kafe hanya untuk iseng menghampiri perempuan-perempuan yang duduk sendiri di sudut ruangan seperti yang Yvonne lakukan saat ini. Yvonne lantas berdiri dan menundukkan sedikit kepalanya untuk memberi hormat karena ia sadar diri bahasa tubuhnya beberapa detik yang lalu terang-terangan mencurigainya pria itu, Nathan.
“Maaf, saya sudah berprasangka buruk. Maaf atas tindakan saya barusan, apa saya melakukan kesalahan sampai anda mendatangi saya? Apa saya membuat ketidaknyamanan di sini?”
Keheningan tercipta sesaat karena Nathan hanya terdiam dengan senyum tipis melengkung di bibirnya meski tak nampak oleh Yvonne yang masih tertunduk malu. Yvonne sendiri masih tenggelam dalam dugaan-dugaan buruk yang bisa ia bayangkan atas dirinya. Ini sudah hari ketiganya menghabiskan waktu di kafe itu dan ia akui sepanjang waktunya mungkin ia banyak mendengkus kesal dan bolak-balik membuka tutup buku novel dihadapannya yang tentunya seringkali menimbulkan bunyi dentuman keras.
Apa mungkin karena Yvonne selalu duduk di bangku yang sama?
Apa mungkin karena Yvonne terlalu lama duduk dan tak sebanding hanya dengan memesan secangkir cappuccino saja?
Yvonne masih tenggelam dalam pikirannya hingga rambut panjang lurus berwarna kecokelatan miliknya yang terurai sebagian telah menenggelamkan wajahnya hingga Nathan tak dapat melihat raut wajah perempuan itu meski ia sangat yakin perempuan itu pastinya sedang cemas karena kehadirannya saat ini.
“Kau tidak perlu merasa bersalah begitu, aku tidak bermaksud kesini untuk menegur apapun, aku hanya ingin menghampirimu saja.”
Yvonne mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya menatap lekat pada wajah Nathan yang ternyata memang menunjukkan kesungguhan atas kata-kata yang ia ucapkan. Setidaknya Yvonne melihatnya seperti itu, ia tak menemukan kebohongan di sana, pada raut wajah Nathan.
“Boleh kah aku duduk di sini?” ucap Nathan memecah keheningan yang masih dibangun oleh Yvonne.
Tersadar akan sikapnya yang masih mematung, Yvonne segera kembali duduk dan mempersilakan Nathan untuk duduk di bangku kosong yang terletak di hadapannya.
Nathan tersenyum kembali dan itu cukup mencairkan suasana canggung sebelumnya. Yvonne sendiri hanya diam menunggu Nathan untuk mengatakan sesuatu, sebab Nathan yang datang menghampirinya, itu artinya dia yang ingin bicara, bukan?
Nathan berdehem sebelum mulai bicara kembali, “Sudah tiga hari ini kau datang kemari, duduk di tempat yang sama dan membaca buku yang sama, tapi, sepertinya kau tidak terlalu menikmati apa yang kau baca? Apa kau kesulitan?”
Yvonne hanya menatap buku yang tergeletak di depan matanya, ia tidak tahu apa ia perlu cerita pada pria yang baru hitungan menit muncul di hadapannya? Tapi kehadiran Nathan seperti angin segar di saat dia sedang suntuk karena beban yang menggelayutinya saat ini.
Karena perintah yang diberikan Lucas kepadanya!
Tak kunjung menjawab pertanyaannya, Nathan beralih menanyakan hal lain, sebab ia hampir saja lupa setidaknya ia harusnya bertanya nama lebih dulu.
“Kalau kau tidak mau menceritakannya, tidak apa-apa. Maaf aku sudah bertanya. Aku hampir lupa untuk menanyakan namamu, maafkan aku.”
“Eh?” Yvonne tertegun karena ia baru sadar bahwa Nathan sudah memperkenalkan dirinya sedangkan ia sendiri malah belum memberi tahu namanya bahkan masih mengisi celah dengan menimbang-nimbang banyak hal.
“Oh, namaku Yvonne. Emm, itu, aku, sejak tiga hari yang lalu punya tugas untuk membaca novel ini dan membuat ringkasannya, jadi aku datang ke sini untuk mencari tempat nyaman untuk membaca. Dan iya, aku memang kesulitan. Sebenarnya ini bukan novel yang ingin kubaca, aku bahkan tidak biasanya membaca novel. Sejujurnya aku lebih suka membaca cerita bergambar seperti komik. Melihat barisan tulisan yang menumpuk rasanya mataku ingin muntah, otakku jadi rabun harus membayangkan gambaran-gambaran karakter fantasi yang diceritakan. Ah, menyebalkan!”
Entah dorongan apa yang membuat Yvonne yang tadinya was-was berubah mengutarakan segala kekesalannya. Ya, Yvonne memang seperti itu, begitu mudah mengutarakan yang ia rasakan tanpa dinding batasan kokoh yang seharusnya ia bangun dan seketika saja Nathan terkekeh mencerna kata-kata Yvonne yang terasa ganjil, selain itu ia tak menyangka Yvonne bereaksi seperti itu hingga ia tak mampu lagi menahan diri untuk tak melepas tawa renyahnya.
Mata mau muntah?
Otak rabun?
“Hahaha, yaa ampun, aku tidak menyangka kau akan berkata seperti itu, apa novel itu benar-benar membuatmu kacau?”
Nathan masih tertawa sedangkan Yvonne mengangguk dengan mantap sembari menunjukkan raut wajah yang serius akan kata-katanya. Perlahan-lahan tawa Nathan pun mereda, ia mulai mengernyitkan dahinya karena rasa ingin tahu mulai menyerangnya.
“Maafkan aku, setahuku novel yang kau baca itu kabarnya akan dirilis menjadi sebuah film. Yaa, itu hanya kabar burung yang kudengar. Bukan kah itu berarti novel itu bagus?”
Iya, benar. Yvonne bukannya tidak tahu kalau novel itu akan menjadi film layar lebar yang diprediksi akan menguntungkan pihak perfilman, oleh karena itu sejak sekarang mereka berusaha mencari pemeran terbaik untuk film tersebut. Justru saat ini Yvonne harus menghabiskan waktunya untuk membaca novel itu secara terpaksa karena ia sangat tahu novel itu akan menjadi sebuah film yang tokoh utamanya digambarkan sebagai pria gagah berani, tegas, tampan nan rupawan, dan akan diperankan oleh Lucas.
Lucas, aktor yang sedang naik daun dan juga pria yang sekarang sedang tinggal bersamanya. Lebih tepatnya sejak kedatangan Yvonne di kota metropolitan ini, ia harus tinggal seatap dengan Lucas karena kemauan kedua ibu mereka yang bersahabat sejak kecil dan terobsesi untuk menjodohkan mereka berdua hingga dengan tidak masuk akal memaksa mereka berdua untuk tinggal bersama. Mereka pikir melakukan itu akan membuat benih-benih cinta akan timbul diantara Yvonne dan Lucas yang bersikeras tidak ingin dijodohkan sejak mereka beranjak dewasa.
Tentu saja, itu tidak mungkin. Lucas mungkin aktor yang tampan dan mempesona, tapi Yvonne tak melihatnya seperti itu. Lucas hanya pria brengsek yang memanfaatkan kehadirannya Yvonne saat ini.
Yvonne tidak ingin kembali ke rumahnya di kota kecil nun jauh di sana, impiannya memang tinggal di kota metropolitan ini dan itu berarti saat ini ia harus bersedia menerima syarat yang dibuat oleh ibunya, yaitu harus tinggal bersama Lucas setidaknya selama tiga bulan. Lucas sendiri, tentu saja tinggal di apartemennya berarti harus ada imbalannya. Pria itu tidak pernah mau rugi dan sebagai gantinya Yvonne harus membaca novel tebal yang sekarang ini dalam genggamannya dan menceritakan ringkasannya kepada Lucas sedetail mungkin. Sial!
“Kau harus membaca novel ini sampai selesai, setidaknya setiap hari kau harus ceritakan ringkasan satu bab-nya di malam hari. Kau harus membuatku memahami isi ceritanya, kau mengerti?”
Gila! Bukankah seharusnya para ibu itu khawatir jika anaknya tinggal bersama? Ini malah memberi peluang seakan siap menyambut dengan tangan terbuka jika Lucas dan Yvonne datang menghadap dan berkata, “Izinkan kami menikah, kami sudah saling mencintai.”
Membayangkan hal itu membuat Yvonne bergidik ngeri hingga ia terlupa bahwa Nathan sedari tadi masih memperhatikannya dan tak satupun gerak gerik aneh Yvonne yang terlewat dari pandangan Nathan saat ini.
“Yvonne,” panggilnya hati-hati.
“Ah, maaf, aku melamun. Otakku merasa buntu. Kau mau tahu sesuatu? Aku sedang membaca bab tiga dari novel ini yang berjudul Naga Penjaga Telaga Berjelaga. Kau sadar rima itu? Naga Penjaga Telaga Berjelaga. Itu aneh. Bukan hanya itu, penulisnya bahkan menggambarkan sosok naga tersebut sebanyak tiga sampai empat halaman, astaga! Mungkin berikutnya dia akan menulis penggambaran dari sosok wanita cantik bertubuh molek dengan pakaian mini sebanyak sepuluh halaman karena nafsu yang membuncah dalam imajinasinya yang mesum!”
“Pffft!” Nathan sangat ingin tertawa terbahak-bahak namun ia menahannya sekuat tenaga karena tak ingin merusak suasana tenang di kafe yang ia bangun sebagai tempat para pengunjung menenangkan diri dengan menyeruput secangkir minuman hangat sembari mendengar alunan akustik yang menyejukkan suasana hati. Tentu saja itu seperti bunuh diri jika Nathan sendiri yang malah menjadi biang keributan tak menyenangkan di kafe itu.
Perempuan itu, Yvonne, membuat Nathan tidak menyesal menghampirinya. Nathan memang sudah diam-diam memperhatikan kedatangan Yvonne sejak pertama berkunjung sedangkan Yvonne tidak tahu bahwa tak semudah itu untuk seorang Nathan yang berkepribadian serius tertawa renyah tiba-tiba, namun ajaib berhadapan dengan Yvonne secara langsung terus membuat Nathan merasa tergelitik setiap kali perempuan itu bicara. Tidak, lebih tepatnya sedang mengomel.
Yvonne sendiri tak menyadari kelakuannya karena perasaan kesal tengah campuraduk dalam benaknya, tentang orang tuanya, tentang Lucas, hingga novel yang terpaksa dibacanya.
Nathan berdehem kembali. Kali ini ia mencoba bicara serius setelah menenangkan dirinya meski masih harus melihat Yvonne yang bersungut-sungut kesal. Tapi Nathan menguatkan dirinya untuk tidak terpancing untuk tertawa bahkan terkekeh apalagi jika harus sampai terbahak-bahak.
Fokus, Nathan!
“Yvonne, mungkin yang membuatmu tersiksa membaca novel itu karena sejak awal kau sudah tidak berminat, kau juga tidak membangun niat, kau apatis hingga tak mau melihat hal-hal indah yang bisa kau baca, kau sengaja membutakan matamu dari hal-hal menarik yang bisa kau lihat. Yaa, aku tidak bisa menyalahkanmu karena kau sendiri bilang bahwa kau terpaksa membacanya, jadi bukan seperti pembaca yang memang tertarik dan penasaran ingin membacanya sehingga ada perasaan nikmat yang terbangun oleh rasa ingin tahu yang menggebu, kau mengerti maksudku?”
Yvonne tertegun mendengar kata-kata Nathan yang diucapkan dengan perlahan namun terasa melekat dalam otaknya yang rasanya masih buntu sebelumnya. Mudah dipahami tapi terasa berbobot dan Yvonne menyukainya.
Sosok yang menyenangkan!
“Kalau kau mau, aku bisa membantumu memahami setiap tulisan yang kau baca. Maksudku kita mungkin bisa berdiskusi bersama setiap kau selesai membaca bagian-bagiannya, itu pun jika kau memang bermaksud rutin datang kemari, kupikir kau sudah menjadikan kedatanganmu kemari sebagai rutinitas,”
“Ah, kau menyadari itu yaa?” gumam Yvonne terperangah oleh dugaan Nathan yang tepat.
“Iya, aku melihat kau datang berturut-turut dalam tiga hari ini, duduk di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, sepertinya ini rutinitas yang kau bangun dan kau sepertinya suka keteraturan.”
Yvonne terkekeh dan mengangguk penuh semangat, “Kau benar, selain itu sebenarnya ada tiga kafe yang kudatangi sederet dengan apartemen tempatku tinggal, tapi aku suka di sini.”
“Oh yaa? Aku sebagai pemilik kafe ini merasa tersanjung. Kenapa begitu?” tanya Nathan penuh antusias. Suatu kehormatan baginya mendapat pujian atas kafe yang ia bangun dengan penuh kemandirian ini.
“Aku suka pot bunga putih mungil yang diletakkan di setiap meja. Aku suka interior nuansa cokelat oak yang mendominasi. Aku suka aroma kopi yang menguar lembut dan tidak membuatku pusing seperti kafe-kafe kelas internasional yang beberapa kali kudatangi dan aku suka alunan musik akustik yang mengalun sayup-sayup di telinga. Selain itu, aku suka bahkan sangat suka dengan semua pigura yang dipenuhi tulisan-tulisan menyenangkan untuk dibaca. Setiap kali aku mau menyerah membaca novel itu, aku juga melihat tulisan di dinding bagian situ,”
Yvonne menunjuk sebuah pigura yang terisi tulisan sederhana, “Don’t Give Up, Miracles Created On Your Bones.”
“Aku jadi kembali semangat, hehe.” Yvonne terkekeh pendek untuk mengakhiri penjelasannya.
“Kau tidak tahu betapa sangat tersanjungnya aku, karena semua penataan dari kafe ini adalah sesuai seleraku dan kau memujinya dengan sungguh-sungguh, terima kasih.” ucap Nathan dengan serius.
“Aku yang seharusnya berterima kasih karena kau sudah menghampiriku dan memberiku motivasi,”
“Ngomong-ngomong tadi kau kesulitan dengan penggambaran naga yaa? Aku rasa aku punya sesuatu yang bisa membantumu,”
Nathan bergegas meninggalkan Yvonne sejenak lalu ia kembali membawa sebuah pensil dan secarik kertas putih polos.
“Coba kau baca perlahan setiap kalimatnya, aku akan menggambarkannnya untukmu.”
Meski sedikit ragu dengan perintah Nathan, Yvonne mencoba mengikuti tanpa bantahan dan mulai membaca dengan pelan dan perlahan setiap kalimat yang tertulis untuk menggambarkan sosok naga dalam cerita tersebut sedangkan Nathan perlahan-lahan menggoreskan pensilnya, hati-hati dan begitu tenang hingga Yvonne merasa semakin lama semakin takjub dengan apa yang saat ini dia baca. Membaca perlahan untuk menyampaikan pada Nathan membuatnya mengematkan baik-baik apa yang sedang ia baca dan setiap melirik apa yang tengah dilakukan Nathan, Yvonne semakin merasa takjub. Gambar yang dibuat Nathan sungguh indah, bahkan meski hanya dengan sebuah pensil dan berupa sketsa kasar.
“Itu naga yang dimaksud dalam cerita ini?” Yvonne tertegun.
“Bagus, bukan?” tanya Nathan dengan percaya diri.
“Kau pandai menggambar? Keren!” Mata Yvonne berbinar penuh kekaguman pada gambar yang ditunjukkan Nathan.
“Kau suka? Kau boleh menyimpannya,” Nathan memberikan kertasnya kepada Yvonne.
Yvonne menerima dengan senang, ia memandangi gambar pemberian Nathan dengan saksama, lalu mata hazelnya tertuju pada tulisan beberapa huruf yang terletak di sudut kertas.
“NTNL? Kenapa kau memberi inisial seperti ini?” tanya Yvonne dengan gamblang dan hanya dipenuhi rasa ingin tahu.
“NTNL adalah nama pena penulis novel yang kau baca itu. Kau sudah membacanya hingga hari ini tapi kau tidak memperhatikan siapa penulisnya yaa?” Nathan terkekeh kembali.
“Buat apa aku peduli? Aku mau baca tulisannya, bukan mau tahu siapa penulisnya. Kau juga bukannya seharusnya menulis namamu saja di gambarmu ini?” celoteh Yvonne yang membuat Nathan semakin terkekeh.
“Tidak, tidak perlu. Biarkan saja tertulis seperti itu, anggap saja aku sedang menghargai imajinasi penulisnya. Apa kau tahu? Sosok naga itu adalah tokoh penting di novel itu, setara sama tokoh utamanya, nanti kau akan mengerti jika kau sudah selesai membacanya.”
Yvonne mengernyitkan dahinya sembari kembali menatap gambar yang diberikan Nathan.
Tokoh penting?
Begitu kah?
“Nathan, apa menurutmu tidak sebaiknya tanduk naga ini dibuat lurus saja seperti tanduk pegasus, mungkin?”.
“Apa? Kenapa kau ingin begitu? Bukankah memang sudah tertulis itu adalah dua tanduk kokoh bercabang serupa tanduk kijang yang menghiasi bagian atas kepalanya yang bersisik keras, bentuknya berulir dan ujungnya runcing,”
“Iya, aku tahu. Tapi aneh.” celetuk Yvonne keras kepala.
“Yvonne, memang makhluk dalam cerita itu diceritakan memiliki bentuk yang aneh dalam imajinasi yang liar, sebab cerita fantasi memang seperti itu,” Nathan menerangkan kembali dengan hati-hati dan merasa canggung sembari menggaruk pelipisnya yang tidak gatal.
“Benar juga, tapi sepertinya akan bagus kalau tanduknya lurus seperti pegasus lalu ujungnya memiliki bola terang, jadi bersinar dalam gelap malam. Latar waktu dalam novel ini kebanyakan malam gelap gulita dan selalu mencekam, dengan tanduk seperti lampu pastinya memudahkan si naga untuk terbang di kegelapan malam yang seperti itu, kasihan sekali ketika di hutan terlarang, naganya bisa tertabrak batang pepohonan tua yang rimbun. Warnanya juga gelap, digambarkan hitam pekat sepekat malam yang mengalami gerhana matahari penuh, dia sangat tidak terlihat, padahal saat kau menggambarnya naga itu punya lekuk tubuh yang mengagumkan, menguarkan aura bengis tapi berkilau,” celetuk Yvonne dengan penuh percaya diri yang membuat Nathan lagi-lagi menahan tawanya.
“Astaga, Yvonne.” batinnya.
Padahal pertama kali melihat Yvonne datang di kafenya, Yvonne terlihat seperti perempuan anggun pada umumnya, berkaki jenjang menggunakan gaun selutut yang terkesan lembut didukung oleh rambut panjang lurusnya yang tergerai indah. Tapi tak disangka Nathan yang awalnya hanya tertarik mendekati karena ini ketiga kalinya Yvonne bertandang dan kelihatan kesulitan membaca novel dalam genggamannya malah mendapat banyak hal yang menarik, setidaknya ia tak habis tergelitik oleh sikap Yvonne yang terlalu lugas.
Ya, novel itu.
Pemicu tekad Nathan untuk mendatangi Yvonne hingga berakhir dengan menawarkan diri secara impulsif untuk membantu Yvonne membacanya hingga tuntas adalah novel dalam genggamannya itu.
“Besok aku datang lagi yaa, terima kasih hari ini sudah membantuku.” pamit Yvonne setelah menyadari sudah waktunya ia harus kembali pulang dan ia harus beristirahat sejenak sebab malamnya ia harus menemui Lucas untuk menceritakan apa yang dia baca hari ini.
Nathan melepas kepergian Yvonne dengan senyuman ramah, melepas dengan tanda tanya yang menggelayuti perasaannya.
Apa tidak apa-apa jika aku bertindak seperti ini?
***