
CHAO XING (朝兴)
1 Februari 2017 in Vitamins Blog

PROLOG
***
“Nona muda tolong turun dari pohon itu sekarang!” Ju Fang—wanita muda berusia tiga puluh tahun itu berteriak keras, sekuat tenaga ia menekan keinginan kuatnya untuk ikut naik ke atas pohon cedar dimana Nona mudanya berdiri di atas dahan tertinggi tanpa rasa takut.
Ju Fang bisa saja nekat naik, namun ia kembali mengingatkan pada dirinya sendiri jika ia akan kesulitan turun nantinya. “Nona muda turun sekarang atau aku akan menghukummu!” teriaknya lagi, dengan debaran jantung yang semakin tidak menentu saat melihat putri asuhnya itu berjinjit, untuk melihat lebih jauh. “Nona, tolong turun sekarang juga, jangan paksa saya untuk menyusul anda naik,” pintanya nyaris putus asa.
“Zian sudah kembali! Zian sudah kembali!” Chao Xing berteriak kegirangan, mengabaikan permintaan Ju Fang. Ia melompat kecil di atas dahan dan nyaris membuat ibu asuhnya itu pingsan di tempat karenanya. “Zian sudah kembali.” Chao Xing berseru senang, dengan gesit ia turun lalu berlari sekuat tenaga untuk menyambut kedatangan Zian.
Ju Fang terduduk di atas rumput segar di bawahnya, wajahnya pucat-pasi karena rasa takut yang menyerangnya dengan hebat. Apa yang harus dikatakannya pada Mendiang Selir Rong jika sesuatu terjadi pada Chao Xing?
Wanita muda itu menggelengkan kepala pelan, dalam hati ia menegaskan jika nanti malam ia harus menghukum nona mudanya itu agar bersikap layaknya seorang putri bukan bersikap seperti bocah laki-laki berumur dua belas tahun.
Ju Fang perlahan berdiri, menepuk-nepuk kain roknya pelan lalu menengahkan kepala, menatap langit biru musim semi yang terlihat memesona. Dua belas tahun berlalu, namun hingga detik ini sepertinya Raja Jian Guo masih enggan menemui putrinya yang mulai beranjak dewasa.
“Sampai kapan anda akan menutup hati anda, Yang Mulia?” Ju Fang berkata lirih, begitu lembut selembut desau angin musim semi. “Puteri begitu mirip dengan Selir Rong,” tambahnya dengan mimik sedih. “Anda akan menyesal Yang Mulia. Anda akan menyesal karena tidak melihat bagaimana Puteri anda tumbuh,” lanjutnya sebelum berbalik, masuk ke dalam rumah sederhananya untuk menyiapkan makan siang.
***
“Zian kau sudah kembali!” Chao Xing berteriak girang, kedua tangannya terbuka lebar, menyambut kedatangan pemuda berusia delapan belas tahun yang terlihat gagah duduk di atas kuda jantan hitamnya yang perkasa. “Kau pergi lama sekali,” keluh gadis kecil itu, bibir merahnya mengerucut lucu. “Lebih lama daripada biasanya.”
Pertemuan Chao Xing dan Zian terjadi hampir empat tahun yang lalu. Chao Xing dan Ju Fang tidak sengaja menemukan Zian yang terluka hebat dan hampir mati kelaparan di kaki bukit. Keduanya lantas merawat Zian hingga pemuda itu sembuh, dan hubungan ketiganya pun terus terjalin baik hingga saat ini.
“Apa yang kau bawa untukku kali ini?” Chao Xing bertanya dengan ekspresi serius, sementara Zian menambatkan tali kekang kudanya pada sebuah pohon. “Jangan bilang kau tidak membawa apa pun untukku!” Chao Xing mulai merajuk, melipat kedua tangannya di depan dada.
“Chao Xing, apa kau percaya takdir?” tanya Zian tiba-tiba. Pemuda dengan wajah rupawan itu merebahkan diri di atas rumput, memejamkan mata, menikmati semilir angin yang memberinya kesejukan.
Kedua alis Chao Xing bertaut. “Apa kau menanyakan hal ini agar aku melupakan kesalahanmu?”
Zian terkekeh pelan, kedua kelopak matanya terbuka, menampilkan iris mata berwarna cokelat muda yang menawan. “Apa menurutmu pertemuan kita sebuah takdir?” tanyanya dengan nada suara berat.
“Mungkin saja,” jawab Chao Xing asal. Gadis kecil itu mengambil sebuah batu kecil, lalu melemparnya pada sungai di depannya. Chao Xing menekuk lututnya, menopangkan kepala, namun tatapannya menerawang jauh. “Mungkin karena takdir jugalah ayahanda membuangku,” tambahnya nyaris tak terdengar.
“Apa maksudmu?” Zian mendudukkan diri, menatap Chao Xing, penasaran. “Jadi kau masih memiliki ayah?”
Chao Xing mengangguk. Mereka memang tidak pernah membahas masalah ini, lagipula Zian tidak pernah bertanya. “Ayahku masih hidup,” terangnya sendu. “Beliau tinggal di ibu kota bersama keluarga besarnya.”
“Lalu kenapa kau tinggal bersama ibu asuhmu di tempat terpencil seperti ini?”
“Karena ayah membenciku,” jelas Chao Xing hampir menangis, “Kelahiranku menyebabkan ibuku meninggal, dan ayah marah padaku karenanya.”
Zian terdiam, kedua tangannya terkepal erat. Bagaimana bisa nasib Chao Xing tidak terlalu jauh berbeda dengan dirinya namun dengan alasan yang berbeda?
“Zian?!” panggil Chao Xing lirih.
Zian tidak langsung menjawab, dengan lembut ia membelai rambut hitam legam Chao Xing yang terurai indah.
“Mungkin ini hanya perasaanku saja,” Chao Xing memalingkan muka, terlihat bingung untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. “Tapi, kadangkala aku seperti tidak mengenalimu,” lanjutnya dengan kepala menunduk dalam. “Kadang kau begitu hangat, kadang sebaliknya.” Chao Xing menggigit bibirnya. “Maaf jika aku menyinggungmu,” tambahnya yang kemudian terpekik kaget karena Zian memeluknya erat.
“Kau harus bisa mengingatku, Chao Xing,” bisik pemuda itu penuh permohonan. “Kau harus bisa mengenaliku,” tambahnya parau. “Suatu hari nanti akan ada yang datang menjemputmu, dan jika saat itu tiba kau harus bisa mengenaliku. Apa kau paham?”
Chao Xing menggeleng di dalam pelukan Zian. “Apa maksudmu? Apa kau mau pergi lagi? Berapa lama?” tanyanya beruntun.
Zian tidak menjawab. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari dalam hanfu hitamnya, lalu meletakkan benda itu di telapak tangan mungil Chao Xing. “Simpan benda ini baik-baik, apa kau mengerti?”
Chao Xing tersenyum. “Jangan main-main lagi. Kau pasti sudah lapar, ayo kita masuk, Bibi Ju pasti sudah menyiapkan makan siang yang lezat untuk kita,” ujarnya riang.
Zian mengangguk pelan. “Kau masuklah lebih dulu, aku akan segera menyusulmu,” tukasnya pada Chao Xing yang lugu.
Chao Xing pun berbalik, berjalan menuju rumah sederhananya dengan hati riang gembira tanpa menyadari jika setelah ini ia akan berpisah cukup lama dengan Zian.
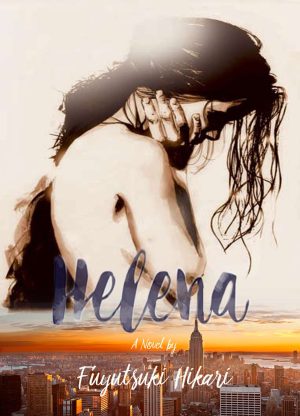
Helena (Bab. 1 Pertemuan Pertama)
1 Februari 2017 in Vitamins Blog
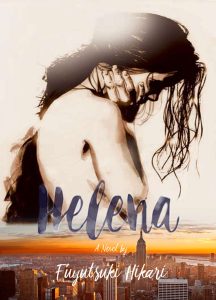
Selamat membaca! ^-^
***
Musim gugur, tahun 2015
Untuk sesaat kedua bola mata James membola saat seorang wanita cantik berambut pirang berjalan dengan ekspresi marah menuju meja yang tengah didudukinya. James mengelap mulutnya pelan menggunakan serbet, sementara wanita cantik berambut cokelat kemerahan di hadapannya terus bicara, tersenyum sensual, menatap penuh arti ke arahnya tanpa malu. James mengerti betul apa arti senyum serta tatapan yang dilempar ke arahnya—janji pergulatan panas di atas ranjang sepanjang malam.
Sayangnya pria berusia tiga puluh dua tahun itu harus rela mengesampingkan kebutuhannya karena saat ini ada hal yang jauh lebih penting yang harus dihadapinya—kemarahan Casandra.
Casandra, wanita cantik keturunan Spanyol itu terus berjalan dengan dagu terangkat, sementara suara hak sepatu tingginya teredam oleh karpet tebal yang diinjaknya. Kedua mata hijaunya berkilat, menyiratkan amarah yang sama sekali tidak bisa disembunyikannya. “Berani sekali kau menggoda kekasihku!!!” teriakan keras wanita berusia dua puluh sembilan tahun itu seketika menjadikan mereka pusat perhatian para pengunjung restoran.
Wanita berambut cokelat kemerahan yang menjadi teman kencan James hanya bisa mengerjapkan mata, terlihat bingung saat melihat Casandra berdiri menjulang di sampingnya. Dengan polosnya ia menatap James yang begitu tenang di atas tempat duduknya.
Ah, Paula mengerti, wanita berambut pirang itu pasti ingin mengklaim James sebagai kekasihnya? Enak saja! Pikirnya tidak terima. “James kekasih— argh…!!!” ucapan Paula terputus, digantikan oleh erangan serta jerit kesakitan. Wanita itu ditarik berdiri secara paksa membuatnya meronta, berusaha melepaskan diri dari jambakan Casandra yang sangat kuat. “Lepaskan aku!” pintanya terdengar seperti cicitan seekor hewan kecil di sarang pemangsa.
“Kau seharusnya berpikir seribu kali sebelum menggoda kekasihku,” desis Casandra tanpa melepaskan jambakannya. “Sekarang kau tahu dimana posisimu?” tanyanya pelan, penuh ancaman di telinga kanan Paula.
Paula mengerjapkan mata, rasa sakit akibat jambakan Casandra pada rambutnya membuat air matanya mengalir. Kalimat-kalimat kasar yang sudah siap meluncur dari bibirnya terpaksa ditelannya kembali. Dengan cepat Paula bisa menarik kesimpulan jika Casandra bukan lawan yang bisa dikalahkannya, karena itu dia memilih untuk mengalah mundur.
Walau demikian, Paula tetap berharap jika pria yang menjadi teman kencannya saat ini bisa membelanya, lalu mengusir wanita berambut pirang yang masih menjambak rambutnya dengan kasar. Sekilas ia melirik ke arah James, harapannya pupus. Pria itu sepertinya tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi. James sama sekali tidak berniat untuk membelanya, atau melerai untuk menghentikan pertengkaran yang tengah berlangsung.
Paula kembali menangis hebat, bukan hanya karena ulah Casandra, tapi juga karena sakit hati oleh sikap acuh James.
“Pergi! Dan jangan pernah memperlihatkan wajahmu lagi dihadapan James, atau aku akan membuat wajah cantikmu itu cacat untuk seumur hidup.”
Paula tidak menunggu lebih lama lagi, dengan wajah banjir air mata dia menyambar coat bulunya serta tas tangan bermerknya dari atas kursi. Wanita berusia dua puluh tahun itu menundukkan kepala dalam, berjalan dengan linangan air mata—keluar dari dalam restoran.
“Sikapmu terlalu berlebihan.” James buka suara sesaat setelah Paula pergi. Dengan tenang dan pelan dia menyesap anggur merahnya, sementara kedua manik abunya tidak lepas memperhatikan wajah cemberut Casandra yang kini duduk di sebrang mejanya.
“Kenapa kau membelanya?” suara Casandra berubah manja, terdengar merajuk. “Aku melakukannya karena tidak mau kau direbut oleh wanita mana pun. Kau kekasihku!” ujarnya mutlak. “Apa wanita itu lebih hebat di atas ranjang?” tanyanya marah. Wanita itu kesal, sangat kesal karena James masih bisa bersikap sesantai ini setelah apa yang terjadi.
Mendengar hal itu James terkekeh. Ia menyunggingkan senyuman memikat yang selama ini selalu berhasil menghipnotis wanita-wanita cantik berkelas naik ke atas ranjangnya untuk menghangatkan tubuhnya. “Kau tahu jika aku tidak pernah memiliki hubungan lama dengan wanita mana pun,” ujarnya santai. “Jadi, kenapa kau begitu terkejut saat aku berjalan dengan wanita lain?” tanyanya dengan satu alis terangkat, seolah pertanyaan yang dilontarkan oleh Casandra tadi merupakan satu pertanyaan bodoh.
“Tapi aku—”
“Kita akhiri,” potong James cepat. “Kita akhiri hubungan kita.”
Casandra membuka mulutnya, lalu merapatkannya kembali. James pasti sedang bercanda, kan? Pria itu tidak mungkin memutuskannya seperti ini. Lagipula hubungan romantis mereka baru berlangsung dua minggu. Jadi, rasanya mustahil jika James memutuskannya begitu cepat.
“Aku tidak suka diatur-atur oleh wanita,” lanjut James tanpa beban.
“Aku bisa berubah,” sahut Casandra dengan nada penuh permohonan, tangannya terulur mencoba menggenggam tangan James, namun sayangnya pria itu segera menarik kedua tangannya.
Sejujurnya, Casandra sudah muak memacari pria-pria paruh baya berperut buncit demi uang, karena alasan itulah dia tidak bisa melepaskan James. Tidak bisa. Selain tampan dan muda, James juga berdompet tebal. “Kumohon, jangan mengakhirinya. Kau bisa mengencani wanita mana pun, tapi jangan akhiri hubungan kita,” katanya memelas.
James kembali mengulum senyum, mengeluarkan selembar cek kosong dari saku jas armani-nya ke atas meja lalu menyodorkannya kea rah Casandra. “Isi berapa pun yang kauinginkan.”
Casandra membisu, menatap nanar selembar cek kosong yang disodorkan ke arahnya. Kehidupan mewahnya untuk satu tahun ke depan bisa terpenuhi oleh selembar kosong itu, namun setelahnya dia harus mencari pria kaya lain untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah? Tidak. Lebih baik dia berpura-pura menolak cek kosong itu, lalu memohon James untuk tidak mengakhiri hubungan mereka. Air mata pasti bisa meluluhkan pendirian James, pikirnya sangat yakin.
“Aku tidak menginginkan uang,” ujarnya dengan air mata berlinang. “Aku hanya menginginkanmu,” tambahnya parau.
James mendengus, tersenyum mengejek. Casandra bukan wanita pertama yang berpura-pura menolak cek yang ditawarkannya. Wanita-wanita itu pasti akan merajuk, menggodanya untuk naik ke atas ranjang dan berharap ia luluh oleh godaan yang mereka lancarkan. Tapi tidak, James bukan tipe pria yang akan menjilat air liurnya sendiri. Ucapan yang sudah dikatakannya adalah mutlak.
“Jangan berpikir terlalu lama, Cass, ambil dan gunakan uang yang kutawarkan. Aku tahu kau menginginkannya,” ucap James sebelum bangkit dari kursinya sesaat setelah seorang pelayan mengembalikan kartu kredit yang digunakannya untuk membayar tagihan makan malamnya.
Hal terakhir yang diinginkan James malam ini adalah suara tangisan histeris Casandra yang terus mengikutinya hingga keluar restoran. James memasang ekspresi datar, menatap lurus wanita berambut pirang yang kini memeluknya erat, terlihat enggan untuk melepaskannya. “Aku akan berubah!” janji Casandra di dalam pelukan mantan kekasihnya. “Aku tidak akan cemburu jika kau berkencan dengan wanita lain. Aku tidak akan keberatan jika kau berkencan dengan wanita lain, asal kau berjanji jangan menjadikan mereka wanitamu. Hanya aku yang boleh menjadi kekasih resmimu.” Wanita itu terisak, sementara air matanya membasahi jas mahal berwarna hitam yang dikenakan James.
James menarik napas, mencoba untuk mengendalikan emosinya yang mulai menjalar hingga ubun-ubun.
“Sulit bagiku membayangkan hidup tanpamu,” kata Casandra lagi, membuat James memutar kedua bola matanya malas.
Casandra hanya tidak bisa membayangkan hidup tanpa uangku, pikir James miris. Wanita-wanita yang dikencaninya selama ini hanya menginginkan uangnya, sementara dirinya hanya membutuhkan tubuh wanita-wanita itu untuk menghangatkan ranjangnya. Bukankah itu hubungan yang sama-sama menguntungkan?
James kembali mengumpat di dalam hati, urusannya dengan Casandra belum usai dan sekarang dia harus berhadapan dengan wanita lain yang tengah mengambil gambar ke arahnya? Wanita itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan dirinya seperti fotografer majalah-majalah gossip yang selama ini membuntutinya. Wanita itu sangat berani—secara terang-terangan dia mengambil gambar, lalu menundukkan kepala untuk mengecek hasil jepretannya sebelum akhirnya membalikkan badan, berjalan cepat dan berbelok di ujung jalan.
“Brengsek,” umpatnya kasar. James tidak bisa berpikir jernih, yang ada di dalam pikirannya adalah merebut kamera milik wanita sialan itu. Dengan kasar ia menyentak tubuh Casandra, melepaskan pelukan wanita berambut pirang itu secara paksa. James hanya menatap dingin wanita di hadapannya yang menangis semakin menjadi, mengabaikannya sebelum berlari dengan cepat untuk mengejar wanita yang dengan kurang ajarnya telah mengambil fotonya bersama Casandra.
Di dalam pikirannya pria berambut gelap itu sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak berhasil merebut kamera sialan itu—foto dirinya dengan Casandra tadi pasti akan memenuhi bagian depan majalah-majalah gosip dengan judul yang hanya akan menyudutkannya. Atau mungkin wanita itu akan memerasnya demi sejumlah uang. Brengsek! Makinya di dalam hati.
***
Helena terus berjalan sambil menenteng kamera DSLR-nya, sesekali ia berhenti berjalan, mengambil beberapa gambar, mengeceknya sebelum akhirnya kembali berjalan untuk mencari objek lain. Kota New York terlihat lebih hidup saat malam menyapa, pikirnya. Helena mendongakkan kepala, menatap layar-layar besar yang menghiasi gedung-gedung di wilayah Time Square. Selalu terlihat menakjubkan, pikirnya.
Wanita berusia dua puluh lima tahun itu merapatkan coat panjang coklat yang dikenakannya saat angin akhir musim gugur berhembus membawa serta angin musim dingin bersamanya. Saatnya pulang, pikirnya setelah melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya, ia baru saja akan melangkah saat sebuah tangan besar menyentak kasar bahunya, menahan langkahnya dan memaksa tubuhnya untuk berbalik.
“Di sini kau rupanya!”
Nada kasar pria asing dihadapannya itu membuat Helena menekuk keningnya bingung. Bukankah yang seharusnya marah saat ini adalah dirinya? Pikir Helena geram. Lalu kenapa pria asing di hadapannya itu terlihat sangat marah, seolah-olah Helena sudah mencuri mainan kesayangannya. “Apa yang kau lakukan?” protesnya saat James mengambil paksa kamera di tangannya.
Rahang James mengeras, pria itu menatap sinis ke arah Helena yang terlihat bingung dan jengkel secara bersamaan. “Kenapa? Kesal karena aku mengambil sesuatu yang akan menjadi pundi-pundi uangmu?” oloknya kasar.
Helena menggigit bagian dalam mulutnya, menahan diri untuk tidak menjerit dan melontarkan kalimat-kalimat kasar ke arah pria yang menatapnya rendah. “Kembalikan, atau aku akan berteriak—”
“Silahkan,” potong James dengan nada mencela. “Wanita sepertimu hanya bisa memanfaatkan kelemahan orang lain untuk menghasilkan uang,” ejeknya membuat gigi Helena gemertuk karena marah. James menyempitkan mata, menatap sosok Helena penuh penilaian dari ujung kaki hingga ujung kepala. Cantik, pikirnya masam. “Apa kau tidak bisa mencari pekerjaan lain selain mengambil foto orang lain untuk memerasnya?”
Helena mengerjapkan mata. Semakin bingung dan marah. Pria dihadapannya ini pasti sedang bergurau. Memeras apa? Dia sama sekali tidak mengenal pria di hadapannya ini. Dan untuk apa dia memerasnya? “Kau salah orang. Aku tidak mengenalmu—”
“Yeah… yang benar saja!” ejek James memotong ucapan Helena dengan sinis. Pria itu mencondongkan wajahnya, mengikis jarak diantara mereka. “Alasan yang kau katakan sangat konyol, Nona. Tidak mengenalku, huh?” tanyanya yang terdengar seperti sebuah ejekan lain di telinga Helena.
Demi ibu angkatnya yang telah tiada, Helena bersumpah jika dia sama sekali tidak mengenal pria di hadapannya ini. “Jangan bergurau, Tuan,” balasnya dingin. “Aku tidak mengenalmu dan tidak ingin mengenalmu. Kurasa kau tidak seberharga itu untuk kukenal,” tambahnya membuat James kembali berdiri dengan tegak, sementara satu alisnya naik menatap Helena dengan terkejut.
James menjilat bibir bawahnya, sementara matanya kini tertuju lurus pada bibir penuh milik Helena. Bibir yang membalas pedas itu pasti akan terasa manis dalam pagutannya.
Brengsek! Umpatnya di dalam hati. Kenapa hasratnya mendadak muncul hanya dengan memandang bibir penuh wanita asing di hadapnnya? Otaknya bahkan mulai membayangkan bagaimana wanita itu menggeliat nikmat di dalam kungkungan tubuh telanjangnya, menikmati pergulatan panas mereka di atas ranjang.
Sialan! Kenapa aku malah membayangkan bercinta dengan wanita ini? Pikir James masam.
“Kembalikan kameraku!” bentak Helena memutus lamunan singkat James. Pria itu segera menyembunyikan kamera milik Helena di belakang punggungnya saat wanita itu berusaha merebut kamera di tangannya. “Kembalikan atau aku akan berteriak.”
“Teriak saja,” sahut James santai, seolah menganggap ancaman Helena seperti angin lalu. “Aku akan mengembalikannya setelah menghapus fotoku yang sudah kau ambil tanpa ijin.”
Helena mengangkat kedua tangannya tanda kebingungan. “Bagaimana lagi aku harus menjelaskannya padamu?” tanyanya mulai frustasi. “Aku tidak mengambil fotomu. Untuk apa aku melakukannya?” tambahnya dengan suara tertahan. Sungguh, ia sudah sangat lelah. Seharian ini dia berkeliling kota, mengabadikan beberapa objek dalam jepretan kameranya. Rasanya yang diinginkannya sekarang adalah segelas cokelat panas lalu bergelung di balik selimut hangatnya, bukan pertengkaran konol dengan seorang pria asing yang tidak dikenalnya.
James mengangkat sebelah bahunya, terlihat tidak peduli. “Aku akan memastikannya sendiri,” jawabnya tenang. “Dan jika aku mendapati fotoku di dalam kameramu ini.” Ia berhenti sebentar, mengangkat kamera di tangannya ke hadapan Helena. “Jika aku mendapati satu fotoku di dalam kameramu ini, maka aku akan pastikan kau akan menghadapi kuasa hukumku atas tuduhan pemerasan,” ancamnya membuat Helena terbelalak tak percaya.
“Apa maksudmu?”
“Jangan memasang ekspresi lugu, Nona.” James bersedekap, menatap Helena dengan ekspresi mencemooh. Namun otaknya berseru keras, mengatakan jika ia bisa memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya. “Kita akhiri pertengkaran konyol kita sampai di sini,” tegasnya kemudian membuat Helena memutar kedua bola matanya malas.
Bukankah dia yang mengawali pertengkaran konyol ini? Pikir Helena geram.
“Jika kau menginginkan kameramu, datang dan ambil sendiri!” tambahnya. James berhenti sejenak, memasang pose berpikir, “Ah, aku lupa. Kau tidak mengenalku bukan?” ia lagi-lagi menyunggingkan senyuman mengejek. “Kau bisa mencariku di sini,” katanya setelah menyerahkan sebuah kartu nama yang diambilnya dari dalam saku jasnya ke tangan Helena.
.
.
.
TBC
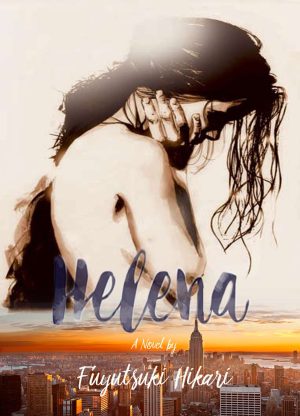
Helena
16 Desember 2016 in Vitamins Blog
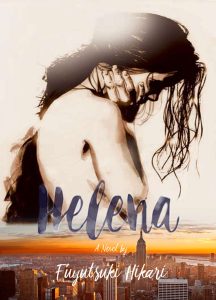
Prolog
***
“Kenapa kau tidak mati saja?!” teriak Rowena menggema di dalam ruang tamu apartemen sempit yang sudah tiga tahun ini ditempatinya. Suaranya memecah keheningan pekat di dalam ruangan itu, sementara di luar hujan turun semakin derasnya.
Rowena terus melayangkan sabuk kulitnya ke tubuh Helena yang kini meringkuk di atas karpet abu kusam. Tubuh kecilnya sudah tidak mampu digerakkannya walau telinganya masih bisa mendengar dengan baik setiap kalimat menyakitkan yang meluncur dari mulut ibunya.
“Seharusnya aku tidak mendengarkan ucapan orangtuaku dan tetap membunuhmu saat kau masih di dalam kandunganku!” raung Rowena membuat jantung Helena untuk seperkian detik serasa berhenti berdetak.
Gadis kecil itu masih belum tahu alasan mengapa ibu kandungnya begitu membencinya. Mengapa Rowena memperlakukannya dengan kasar padahal Helena selalu berusaha menjadi anak baik dan penurut.
Helena bahkan tidak pernah sekali pun membantah ucapan ibunya, namun sepertinya hal itu masih belum cukup membuat Rowena puas dan menyayanginya.
Rowena kembali melayangkan pukulannya, kali ini tepat mengenai betis kanan Helena, meninggalkan jejak warna merah yang mengerikan di atas kulit putih putrinya.
“Bagaimana bisa aku mencintai anak dari pria yang sudah memperkosaku?” Jerit Rowena mengeluarkan isi hatinya yang selama delapan tahun ini disimpannya rapat di dalam hati.
“Keberadaanmu mengingatkanku padanya. Pada ayahmu yang brengsek itu, Helena!” jeritnya lagi begiru frustasi.
Ya. Helena memang selalu mengingatkan Rowena akan pria yang sudah memperkosanya. Pria itu dengan liciknya menjebaknya, lalu memperlakukannya seperti seorang pelacur murahan dengan memberi Rowena selembar cek kosong keesokan paginya. “Isi berapa pun yang kau inginkan,” ujar pria itu yang hingga saat ini masih diingat jelas oleh Rowena.
Helena terdiam. Tubuhnya terasa kaku, kepalanya terasa mau meledak. Sekarang akhirnya dia tahu alasan mengapa ibunya begitu membencinya. Kini dia tahu kenapa ibunya acap kali memukulinya; karena ia mengingatkan ibunya pada sosok ayahnya.
Ironis, pikir Helena pahit. Bukankah ia juga tidak pernah mengharapkan untuk dilahirkan sebagai anak hasil perkosaan. Lalu kenapa ibunya melampiaskan kemarahaan serta rasa frustasinya pada Helena? Sungguh hal itu tidak bisa dimengerti oleh Helena kecil.
“Mati! Mati kau Helena!!!” raung Rowena tanpa belas kasih. Alkohol mempengaruhinya dengan kuat saat ini. Dendam terhadap pria yang sudah memperkosanya dilimpahkannya pada Helena yang sesungguhnya sama sekali tidak berdosa. “Mati kau, Helena! Setelah itu aku akan mati menyusulmu!” teriaknya keras, penuh amarah.
“Apa yang kau lakukan?!” bentak Tuan Brown yang terpaksa masuk ke dalam apartemen milik Rowena setelah mendengar jeritan serta suara keras wanita itu dari balik tembok tipis yang menjadi sekat antara satu ruang dengan ruang apartemen milik keluarga lainnya. “Kau akan membunuh putri kandungmu sendiri?” tambahnya seraya menepis tangan Rowena yang masih terus melecutkan sabuk kulitnya ke tubuh putrinya. “Nyonya Rowena?!” bentak pria paruh baya itu keras, berusaha untuk menyadarkan tetangganya itu.
Sungguh, Brown sama sekali tidak menyangka jika tetangga manisnya bisa berbuat sekeji ini pada putri kandungnya sendiri.
Brown segera membawa tubuh Helena yang tergeletak tak berdaya ke dalam gendongannya, membawanya keluar dari dalam apartemen sederhana itu dengan cepat. Pria itu mengabaikan jerit protes Rowena yang meminta putrinya dikembalikan.
“Helena harus mati!” di puncak anak tangga samar Brown masih bisa mendengar suara Rowena. Pria itu tidak peduli, yang harus dicemaskannya saat ini adalah keselamatan Helena dan memisahkan anak di dalam gendongannya ini dari ibunya yang ternyata sakit mental. “Tenang, Nak. Kau akan baik-baik saja,” janji Brown pada Helena kecil yang sudah tak berdaya.
Dan malam itu, adalah malam terakhir Helena melihat ibunya, sebelum kemudian secara mengejutkan ia kembali bertemu setelah berpisah selama tujuh belas tahun lamanya.

 (396 votes, average: 1.00 out of 1)
(396 votes, average: 1.00 out of 1)