
Diana’s Marriage
9 Februari 2017 in Vitamins Blog
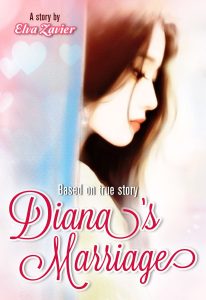
Diana kembali menyesap gelas kedua Mocha Lattenya. Duduk di sudut ruangan, menatap jendela kaca besar dengan pemandangan manusia yang sibuk berlalu lalang dengan segala aktifitasnya. Diliriknya arloji silver di pergelangan kirinya yang sudah menunjuk angka 4 tepat. Diana menghela nafas, sudah lebih dari satu jam ia menunggu disini. Satu jam yang ia sia-siakan untuk menunggunya.
Pria itu masih tetap sama, mulut dan perbuatannya tak pernah sejalan. Diana tentu masih ingat apa yang semalam pria itu ucapkan dalam pesan singkatnya.
‘Kita bertemu jam 3 sore, kau tau kan aku tidak suka menunggu.’
Setiap barisan huruf yang ia ketik mencerminkan dirinya yang arogan dan tak terbantahkan. Memang begitulah dirinya, diktator dan tak mau kalah. Setiap perkataannya ibarat titah raja, berani membantah maka sebuah tamparan menantimu.
Hidup ini kejam, tapi pria itu lebih kejam. Lima tahun kebersamaan mereka, sedikit kebahagiaan yang dirasakannya. Lima tahun Diana harus rela kebebasannya sebagai seorang wanita terenggut. Ia harus bermain kucing-kucingan hanya untuk bertemu keluarganya, bahkan ia rela membuang kedua sahabat yang selama ini selalu bersamanya sejak mereka masih berseragam putih abu-abu.
Sengajakah ia? Tentu saja tidak. Semuanya karena Diana tak memiliki pilihan.
Tapi kini Diana punya pilihan. Untuk bertahan tapi terus disakiti, atau pergi dengan harapan menggapai kebahagiaan baru yang telah lama dinantikannya.
Pria itu berdiri di depannya, dengan setelan polo shirt putih yang dilapisi jaket denim warna abu-abu dan celana jeans belel biru tua. Pria itu masih terlihat menawan seperti biasa, tapi tampilannya di luar berbanding terbalik dengan sifatnya. Diana menggambarkan pria itu seperti malaikat bersayap iblis.
“Maaf terlambat, kau tau jam pulang kerja jalanan selalu macet.” Alasan klasik. Tapi Diana memilih mengabaikannya. Lima tahun hidup bersama pria itu membuat Diana mengenalnya luar dalam. Pria itu tak pernah menghargai waktu.
Pria itu mendudukkan tubuhnya di kursi di depannya. Lalu menatap Diana penuh arti. Diana tahu arti tatapan itu. Wajah memelas dengan keinginan merajut kembali tali yang sudah setengah putus. Diana bodoh jika terpedaya, berani bertaruh beberapa menit ke depan wajah itu akan berubah menjadi tokoh Shan Yu dalam film animasi Mulan yang sering ditonton Ara.
Adrian. Itu namanya. Orang yang pernah ia cintai sepenuh hati, walau dalam kesakitannya menanggung segala perlakuan kasar darinya.
“Aku tetap pada pendirianku. Aku harap mas tidak lagi memperlambat prosesnya.” Diana tidak ingin berbasa basi, selain sudah bosan karena terlalu lama menunggu, Diana juga muak menatap wajah pria itu.
Diana menatap tegas ke arah manik mata pria itu, seolah menegaskan kini ia bukan lagi seorang istri yang diperlakukan seperti budak yang harus tunduk pada tuannya. Diana hanyalah seorang wanita yang ingin meraih kebahagiaannya. Meskipun itu dengan jalan memutus jalinan suci yang selama ini mengikat keduanya.
“Kau egois! Kau lupa kita memiliki Ara?”
“Tentu aku masih ingat. Justru ini kulakukan karena aku menyayangi Ara, juga diriku sendiri.”
“Cih, menyayangi Ara katamu?” Adrian berdecak. “Menjadikan anakmu tumbuh di tengah keluarga broken home, itu yang kau bilang menyayangi?” Adrian tersenyum mengejek.
Diana memiringkan kepalanya, menatap Adrian lekat. “Menurut mas definisi broken home itu hanya sebatas perceraian? Tidakkah pemikiran itu terlalu picik?” Terdiam sejenak, Diana kembali menyesap Mocha Lattenya yang tersisa separuh. “Yang jelas aku tidak akan mempertaruhkan perkembangan mental putriku hanya demi mempertahankan pernikahan kita. Sudah cukup dia melihat perlakuan mas padaku selama ini. Aku ingin membesarkannya di lingkungan yang penuh dengan kasih sayang.”
Bibir Adrian menipis mencoba menahan amarahnya yang mulai berkobar, bola matanya menatap nyalang pada mata jernih Diana. Sejak kapan istrinya yang rapuh dan penurut ini berubah menjadi wanita yang pandai bermain kata-kata.
“Kau hanya menuruti kedua orang tuamu. Disini aku suamimu, aku yang lebih berhak atas dirimu. Bukannya mereka!” Diana bisa melihat kilatan amarah yang mulai membara di mata Adrian. Kilatan yang dulu membuatnya gentar, tapi tidak dengan sekarang. Pengalaman mengajarkannya segala hal. Bukan takut lagi yang kini ia rasakan, tapi lebih kepada rasa muak.
“Kalau aku kembali padamu, apa yang bisa kau janjikan untuk kami? Apa kau bisa menjamin kau tidak akan menyakiti kami lagi?”
“Tentu saja!”
Diana mengangkat sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. “Kau lupa, kau menjanjikan hal yang sama setahun yang lalu, bahkan di tahun sebelumnya, dan sebelumnya lagi?” Diana menghela nafas berat. “Lalu apa? Mulutmu hanya bisa berjanji.”
Adrian masih terdiam, mungkin salah satu sudut kecil dari hatinya membenarkan ucapan Diana. Adrian berusaha menurunkan sedikit egonya yang setinggi menara Eiffel itu, misinya hari ini ia harus berusaha membawa kembali istrinya.
“Sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar khilaf saat itu. Aku hanya ingin kau menurutiku, tapi kau selalu membantah ucapanku. Kau tahu kan aku paling tidak suka dibantah.” Diana mendengus. Inikah yang disebut minta maaf jika ujung-ujungnya semua kesalahan bermuara pada dirinya?
“Boleh aku bertanya satu hal, mas?”
“Apa?” Adrian menatap lekat manik kecoklatan Diana, menanti pertanyaan yang akan dilontarkan padanya.
“Pernahkah kau mencintaiku, mencintai Ara?”
“Kenapa kau menanyakan hal yang kau sudah tahu pasti jawabannya?” Adrian mendengus kesal. “Kalau aku tidak mencintaimu untuk apa aku repot-repot kemari menemuimu dan mengemis untuk kembali rujuk denganmu. Masih banyak hal yang bisa kulakukan.”
Diana tertawa sinis. Ternyata pria ini masih suaminya yang arogan. Ingin sekali Diana mengatakan padanya jika benar ia mencintai Diana, maka tak akan ada tamparan. Jika ia mencintai Diana, ia pasti akan bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, bukannya memaksa istrinya bekerja di luar menjadi seorang sales girl yang menjajakan rokok dengan pakaian serba ketatnya sementara dirinya duduk berdiam diri di rumah menanti hujan uang dari langit. Dan jika ia mencintai Diana, maka kata-kata ‘menikah denganmu membuat hidupku susah!’ tak akan pernah keluar dari mulutnya.
Dan Diana membiarkan kata-kata itu hanya terkubur dalam hatinya. Bukan ia takut mengkritik, hanya ia sudah tak ingin lagi terlalu lama berdekatan dengan Adrian. Sudah cukup untuk hari ini.
“Aku sudah tidak sanggup lagi, mas. Dan aku tetap pada keputusanku untuk bercerai.” Ujar Diana. Mendengarnya Adrian kembali meradang.
Brakk!
Adrian menggebrak meja, hingga gelas kopi yang dipesan Diana hampir terjatuh jika saja Diana tidak dengan cekatan meraihnya. Tatapan mata Adrian kembali nyalang, rahangnya mengeras menahan amarahnya.
“Jangan pernah bermimpi, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu!” Ucap Adrian penuh penekanan. “Kau dengar itu? Tidak akan pernah!”
Beberapa pasang mata menatap mereka penuh tanya. Bagus. Kini mereka menjadi bahan tontonan para pengunjung café. Diana ingin sekali menutup wajahnya karena malu.
“Kau dan orang tuamu sama saja, sama-sama pecundang!”
Dengan amarah yang meluap, Adrian meninggalkan Diana yang masih mematung di tempatnya. Adrian berjalan dengan langkah lebarnya keluar dari café, mengabaikan beberapa pasang mata yang masih keheranan menatapnya.
Diana menarik nafas dalam hingga memenuhi seluruh rongga dalam paru-parunya lalu menghembuskannya perlahan. Ternyata ini tak semudah yang ia duga, berbicara dengan pria yang masih berstatus suaminya memang bukan hal mudah. Mungkin benar kata beberapa orang terdekatnya, ia harus bersabar. Diana masih bersyukur, setidaknya Adrian tidak membuat keributan seperti halnya di rumah orang tuanya sebulan yang lalu. Dimana ia mengamuk sambil berteriak seperti orang kesetanan di halaman rumah orang tuanya. Hingga jendela kaca rumah ibunya pun menjadi sasaran amukan Adrian kala itu.
Diana meraih handbagnya, mengeluarkan selembar uang lima puluh ribuan dari dalam dompetnya lalu ia letakkan di atas meja.
Menarik kedua sudut bibirnya, Diana mulai melangkah dengan percaya diri. Membuka pintu kaca itu seolah membuka segel rantai yang selama ini membelenggunya. Meski belum sepenuhnya terbebas dari suaminya, tapi setidaknya Diana bisa masih bisa menghirup udara luar.
Diana menatap gumpalan awan yang kian hitam. Mendung mulai bersiap-siap untuk menjatuhkan titik-titik airnya. Ia harus bergegas. Dengan langkah yang dipercepat, ia harus segera menghampiri Ara yang saat ini tengah ia titipkan pada kedua sahabatnya.
Setelah berjalan selama kurang lebih 15 menit dari cafe menuju taman kota, dari kejauhan Diana melihat Ara tengah bermain kejar-kejaran dengan Axel diiringi tawa lebarnya. Sementara dua orang wanita nampak berbincang sambil sesekali tertawa terbahak-bahak. Diana hanya menggeleng, kedua sahabatnya ini tak pernah berubah.
Diana berjalan menghampiri mereka dengan memasang senyum terindahnya.
“Hai, maaf menunggu lama.” Seketika kedua orang itu meliriknya dengan tatapan horornya. “Kenapa menatapku begitu?” Diana nyengir kuda, menunjukkan kedua gigi kelincinya tanpa rasa bersalah.
“Lama sekali, kau tidak bermesraan dulu dengannya, kan. Dan membiarkan sahabatmu menjadi pengasuh anakmu?” Kali ini wanita bersurai panjang hitam dengan mata sipit memicing ke arahnya.
Diana terkekeh geli. “Ihh, malas.”
“Sekarang malas, dulu saja kau cinta mati. Sampai-sampai mengabaikan sahabatmu.” Sindir Liza, si gadis mungil keturunan Arab itu memicing ke arahnya.
“Iya… iya maaf.” Diana memasang wajah sendu andalannya. “Kalian tahu, aku hanya berbicara 10 menit dengannya setelah menunggunya lebih dari satu jam. Pria itu sungguh menyebalkan.” Diana mendengus kesal.
“Lalu bagaimana?” Tanya Elva dan hanya dijawab dengan gelengan pelan oleh Diana. Disampingnya, Liza juga memasang wajah penuh simpati. Sudah tahu bahwa usaha Diana untuk mempercepat proses perceriannya kembali gagal.
“Dia tidak membuat keributan kan?” Tanya Liza.
“Sedikit.”
“Sudahlah, tidak apa-apa. Kamu harus sabar. Setidaknya sekarang kamu bukan tahanan rumah lagi, kan.” Ujar Elva menenangkan, meski dalam hati ia juga kesal dengan pria bernama Adrian itu.
“Si Adrian itu maunya apa sih, lama-lama aku meradang melihat wajah tengilnya. Aku berharap bisa melemparnya ke kandang buaya.” Liza bersungut-sungut, membuat Elva terkekeh geli, sementara Diana mengangguk mengamini niat brutal sahabatnya itu.
Sejak ia mulai berpisah dengan Adrian, Diana mulai menghubungi kembali sahabat-sahabatnya. Ia ingin menyimpul mati tali persahabatan mereka yang sempat putus. Diana tidak banyak berharap mereka bisa kembali bersahabat layaknya saudara seperti dulu lagi, Diana hanya ingin mereka memaafkannya, ia juga ingin menjelaskan tentang segala hal yang terjadi dengannya selama ini, semua yang terjadi diluar keinginannya.
Dan betapa Tuhan sungguh murah hati, kedua sahabatnya menerimanya dengan tangan terbuka. Dan kini mereka selalu ada untuknya, menerima segala keluh kesahnya. Setidaknya dengan semua itu bisa meringankan sedikit beban hidupnya.
“Wahahahahahaha!”
Diana dan Elva seketika menatap Liza yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menatap layar smartphonenya. Kedua orang itu saling berpandangan aneh melihat sahabat termungil mereka terpingkal-pingkal dengan air mata yang mengalir di sudut matanya.
“Kurasa bukan hanya suamimu yang menggila, temanmu yang satu itu juga mulai tidak waras.” Elva menunjuk ke arah Liza dengan dagunya. Diana tersenyum kaku.
“Lihat, lihat. Suamimu update status, Dy.” Ujar liza bersemangat sambil menunjukkan layar ponselnya yang tengah membuka halaman jejaring sosial facebook, menampilkan profil dari Adrian.
Elva tak bisa menutupi rasa penasarannya, ia meraih ponsel Liza dan melihat apa lagi kali ini yang ditulis oleh suami Diana itu.
Sedetik kemudian, Elva tak bisa membendung tawanya. Membaca kata demi kata yang terangkai indah yang ditulis Adrian di profile facebooknya.
Bisakah aku mengatakan sore ini adalah yang terindah? Aku rela meski harus datang satu jam lebih awal, itu karena aku begitu tidak sabar untuk segera bertemu denganmu dan bisa melihat senyuman indahmu lagi. Terima kasih sudah hadir untukku, jangan sampai kedua tangan yang sudah bertautan ini terlepas lagi. Kita hadapi ini bersama, meski restu orangtuamu tak lagi kita genggam. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Aku mencintaimu istriku, Diana.
“Ini sungguh menggelikan, Za. Pria ini sungguh berlebihan dan pembohong besar. Astaga Didy… kau pungut dimana suamimu ini?” Elva menggeleng dramatis.
“Kurasa dia lebih cocok jadi aktor, Dy.” Ujar Liza dengan kekehan gelinya. “Dia begitu pintar mencari simpati.”
Diana tersenyum masam. “Kurasa dia harus periksa kejiwaan, padahal jelas-jelas aku yang menunggu sampai bosan tadi.” Ekspresi cemberut Diana tentu saja mengundang tawa kedua sahabatnya.
“Huuwaaa!!!”
Terdengar suara tangisan dari arah depan mereka, arah tempat kedua bocah yang tadinya bermain kejar-kejaran. Axel tersungkur di atas tanah sambil menangis, sepertinya ia baru saja terjatuh. Dengan cepat Elva berlari menghampiri putranya.
“It’s ok, baby.” Elva meraih bocah laki-laki itu lalu menepuk-nepuk bajunya yang terlihat kotor, mengamati sekujur tubuh Axel untuk melihat apakah ada luka yang serius, ternyata hanya lututnya saja yang sedikit tergores. “Laki-laki tidak boleh cengeng, hmm?”
Elva meniup-niup luka di lutut Axel. “Sakit, nda.” Rengeknya manja. Elva meraih bocah empat tahun itu dalam gendongannya. Sementara di sebelahnya Ara terdiam menatap Axel yang tengah menangis. Tatapan matanya seolah mengatakan ‘aku tidak memukulnya,’
“Apa ada yang luka?” Tanya Diana khawatir.
“Hanya sedikit lecet.” Jawab Elva. Ia kemudian membisikkan sesuatu kepada anaknya. “Axel mau eskrim? Tante Liza mau belikan Axel dan Kak Ara eskrim.” Dan berhasil, tangis Axel berhenti digantikan dengan senyuman lebarnya.
Axel menggeliat ingin diturunkan dari gendongan bundanya, lalu berlari ke arah Liza. Axel meraih tangan Liza dengan semangat. “Ayo tante, Axel mau yang rasa coklat.”
“Coklat?” Liza mengernyit tak mengerti, kenapa bocah laki-laki yang sedetik lalu ini menangis kencang tiba-tiba tersenyum cerah ke arahnya sambil berkata rasa coklat.
Rasa coklat? Jangan bilang …
Axel mengangguk lucu. Ia menatap Liza dengan tatapan polosnya. “Kata Bunda, Tante Liza mau belikan eskrim buat Axel dan Kak Ara.” Liza memejamkan matanya sejenak kemudian menatap horor ke arah Elva yang tengah terkikik geli.
“Elva, awas kau!”
*** FIN ***
Cerita pendek nan geje ini aku persembahkan buat sahabatku tercinta, Diana. Semoga segala proses untuk gugatannya diberi kelancaran. Amin.
Aneh ya, mengaku sahabat tapi mendukung perceraian sahabatnya sendiri? Awalnya aku dan Liza juga menyarankan apakah tidak bisa diperbaiki lagi, mereka punya anak yang masih butuh kasih sayang kedua orangtuanya. Tapi apa daya, melihat penderitaannya selama ini karena memiliki suami dengan tempramen tinggi membuat kami berdua sebagai sahabat hanya bisa mendukung segala keputusan yang sudah diambil Diana.
Alur cerita ini hanya fiksi, tapi beberapa deskripsi di dalamnya adalah realita. Bagaimana si Adrian (nama samaran, gak mungkin pakai ‘codet’ kaya penjual bakso borax) begitu tempramen dan pemarah sebagai suami, tapi bersikap alay dan sok ustad jika di medsos. Dia merasa segala tindak kekerasan yang dilakukannya pada istri dan anaknya memiliki sebab dan alasan.
Aku juga punya suami, tapi dia tak pernah memperlakukanku seperti samsak tinju. Bapakku juga, selama 30 tahun usia pernikahan emak dan bapak, tak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi pertanyaannya, jika orang lain bisa kenapa kita tidak? Apakah kekerasan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga?
Padahal menilik sifat dari Diana ini, dia adalah pribadi yang kalem nan lemah lembut. Berbeda 180 derajad dibandingkan aku dan Liza. Dan jika ia sampai mengalami tindak kekerasan seperti itu, sedikit banyak kami berdua sebagai sahabat merasa ini sungguh tidak adil.
Tapi semua keputusan kembali kami serahkan kepada sahabat bungsu kami tersayang. Apapun keputusannya kita pasti mendukung sepenuh hati. Apakah tetap bertahan ataukah harus berpisah, semoga jalan yang diambil adalah yang terbaik. Untuk Diana sendiri juga untuk putrinya.
Semangat Didy! Fighting! Ganbatte!!!!! :D
Simpan
Simpan

 (149 votes, average: 1.00 out of 1)
(149 votes, average: 1.00 out of 1)